Opini
Identitas di Ujung Lidah
Published
2 months agoon
By
Mitra Wacana

Mareta Naza Yuana Dewi merupakan mahasiswa program studi Tadris (Pendidikan) Bahasa Indonesia Fakultas Adab dan Bahasa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Koridor kampus yang kerap kali ramai mahasiswa berlalu-lalang, angkringan hingga warmindo-warmindo sekitar kampus yang ramai di kunjungi mahasiswa, entah untuk mengerjakan tugas bersama ataupun hanya untuk nongkrong santai, disanalah mereka berbincang tentang banyak hal. Disana juga berbagai bahasa seolah bercampur, dengan logat mereka yang juga beragam. Meskipun masih seputar Jawa, penggunaan bahasa rupanya juga memiliki perbedaan yang kontras, sekalipun mereka yang tinggal di perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Adapun yang lebih unik lagi ketika seorang mahasiswa asal Jabodetabek dengan logatya yang kental berdialog menggunakan bahasa Jawa, tak jarang mencampur aduk kan bahasa. “Horok ra iso gua ngerjain tugase, susah banget,” ucap mahasiswa pendatang dengan mengusap kepalanya kasar, di sisi lain, teman asal Solo menimpali dengan logat Jawa nya “ho’i to, gua juga mumet tenan, coy” Fenomena ini mungkin hanya hal sepele, tapi menarik jika dicermati. Apakah percampuran bahasa dan logat ini menandakan bentuk toleransi linguistik antardaerah, atau justru lunturnya identitas kebahasaan.
Soloraya meliputi beberapa kota namun, Surakarta dan Sukoharjo menjadi kota yang sering di datangi mahasiswa perantau, setiap tahunnya menjadi magnet bagi ribuan mahasiswa pendatang dari berbagai daerah. Dalam lingkungan kampus, kos, warmindo, maupun angkringan yang kerap menjadi tempat singgah mereka, dan tentunya berbincang banyak hal mencerminkan sebuah fenomena menarik: logat dan bahasa bercampur. Mahasiswa perantau yang datang dari berbagai daerah, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta dan sekitarnya, hingga mereka yang berasal dari luar pulau Jawa seperti Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan masih banyak lagi tentunya, perlahan mulai menyesuaikan dengan penggunaan logat dan bahasa lokal yang lembut khas Jawa Tengah, khususnya Solo. Banyak dari mereka meniru intonasi pengucapaan hingga kosakata yang semula asing bagi mereka, seperti, “horok”, “pekeweuh”, “men” dan “rak”. Bahasa menjadi ruang sosial cair yang memudahkan interaksi lintas identitas. Bahkan mahasiswa lokal asal Solo juga ikut “terseret arus”, kerap meniru gaya bicara teman pendatang karena dianggap lebih ekpresif atau lucu.
Dalam pandangan sosiolinguistik, percampuran ini disebut akomodasi komunikasi, yakni penyesuaian gaya Bahasa demi menciptakan sosial. Menurut Howard Giles dalam artikelnya yang berjudul “Accent Mobility: A Model and Some Data” (1973), ia menjelaskan bahwa fenomena penyesuaian perilaku berbahasa muncul sebagai bagian dari Communication Accommodation Theory, yaitu teori yang menerangkan bagaimana penutur menyesuaikan gaya komunikasi mereka agar interaksi lintas identitas berjalan lebih cair dan harmonis. Berbagai logat dan bahasa yang bercampur ini bisa di baca sebagai bentuk toleransi linguistik. Saat mahasiswa pendatang mulai menggunakan logatnya dengan bahasa lokal merupakan bagian dari penyesuaian diri, dimana dalam hal tersebut mereka mahasiswa pendatang berusaha untuk menghargai lawan bicaranya. Begitupun sebaliknya, ketika mahasiswa lokal ikut meniru gaya bicara mahasiswa pendatang, itu menandakan keterbukaan terhadap keberagaman ekspresi.
Menurut Harimurti Kridalaksana dalam bukunya yang berjudul Kamus Linguistik (2008), ia mengatakan bahwa bahasa selalu bersifat dinamis; perubahan logat maupun gaya bicara akan menyesuaikan konteks serta situasi penuturnya. Hal ini berarti, perubahan logat atau gaya bicara adalah hal wajar selama terjadi dalam semangat keterhubungan, bukan penyeragaman. Di perantauan, khususnya kehidupan rantau mahasiswa, logat dan bahasa yang bercampur justru menjadi “bahasa gaul” yang baru seperti “sing penting paham,” begitulah kira-kira semangatnya. Bahasa bukan lagi menjadi pembeda, melainkan perekat sosial yang memperkecil jarak antardaerah. Toleransi yang tercipta karena semangat tidak menutup kemungkinan terdapat sisi yang perlu diwaspadai. Banyak mahasiswa pendatang yang merasa kehilangan logat ataupun bahasa asal daerah mereka karena lama menetap di Solo. Beberapa juga merasa “malu” menggunakan dialek asal karena beberapa alasan, seperti dianggap aneh karena bahasanya berbeda, kemudian untuk mereka yang berasal dari Jawa Timur dengan logat intonasi yang tinggi kerap dianggap kasar jika di lingkup masyarakat dengan budaya yang lemah lembut seperti Solo. Fenomena ini menunjukkan adanya krisis identitas linguistik dimana seseorang tidak lagi terikat dengan bahasa ibu, namun juga belum sepenuhnya menyatu dengan bahasa lingkungannya.
Menurut A. Chaedar Alwasilah dalam bukunya yang berjudul Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif (2011), ia berpendapat bahwa hilangnya bahasa daerah merupakan gejala awal lunturnya identitas bahasa daerah, sekaligus menjadi tanda awal terkikisnya identitas kebangsaan. Bahasa bukan hanya sekadar alat komunikasi, melainkan simbol eksistensi dan akar budaya. Maka dari itu, apabila seseorang meninggalkan logatnya demi menyesuaikan diri, bisa dikatakan ia sedang melepaskan identitasnya. Perubahan yang terjadi tentu tidak bisa kita tolak kehadirannya, khususnya di lingkup kampus dan kota seperti Solo yang memiliki budaya kental adalah ruang lingkup yang dinamis, bahasa yang terus berkembang sejalur dengan arus pergaulan serta berkembangnya teknologi.
Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa ataupun para pendatang untuk menjaga kesadaran linguistik dengan paham akan konsep bahwa untuk adaptasi dengan lingkungan tidak sama hal nya dengan melebur total. Mereka yang berada di perantauan, boleh saja mencampur aduk logat ataupun bahasa untuk bersosialisasi, asal tidak lupa darimana suara kita berasal. Bahasa daerah dan logat daerah tetap memiliki nilai yang bukan hanya sekedar cara berbicara, namun juga bagian dari diri. Hingga pada akhirnya, bahasa dan logat yang bercampur bukanlah krisis atau kebanggan semata. Ia menjadi bukti toleransi selama kita sadar kapan harus menyesuaikan diri, dan kapan harus menjaga akar. Karena pada dasarnya, yang membuat kita kaya bukanlah bahasa yang seragam, namun keberanian untuk tetap berbeda tanpa kehilangan diri sendiri.
You may like
Opini
Efek Ben Franklin: Kunci Tersembunyi Membangun Kedekatan
Published
1 week agoon
9 February 2026By
Mitra Wacana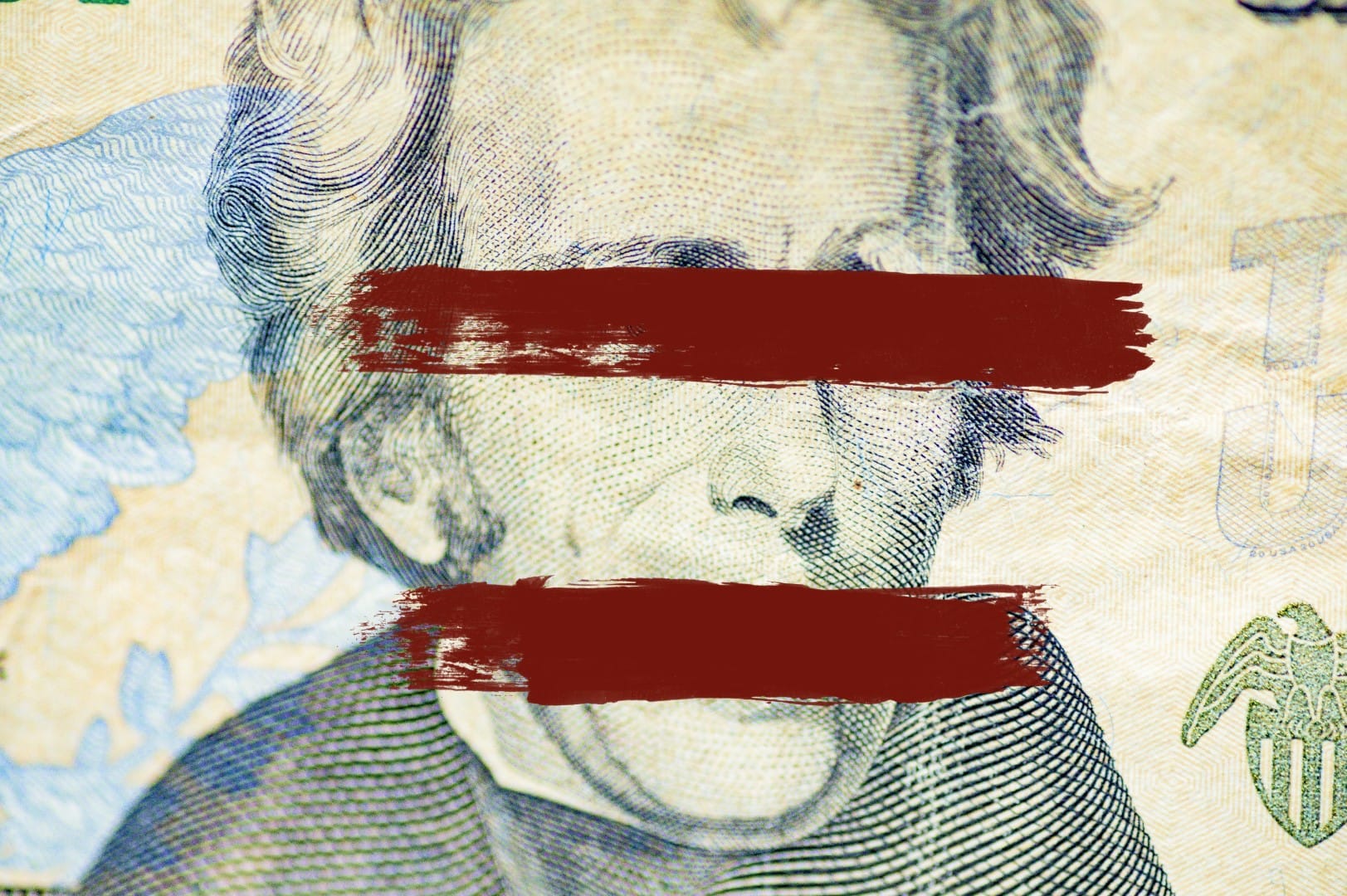

T.H. Hari Sucahyo,
alumnus Psikologi, peminat sosial humaniora
Awalnya, kita selalu diajari: kalau mau disukai, berbuat baiklah. Beri, bantu, tunjukkan kemurahan hati. Tapi, bagaimana jika semua itu salah? Bagaimana jika cara tercepat untuk merebut hati seseorang justru dengan… meminta bantuan mereka? Ini bukan trik manipulatif murahan, melainkan sebuah ironi psikologis elegan yang pernah dibuktikan oleh seorang jenius bernama Ben Franklin. Siap-siap, karena cara kita memandang hubungan bisa jadi akan terbalik 180 derajat.
Ben Franklin, seorang tokoh yang tidak hanya jenius dalam sains dan politik, tetapi juga memahami dinamika halus psikologi sosial, justru menemukan bahwa ketika ia meminta bantuan kecil dari seseorang yang awalnya tidak menyukainya, justru di sanalah hubungan mulai mencair. Dan ketika kita renungkan lebih jauh, ternyata ada alasan logis dan emosional mengapa trik ini bekerja.
Menurut saya, inti dari Efek Ben Franklin bukan sekadar tentang meminta bantuan atau menciptakan koneksi secara instan. Lebih dari itu, efek ini mengungkap sisi rapuh dari identitas manusia. Ketika seseorang memberikan bantuan kepada kita, ia secara tidak sadar menata ulang narasi internalnya: “Kalau aku bersedia menolong, berarti orang ini tidak seburuk yang kupikirkan.”
Otak kita menyukai konsistensi, dan karena itu, setelah seseorang berbuat baik, ia akan lebih mudah mempercayai bahwa tindakannya didasari alasan positif. Maka dari itu, orang yang memberikan pertolongan justru akan merasa lebih dekat secara emosional dibanding mereka yang menerima bantuan. Hal ini bertentangan dengan pola pikir umum kita, tetapi justru di situlah letak kecerdikannya.
Bagi saya, Efek Ben Franklin bukan hanya trik manipulatif seperti yang sering dipahami secara dangkal. Ia lebih menyerupai jembatan sosial. Franklin bukan sedang memanipulasi seseorang untuk menyukainya, melainkan mencari jalan untuk membangun hubungan dengan orang yang pada awalnya memandangnya secara negatif. Ia memanfaatkan sifat manusia yang ingin merasa rasional dan koheren dalam setiap tindakan.
Ketika seseorang melakukan kebaikan, batinnya ingin percaya bahwa ia melakukan itu pada orang yang pantas dibantu. Hal inilah yang mengubah cara pandangnya terhadap si penerima bantuan. Dalam konteks modern, trik ini sering dipakai dalam dunia kerja, organisasi, hingga hubungan interpersonal. Misalnya, ketika ingin menjalin hubungan baik dengan rekan kerja baru, meminta bantuan kecil atau saran sederhana sering kali menjadi langkah efektif untuk membuka komunikasi tanpa terkesan berlebihan.
Di satu sisi, saya melihat Efek Ben Franklin sebagai sesuatu yang memungkinkan kita meruntuhkan jarak dan prasangka. Di era sekarang, ketika banyak hubungan dibangun secara dangkal melalui media sosial, efek ini mengingatkan kita bahwa koneksi sejati terbentuk dari interaksi manusia yang lebih langsung dan emosional.
Meminta bantuan kecil bukanlah tanda kelemahan; justru bentuk kepercayaan bahwa orang lain memiliki sesuatu yang berharga untuk diberikan. Tindakan itu sendiri membawa pesan halus: “Aku menghargai pendapatmu dan percaya bahwa kamu dapat membantuku.” Pesan ini sering kali lebih mengena daripada bermacam-macam gesture kebaikan yang diberikan secara sepihak.
Kendati begitu, saya juga menyadari bahwa Efek Ben Franklin tidak serta-merta berhasil dalam setiap situasi. Ada kondisi psikologis dan sosial tertentu yang harus terpenuhi. Pertama, bantuan yang diminta harus kecil dan wajar. Bila kita meminta sesuatu yang terlalu besar, kita justru menempatkan orang tersebut pada posisi tertekan atau defensif. Efeknya malah kebalikannya: ia akan merasa dimanfaatkan.
Kedua, hubungan dasarnya tidak boleh berada dalam titik permusuhan ekstrem. Dalam konteks Franklin, orang yang membencinya bukanlah musuh yang berpotensi membahayakan nyawanya, tetapi lawan politik atau orang yang memiliki pandangan negatif tentang dirinya. Ketiga, waktu dan cara penyampaian sangat menentukan. Permintaan bantuan harus dilakukan dengan cara yang menunjukkan penghargaan dan ketulusan, bukan sebagai taktik licik yang dibuat-buat.
Saya melihat Efek Ben Franklin sebagai contoh bagaimana psikologi manusia sering kali bekerja pada pola yang halus dan tidak disadari. Orang mungkin merasa bahwa mereka mengambil keputusan berdasarkan logika atau sikap objektif. Padahal, banyak dari reaksi kita terhadap orang lain dipengaruhi oleh emosi dan rasa konsistensi internal.
Ketika seseorang melakukan kebaikan, ia ingin melihat dirinya sebagai orang yang baik. Maka ia akan mencari alasan untuk mengonfirmasi tindakan itu, salah satunya dengan mengubah persepsinya terhadap orang yang ditolong. Pola ini bisa sangat kuat, sehingga sering digunakan dalam berbagai konteks persuasi maupun negosiasi.
Di luar konteks politik dan sejarah Franklin, saya memandang efek ini sebagai pelajaran yang sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam memperbaiki hubungan yang mulai renggang. Banyak orang berusaha memperbaiki hubungan dengan memberi hadiah atau melakukan sesuatu yang besar untuk menebus kesalahan.
Terkadang, langkah kecil seperti meminta bantuan ringan bisa lebih efektif untuk memulihkan kedekatan. Permintaan itu secara tidak langsung memberikan ruang bagi orang lain untuk merasa dibutuhkan, dihargai, dan dilibatkan dalam hidup kita. Ini menciptakan dinamika emosional yang hangat tanpa harus memaksakan rekonsiliasi besar.
Dalam dunia profesional, efek ini dapat digunakan untuk membangun relasi yang lebih kuat. Saya sering melihat bagaimana para pemimpin yang baik bukan hanya mereka yang paling membantu, tetapi juga mereka yang memberi ruang bagi bawahannya untuk turut berkontribusi, bahkan dalam hal-hal kecil.
Dengan meminta masukan, pendapat, atau bantuan minor, mereka menciptakan rasa kepemilikan bersama. Orang yang dilibatkan akan merasa lebih dekat dan lebih loyal kepada pemimpin yang menaruh kepercayaan itu. Di titik ini, efeknya bukan lagi tentang trik psikologis, tetapi tentang membangun ekosistem kolaboratif yang sehat.
Tetapi tentu saja, saya juga melihat sisi lain yang perlu diperhatikan. Efek Ben Franklin dapat disalahgunakan jika dipakai untuk tujuan manipulatif. Jika seseorang hanya memanfaatkan efek ini demi keuntungan pribadi tanpa menghargai hubungan yang terbangun, maka hasilnya adalah hubungan yang rapuh dan palsu.
Kepercayaan yang muncul dari efek ini memang kuat, tetapi hanya jika permintaan bantuan disertai niat yang tulus. Menurut saya, kunci penting dalam menerapkan efek ini adalah keaslian. Jika seseorang merasa diperalat, maka efek itu akan terbalik dan justru menciptakan jarak lebih besar.
Terlepas dari itu, saya merasa Efek Ben Franklin adalah salah satu fenomena psikologis yang menunjukkan betapa fleksibelnya cara manusia membangun hubungan. Tidak selalu dengan memberi kita memperoleh teman. Terkadang, justru dengan menerima atau lebih tepatnya, meminta, kita membuka ruang bagi orang lain untuk mengekspresikan sisi terbaik dari diri mereka.
Di dunia yang sering menyanjung kemandirian berlebihan, efek ini mengingatkan kita bahwa kerentanan kecil bisa menjadi kekuatan sosial yang besar. Permintaan bantuan sederhana dapat membuka percakapan, mencairkan kecanggungan, menurunkan tembok pertahanan, dan pada akhirnya memperkuat ikatan.
Secara pribadi, saya menganggap Efek Ben Franklin sebagai pengingat bahwa hubungan manusia tak pernah bisa disederhanakan hanya dalam logika transaksional. Terkadang, seseorang akan lebih menyukai kita bukan karena kita memberi mereka sesuatu, melainkan karena kita memberi mereka kesempatan untuk merasa berarti.
Ini adalah dinamika yang sering terlupakan dalam interaksi modern yang serba cepat. Kita sibuk menunjukkan kemampuan, pencapaian, dan kebaikan kita kepada dunia, tetapi lupa bahwa salah satu cara terbaik untuk disukai adalah dengan menunjukkan sisi manusiawi kita: bahwa kita juga membutuhkan orang lain.
Efek Ben Franklin bukan sekadar trik, melainkan pemahaman mendalam tentang psikologi hubungan. Ia bekerja karena menyentuh sesuatu yang sangat mendasar: kebutuhan manusia untuk merasa kompeten, relevan, dan dihargai. Ketika kita memberi seseorang kesempatan melakukan sesuatu untuk kita, kita mengakui nilai mereka.
Pada saat yang sama, kita membuka ruang bagi hubungan yang lebih autentik dan saling menguntungkan. Itulah mengapa efek ini tetap relevan hingga hari ini. Ia bukan warisan retorika politik Franklin belaka, tetapi cermin dari cara manusia membangun makna dalam interaksi sosialnya.

Efek Ben Franklin: Kunci Tersembunyi Membangun Kedekatan

“Pemenuhan Hak Rakyat dan Perlindungan dari Bahaya Perdagangan Manusia di Indonesia” Upaya Kolaboratif Pencegahan Perdagangan Orang di Yogyakarta













