Opini
MAHASISWA DAN AURA FARMING
Published
2 months agoon
By
Mitra Wacana

Desfita Engggi Tri Andini mahasiswa aktif Program Studi Tadris (Pendidikan) Bahasa Indonesia di Fakultas Adab dan Bahasa, UIN Raden Mas Said Surakarta
Di zaman digital seperti saat ini, menjadi mahasiswa tidak cukup jika hanya rajin kuliah dan mendapat nilai bagus. Dunia kerja dan masyarakat mengharapkaan lebih: keterampilan berkomunikasi, kepercayaan diri, dan penampilan diri yang positif. Semua itu menjadi hal penting untuk dikenali, dipercaya, dan dihargai. Maka dari itu, banyak anak muda mulai sadar pentingnya membangun personal branding. Salah satu tren yang sedang ramai di media sosial dan nyatanya sangat relevan dengan hal ini adalah aura farming.
Aura farming merupakan kegiatan yang bertujuan untuk merawat, mengelola, dan memperbaiki citra diri atau aura pribadi melalui tindakan yang konsisten, konten yang relevan, perilaku yang baik, dan cara berinteraksi sehingga orang lain dapat merasakan “nilai” atau “getaran” yang ingin kita sampaikan. Jika didengar sekilas, mungkin terdengar seperti tren dari gaya hidup anak TikTok atau kadang terkesan aneh, seolah kita sedang “bercocok tanam” tapi yang ditanam adalah aura. Tetapi, sebenarnya memiliki makna yang lebih dalam dari itu.
Aura farming adalah sebuah metode yang dilakukan dengan kesadaran untuk menumbuhkan dan merawat energi positif dalam diri, mulai dari cara berpakaian, sikap, hingga cara berbicara. Di era digital, personal branding tidak bisa dilepaskan dari media sosial. Penelitian Universitas Pasundan menyebutkan bahwa media sosial berperan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap citra diri mahasiswa jika digunakan secara bijak (Menurut Journal Wistara, 2022).
Mahasiswa bahasa dapat memanfaatkan platform seperti Instagram, TikTok, dan LinkedIn untuk berbagi wawasan kebahasaan, membuat konten edukatif, atau menulis refleksi akademik. Aktivitas tersebut menjadi cara cerdas menanam “aura positif” yang menggambarkan kepribadian profesional. Aura farming tidak hanya berfokus dengan penampilan menarik di media sosial. Lebih dari itu, hal ini tentang bagaimana seseorang memancarkan atau menumbuhkan kepercayaan diri dan energi positif lewat perilaku dan pembawaan diri sendiri. Bagi mahasiswa bahasa, konsep ini sebenarnya sangat penting. Mahasiswa bahasa dikenal dengan keterampilan dalam berkomunikasi, berbahasa, dan memahami makna. Jika semua keterampilan tersebut dipadukan dengan kepribadian yang positif, rasa percaya diri, serta citra yang baik, maka akan tercipta sosok yang tidak hanya pintar, tetapi juga karismatik. Di lingkungan kampus, ini bisa menjadi faktor pembeda antara mahasiswa yang “biasa saja” dan mereka yang benar-benar menonjol.
Menurut Arista, Sela Septi Dwi, personal branding adalah proses membentuk citra diri yang autentik agar seseorang memiliki nilai dan pembeda di lingkungan sosial atau profesionalnya (Unair.ac.id, 2023). Bagi mahasiswa bahasa, personal branding dapat diwujudkan melalui tiga aspek utama: kemampuan berbicara, menulis, dan berpikir kritis. Personal branding adalah proses membangun citra diri yang autentik agar seseorang memiliki pembeda dan nilai lebih di lingkungannya. Artinya, personal branding bukan cuma soal pencitraan, tapi tentang mengenali potensi diri dan menampilkannya secara konsisten.
Bagi mahasiswa bahasa, terdapat tiga cara utama untuk mengembangkan merek pribadi, yaitu melalui keterampilan berbicara, menulis, dan berpikir secara kritis. Pertama yaitu Berbicara: Mahasiswa bahasa yang pandai berbicara akan terlihat percaya diri saat presentasi, diskusi, atau jadi pembicara di acara kampus. Public speaking yang baik adalah cara efektif untuk memancarkan aura positif. Kemudian yang kedua Menulis: Tulisan juga bisa jadi cerminan karakter. Lewat karya sastra, opini, atau konten media sosial, mahasiswa bahasa bisa menunjukkan kepekaan dan kecerdasannya dalam menanggapi isu. Terakhir Berpikir kritis: Kemampuan menganalisis masalah kebahasaan atau sosial membuat mahasiswa punya daya tarik intelektual tersendiri.
Selain itu, berpartisipasi dalam aktivitas seperti Duta Bahasa, kompetisi debat, penulisan, atau organisasi yang bergerak di bidang literasi juga dapat menjadi wujud nyata dari aura farming. Melalui pengalaman tersebut, kita dapat belajar untuk tampil secara profesional, mengasah kemampuan kepemimpinan, dan menunjukkan versi terbaik dari diri kita. Saat ini, hampir semua mahasiswa aktif di media sosial. Dan di situlah “aura” kita sering kali terlihat oleh orang lain. Media sosial bukan cuma tempat berbagi momen, tapi juga ruang membangun reputasi atau personal branding.
Mahasiswa bahasa bisa memanfaatkan platform seperti Instagram, TikTok, atau LinkedIn untuk berbagi hal-hal bermanfaat misalnya tips berbicara, refleksi kebahasaan, atau konten literasi ringan. Dengan begitu, kita bukan hanya dikenal sebagai pengguna media sosial aktif, tapi juga sebagai pribadi yang membawa pengaruh positif.
Namun, aura farming tidak boleh berubah jadi pencitraan palsu. Citra diri yang bagus itu harus datang dari keaslian dan konsistensi. Orang yang berusaha tampil baik tapi tidak punya isi akan cepat kehilangan kepercayaan. Personal branding sejatinya dibangun dari kejujuran dan kompetensi, bukan dari kepura-puraan.
Mahasiswa bahasa juga mempunyai modal besar untuk bersinar dengan kita terbiasa melakukan pengolahan kata, memahami makna, dan membaca situasi. Kalau kemampuan itu diimbangi dengan pembawaan yang positif dan rasa percaya diri, aura kita akan terpancar dengan sendirinya. Jadi, aura farming bukan cuma tren estetik yang muncul di media sosial. Ini adalah strategi cerdas untuk menampilkan versi terbaik dari diri sendiri dan seseorang yang sopan, komunikatif, percaya diri, dan konsisten dengan nilai-nilai positif.
Karena pada akhirnya, bukan hanya IPK atau nilai akademik yang akan membawa kita ke masa depan yang lebih baik. Tapi juga bagaimana kita membangun citra diri yang kuat dan autentik. Bagaimana kita mampu “memancarkan aura” yang menunjukkan kepribadian, integritas, dan kemampuan komunikasi kita sebagai mahasiswa bahasa.
You may like
Opini
Efek Ben Franklin: Kunci Tersembunyi Membangun Kedekatan
Published
1 week agoon
9 February 2026By
Mitra Wacana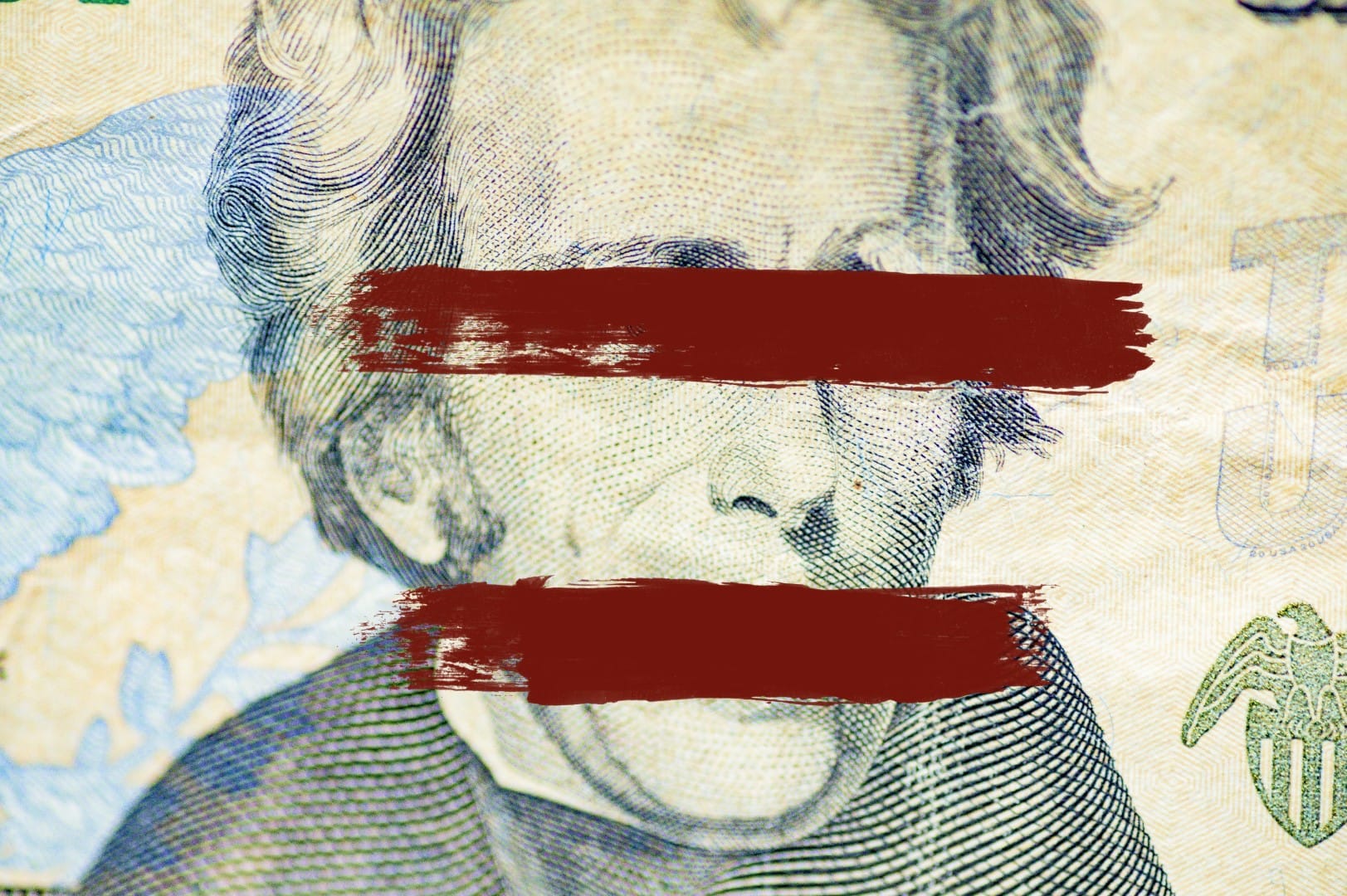

T.H. Hari Sucahyo,
alumnus Psikologi, peminat sosial humaniora
Awalnya, kita selalu diajari: kalau mau disukai, berbuat baiklah. Beri, bantu, tunjukkan kemurahan hati. Tapi, bagaimana jika semua itu salah? Bagaimana jika cara tercepat untuk merebut hati seseorang justru dengan… meminta bantuan mereka? Ini bukan trik manipulatif murahan, melainkan sebuah ironi psikologis elegan yang pernah dibuktikan oleh seorang jenius bernama Ben Franklin. Siap-siap, karena cara kita memandang hubungan bisa jadi akan terbalik 180 derajat.
Ben Franklin, seorang tokoh yang tidak hanya jenius dalam sains dan politik, tetapi juga memahami dinamika halus psikologi sosial, justru menemukan bahwa ketika ia meminta bantuan kecil dari seseorang yang awalnya tidak menyukainya, justru di sanalah hubungan mulai mencair. Dan ketika kita renungkan lebih jauh, ternyata ada alasan logis dan emosional mengapa trik ini bekerja.
Menurut saya, inti dari Efek Ben Franklin bukan sekadar tentang meminta bantuan atau menciptakan koneksi secara instan. Lebih dari itu, efek ini mengungkap sisi rapuh dari identitas manusia. Ketika seseorang memberikan bantuan kepada kita, ia secara tidak sadar menata ulang narasi internalnya: “Kalau aku bersedia menolong, berarti orang ini tidak seburuk yang kupikirkan.”
Otak kita menyukai konsistensi, dan karena itu, setelah seseorang berbuat baik, ia akan lebih mudah mempercayai bahwa tindakannya didasari alasan positif. Maka dari itu, orang yang memberikan pertolongan justru akan merasa lebih dekat secara emosional dibanding mereka yang menerima bantuan. Hal ini bertentangan dengan pola pikir umum kita, tetapi justru di situlah letak kecerdikannya.
Bagi saya, Efek Ben Franklin bukan hanya trik manipulatif seperti yang sering dipahami secara dangkal. Ia lebih menyerupai jembatan sosial. Franklin bukan sedang memanipulasi seseorang untuk menyukainya, melainkan mencari jalan untuk membangun hubungan dengan orang yang pada awalnya memandangnya secara negatif. Ia memanfaatkan sifat manusia yang ingin merasa rasional dan koheren dalam setiap tindakan.
Ketika seseorang melakukan kebaikan, batinnya ingin percaya bahwa ia melakukan itu pada orang yang pantas dibantu. Hal inilah yang mengubah cara pandangnya terhadap si penerima bantuan. Dalam konteks modern, trik ini sering dipakai dalam dunia kerja, organisasi, hingga hubungan interpersonal. Misalnya, ketika ingin menjalin hubungan baik dengan rekan kerja baru, meminta bantuan kecil atau saran sederhana sering kali menjadi langkah efektif untuk membuka komunikasi tanpa terkesan berlebihan.
Di satu sisi, saya melihat Efek Ben Franklin sebagai sesuatu yang memungkinkan kita meruntuhkan jarak dan prasangka. Di era sekarang, ketika banyak hubungan dibangun secara dangkal melalui media sosial, efek ini mengingatkan kita bahwa koneksi sejati terbentuk dari interaksi manusia yang lebih langsung dan emosional.
Meminta bantuan kecil bukanlah tanda kelemahan; justru bentuk kepercayaan bahwa orang lain memiliki sesuatu yang berharga untuk diberikan. Tindakan itu sendiri membawa pesan halus: “Aku menghargai pendapatmu dan percaya bahwa kamu dapat membantuku.” Pesan ini sering kali lebih mengena daripada bermacam-macam gesture kebaikan yang diberikan secara sepihak.
Kendati begitu, saya juga menyadari bahwa Efek Ben Franklin tidak serta-merta berhasil dalam setiap situasi. Ada kondisi psikologis dan sosial tertentu yang harus terpenuhi. Pertama, bantuan yang diminta harus kecil dan wajar. Bila kita meminta sesuatu yang terlalu besar, kita justru menempatkan orang tersebut pada posisi tertekan atau defensif. Efeknya malah kebalikannya: ia akan merasa dimanfaatkan.
Kedua, hubungan dasarnya tidak boleh berada dalam titik permusuhan ekstrem. Dalam konteks Franklin, orang yang membencinya bukanlah musuh yang berpotensi membahayakan nyawanya, tetapi lawan politik atau orang yang memiliki pandangan negatif tentang dirinya. Ketiga, waktu dan cara penyampaian sangat menentukan. Permintaan bantuan harus dilakukan dengan cara yang menunjukkan penghargaan dan ketulusan, bukan sebagai taktik licik yang dibuat-buat.
Saya melihat Efek Ben Franklin sebagai contoh bagaimana psikologi manusia sering kali bekerja pada pola yang halus dan tidak disadari. Orang mungkin merasa bahwa mereka mengambil keputusan berdasarkan logika atau sikap objektif. Padahal, banyak dari reaksi kita terhadap orang lain dipengaruhi oleh emosi dan rasa konsistensi internal.
Ketika seseorang melakukan kebaikan, ia ingin melihat dirinya sebagai orang yang baik. Maka ia akan mencari alasan untuk mengonfirmasi tindakan itu, salah satunya dengan mengubah persepsinya terhadap orang yang ditolong. Pola ini bisa sangat kuat, sehingga sering digunakan dalam berbagai konteks persuasi maupun negosiasi.
Di luar konteks politik dan sejarah Franklin, saya memandang efek ini sebagai pelajaran yang sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam memperbaiki hubungan yang mulai renggang. Banyak orang berusaha memperbaiki hubungan dengan memberi hadiah atau melakukan sesuatu yang besar untuk menebus kesalahan.
Terkadang, langkah kecil seperti meminta bantuan ringan bisa lebih efektif untuk memulihkan kedekatan. Permintaan itu secara tidak langsung memberikan ruang bagi orang lain untuk merasa dibutuhkan, dihargai, dan dilibatkan dalam hidup kita. Ini menciptakan dinamika emosional yang hangat tanpa harus memaksakan rekonsiliasi besar.
Dalam dunia profesional, efek ini dapat digunakan untuk membangun relasi yang lebih kuat. Saya sering melihat bagaimana para pemimpin yang baik bukan hanya mereka yang paling membantu, tetapi juga mereka yang memberi ruang bagi bawahannya untuk turut berkontribusi, bahkan dalam hal-hal kecil.
Dengan meminta masukan, pendapat, atau bantuan minor, mereka menciptakan rasa kepemilikan bersama. Orang yang dilibatkan akan merasa lebih dekat dan lebih loyal kepada pemimpin yang menaruh kepercayaan itu. Di titik ini, efeknya bukan lagi tentang trik psikologis, tetapi tentang membangun ekosistem kolaboratif yang sehat.
Tetapi tentu saja, saya juga melihat sisi lain yang perlu diperhatikan. Efek Ben Franklin dapat disalahgunakan jika dipakai untuk tujuan manipulatif. Jika seseorang hanya memanfaatkan efek ini demi keuntungan pribadi tanpa menghargai hubungan yang terbangun, maka hasilnya adalah hubungan yang rapuh dan palsu.
Kepercayaan yang muncul dari efek ini memang kuat, tetapi hanya jika permintaan bantuan disertai niat yang tulus. Menurut saya, kunci penting dalam menerapkan efek ini adalah keaslian. Jika seseorang merasa diperalat, maka efek itu akan terbalik dan justru menciptakan jarak lebih besar.
Terlepas dari itu, saya merasa Efek Ben Franklin adalah salah satu fenomena psikologis yang menunjukkan betapa fleksibelnya cara manusia membangun hubungan. Tidak selalu dengan memberi kita memperoleh teman. Terkadang, justru dengan menerima atau lebih tepatnya, meminta, kita membuka ruang bagi orang lain untuk mengekspresikan sisi terbaik dari diri mereka.
Di dunia yang sering menyanjung kemandirian berlebihan, efek ini mengingatkan kita bahwa kerentanan kecil bisa menjadi kekuatan sosial yang besar. Permintaan bantuan sederhana dapat membuka percakapan, mencairkan kecanggungan, menurunkan tembok pertahanan, dan pada akhirnya memperkuat ikatan.
Secara pribadi, saya menganggap Efek Ben Franklin sebagai pengingat bahwa hubungan manusia tak pernah bisa disederhanakan hanya dalam logika transaksional. Terkadang, seseorang akan lebih menyukai kita bukan karena kita memberi mereka sesuatu, melainkan karena kita memberi mereka kesempatan untuk merasa berarti.
Ini adalah dinamika yang sering terlupakan dalam interaksi modern yang serba cepat. Kita sibuk menunjukkan kemampuan, pencapaian, dan kebaikan kita kepada dunia, tetapi lupa bahwa salah satu cara terbaik untuk disukai adalah dengan menunjukkan sisi manusiawi kita: bahwa kita juga membutuhkan orang lain.
Efek Ben Franklin bukan sekadar trik, melainkan pemahaman mendalam tentang psikologi hubungan. Ia bekerja karena menyentuh sesuatu yang sangat mendasar: kebutuhan manusia untuk merasa kompeten, relevan, dan dihargai. Ketika kita memberi seseorang kesempatan melakukan sesuatu untuk kita, kita mengakui nilai mereka.
Pada saat yang sama, kita membuka ruang bagi hubungan yang lebih autentik dan saling menguntungkan. Itulah mengapa efek ini tetap relevan hingga hari ini. Ia bukan warisan retorika politik Franklin belaka, tetapi cermin dari cara manusia membangun makna dalam interaksi sosialnya.

Efek Ben Franklin: Kunci Tersembunyi Membangun Kedekatan

“Pemenuhan Hak Rakyat dan Perlindungan dari Bahaya Perdagangan Manusia di Indonesia” Upaya Kolaboratif Pencegahan Perdagangan Orang di Yogyakarta













