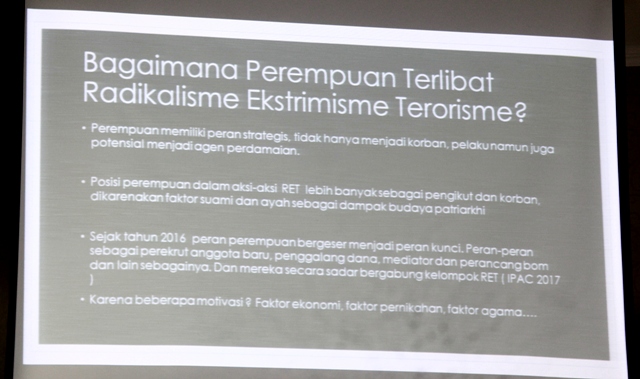Rilis
Sebuah Kisah Eks Migran
Published
12 years agoon
By
Mitra Wacana
Oleh Imelda Zuhaida
Beberapa waktu lalu, penulis bertemu dengan para mantan buruh migrant di kecamatan Kokap Kulon Progo. Dikisahkan oleh seorang perempuan bernama Sukini (36 tahun)yang berangkat ke Taiwan sebagai PRT. Perempuan lulusan SMEA Negeri Wates jurusan pemasaran ini, diajak oleh orang Wates yang merupakan perwakilan dari PJTKI yang berdomisili di Jakarta. Sukini berangkat bersama teman-temannya ke Jakarta. Di Jakarta dia bersama teman-temannya ditampung selama 5 bulan untuk mengikuti training memasak, merawat bayi dan bahasa.
Dalam kontrak kerjanya tertera dia sebagai pramurukti (merawat orang tua) selama 2 tahun tetapi sesampai disana, dia harus mengerjakan seluruh pekerjaan rumah dengan jam kerja selama 12 jam sehari, mendapat libur 1 hari dalam 1 bulan. Selama di Taiwan, Sukini mendapat gaji sekitar 4,5 juta,rupiah dipotong oleh PJTKI sebanyak 1 juta rupiah selama 1 tahun untuk biaya keberangkatan. Sukini memperpanjang kontraknya menjadi 3 tahun. Setelah pulang, atas kebaikan majikannya, dia diberi hadiah emas sebanyak 10 gram.
Saat pulang ke Indonesia, di bandara Sukini sangat ketakutan oleh para calo. Dia berharap, pemerintah memberikan jaminan keamanan saat kepulangan TKI di bandara.
Hasil dari pendapatan selama Sukini merantau, Sukini bisa membeli kebun kelapa sawit sebanyak 2 hektar dengan harga 60 juta rupiah di Riau yang dikelola oleh mertuanya. Penghasilan dari kelapa sawit ini antara 2 juta rupiah hingga 6 juta rupiah, tergantung jumlah panen. Uang ini dia gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena suaminya juga tidak mempunyai pekerjaan tetap.
Jika dilihat pelanggaran yang terjadi, Sukini sudah diperlakukan tidak adil. Dimulai saat di penampungan, sering terjadi kekerasan verbal (dibentak) jika melakukan sedikit kesalahan. Yang kedua, dikontrak kerja yang hanya pramurukti, dia harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga penuh. Ketiga, pemotongan gaji sebanyak 12 juta rupiah yang tidak disampaikan sejak awal pemberangkatanKarena Sukini tidak pilihan saat itu, dia hanya pasrah.
Lain halnya dengan Sunarti (30 tahun) seorang lulusan SMK PGRI Sentolo. Dia berangkat dua kali ke negeri Malaysia. Yang pertama selama 2 tahun, dia sebagai tenaga di pabrik IC untuk pesawat dan telpon genggam. Dia berangkat ke Malaysia karena ajakan temannya yang pernah menjadi TKI di Malaysia melalui PJTKI yang ada di Yogya. Sebelum diberangkatkan, Sunarti sempat tinggal di penampungan di Solo selama 1 hari.
Upah yang diterimakan sebanyak 430 Ringgit atau sekitar 2 juta Rupiah sesuai dengan standar UMR Malaysia saat itu dengan jam kerja 12 jam, istirahat 2 kali untuk sholat dan makan, masing-masing 15 menit. Sebelum bekerja, Sunarti mendapatkan training selama 2 bulan. Kepergian Sukini ke negeri Jiran yang kedua dengan PJTKI yang berbeda, dia harus membayar uang awal 5 juta yang dia dapatkan dari orang tuanya dengan menjual kayu. Di perusahaan yang kedua ini, Sukini sering mendapat perlakuan kekerasan dari mandor pabrik jika melakukan kesalahan.
Hasil dari merantau selama 4 tahun di Malaysia, Sukini yang kini beraktivitas sebagai pembuat wig (rambut palsu) ini, tidak sebanding dengan jerih payahnya. Jangankan untuk mengembalikan uang tuanya 5 juta yang dipinjam untuk keberangkatan, dia hanya bisa untuk membeli TV, selebihnya habis untuk biaya konsumsi disana, meskipun dia tinggal di asrama.
Meskipun saat Pemilu, tetap dilibatkan atas fasilitas perusahaan, namun Sukini mengaku tidak akan kembali ke Malaysia karena tidak kerasan karena kerjanya tidak manusiawi. Ada lagi, Tumiyati (36 tahun) berangkat ke Malaysia tahun 2000 sebagai pekerja di pabrik kayu lapis melalui PJTKI Persada Duta Utama Wates dengan biaya 3 juta yang didapat dari hutang . Sebelum berangkat, dilakukan training selama 3 bulan. Tumiyati merantau ke negeri jiran dengan kontrak 3 tahun, kemudian diperpanjang 2 tahun, kemudian 1 tahun, sehingga total 6 tahun.
Perjalanan menuju Malaysia menggunakan kapal laut selama 1 minggu yang singgah di Tarakan dan Towawu. Gaji yang diterima 8 ringgit dengan beban kerja 600 lembar kayu lapis per hari. Jam kerja 12 jam dengan waktu istirahat 15 menit 2 kali untuk ibadah dan makan. Melihat pengalaman yang pahit, dari modal awal untuk keberangkatan, proses pengangkutan, beban kerja dan gaji yang sangat tidak manusiawi. Makanya Tumiyati memilih untuk tidak menjadi buruh migran lagi.
You may like
Berita
Nobar Film “Tak Ada Makan Siang Gratis”, CELIOS Ajak Publik Kritisi Kebijakan MBG
Published
1 month agoon
19 December 2025By
Mitra Wacana
Yogyakarta, Kamis (18/12/2025) — Ketika makan disebut “gratis”, siapa sebenarnya yang membayar harganya? Pertanyaan ini seketika muncul saat mendengar judul film dokumenter ‘Tak Ada Makan Siang Gratis’ karya Watchdoc dalam acara Nonton Bareng (Nobar) yang diinisiasi oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Acara yang digelar di VRTX Compound Space pada Kamis malam, pukul 18.30–22.00 WIB ini menjadi ruang diskusi bagi publik untuk mengkritisi kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) dari berbagai perspektif, mulai dari anggaran negara, tata kelola pangan, mitigasi bencana, hingga suara perempuan dan ibu. Mitra Wacana menjadi salah satu undangan yang hadir bersama berbagai organisasi, CSO, akademisi, dan individu lain yang ada di Yogyakarta karena memang acara ini terbuka bagi semuanya.
Film Tak Ada Makan Siang Gratis membongkar narasi populer MBG sebagai program pro-rakyat dengan menunjukkan konsekuensi kebijakan fiskal dan politik di baliknya. Diskusi setelah pemutaran film menyoroti bagaimana pelaksanaan MBG tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan pemotongan anggaran sektor lain yang sama-sama krusial bagi keselamatan dan kesejahteraan warga.

Dalam diskusi terungkap bahwa MBG dijalankan bersamaan dengan pemangkasan anggaran pendidikan dan transfer ke daerah. Dana pendidikan dan transfer daerah, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta, disebut mengalami pengurangan signifikan, sementara ratusan triliun rupiah dialihkan untuk MBG. Jika dihitung secara proporsional, dana tersebut seharusnya dapat memberikan manfaat yang jauh lebih besar bagi penerima. Namun di lapangan, nilai makanan yang diterima anak hanya sekitar Rp10.000 per porsi. Selisih ini memunculkan pertanyaan mengenai inefisiensi anggaran, potensi rente, dan politisasi kebijakan sosial.
Film dan diskusi juga menyoroti dampak kebijakan fiskal tersebut terhadap kemampuan negara menangani bencana. Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan lembaga terkait mengalami pemangkasan drastis, padahal Indonesia setiap tahun menghadapi 4.000–5.000 kejadian bencana. Yang jika dihitung-hitung, setiap bencana hanya akan mendapat anggaran sebesar 200 juta saja. Dengan anggaran yang semakin terbatas, penanganan bencana kerap dibebankan kepada pemerintah daerah dan relawan. Situasi ini dinilai ironis karena di dalam konteks bencana banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, negara juga cenderung enggan menetapkan status bencana nasional maupun menerima bantuan internasional, sehingga risiko dan beban terbesar justru ditanggung oleh warga di lapangan.
Salah satu fokus penting dalam diskusi adalah minimnya pelibatan perempuan dan ibu dalam perumusan kebijakan MBG. Padahal, dalam kehidupan sehari-hari, perempuan—terutama ibu—memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait gizi, keamanan pangan, dan kebutuhan anak. Dari perspektif “bahasa ibu-ibu”, pemenuhan gizi anak seharusnya dilakukan melalui dapur sekolah atau kantin sehat berbasis komunitas, dengan makanan segar yang dimasak setiap hari. Model ini dinilai lebih aman, bergizi, dan berkelanjutan dibanding sistem dapur terpusat berskala besar.
Film Tak Ada Makan Siang Gratis menunjukkan bagaimana model dapur terpusat (SPPG) justru melahirkan persoalan baru. Produksi ribuan porsi makanan setiap hari mendorong penyimpanan bahan baku dalam jumlah besar dan waktu lama, sehingga berisiko basi dan menurunkan kualitas gizi. Akibatnya, menu yang diberikan kepada anak-anak kerap berupa makanan olahan dan beku karena lebih mudah disimpan. Diskusi mencatat adanya kasus keterlambatan distribusi, makanan tidak segar, hingga keracunan di sekolah-sekolah, yang menimbulkan keresahan bagi guru dan orang tua.
Diskusi juga menyinggung dugaan kuat bahwa MBG telah menjadi arena politisasi pangan. Dalam film ditunjukkan adanya ratusan dapur yang terafiliasi dengan jaringan atau kelompok tertentu. Penutupan dapur sekolah dan penolakan terhadap model berbasis komunitas dinilai tidak lepas dari kepentingan politik dan ekonomi. Alih-alih memperkuat kedaulatan pangan dan kesejahteraan warga, MBG justru berpotensi memperluas praktik rente serta mengabaikan sistem pangan lokal yang sebelumnya telah berjalan.
Melalui nobar dan diskusi ini, CELIOS dan Watchdoc membuka ruang bagi publik untuk bersikap kritis terhadap kebijakan pangan nasional. Kritik yang disampaikan tidak dimaksudkan untuk menolak pemenuhan gizi anak, melainkan menuntut kebijakan yang transparan, berbasis data, dan berpihak pada keselamatan serta kesejahteraan rakyat.
Acara ini menegaskan pesan utama film: dalam kebijakan publik, tidak pernah ada “makan siang gratis”. Setiap kebijakan memiliki biaya sosial dan politik, dan karena itu harus terus diawasi dan diperdebatkan secara terbuka. Acara nobar ditutup dengan pembacaan 10 Tuntutan Reformasi Program MBG:
Realokasi Anggaran untuk Penanganan Bencana.
Rapikan tumpang tindih anggaran, pastikan MBG tepat sasaran, dan alokasikan anggaran ke penanganan bencana yang lebih mendesak. Termasuk jangan mengambil anggaran MBG dari anggaran pendidikan.
Tetapkan Status Bencana Nasional untuk Bencana Ekologis di Sumatra.
Moratorium dan Audit Total.
Hentikan ekspansi SPPG MBG dan lakukan audit menyeluruh terhadap sistem, pelaksanaan, dan dampak program. Termasuk audit terbuka seluruh SPPG terkait keamanan pangan, standar gizi, efektivitas, dan keuangan SPPG serta buka hasilnya ke publik.
Pembekuan Kontrak.
Selesaikan seluruh tunggakan pembayaran dan bekukan kontrak serta selesaikan semua pembayaran yang terhutang maksimal awal tahun 2026.
Restrukturisasi Kepemimpinan.
Ganti pimpinan yang gagal dan tunjuk pelaksana tugas profesional independen berbasis kompetensi.
Satgas Reformasi 100 Hari.
Bentuk satgas lintas lembaga untuk membenahi tata kelola, menyeleksi ulang kontraktor, dan menindak pelanggaran.
Desentralisasi Sistem.
Hentikan model dapur besar terpusat dan alihkan ke dapur berbasis sekolah serta UMKM lokal yang terarah.
Standarisasi Menu Nasional.
Terapkan menu berbasis pangan lokal segar, bebas ultra-processed food, dan memenuhi kecukupan gizi.
Transformasi Skema Program.
Jalankan MBG baru dengan skema makanan berbasis sekolah di wilayah prioritas serta voucher gizi atau BLT disertai pelatihan bagi keluarga rentan.
Konsolidasi Permanen.
Bangun sistem MBG berkelanjutan dengan pengawasan lintas lembaga, integrasi program gizi nasional, dan dashboard publik.
Oleh Alfi ramadhani Divisi Pendidikan dan Pengorganisasian Mitra Wacana