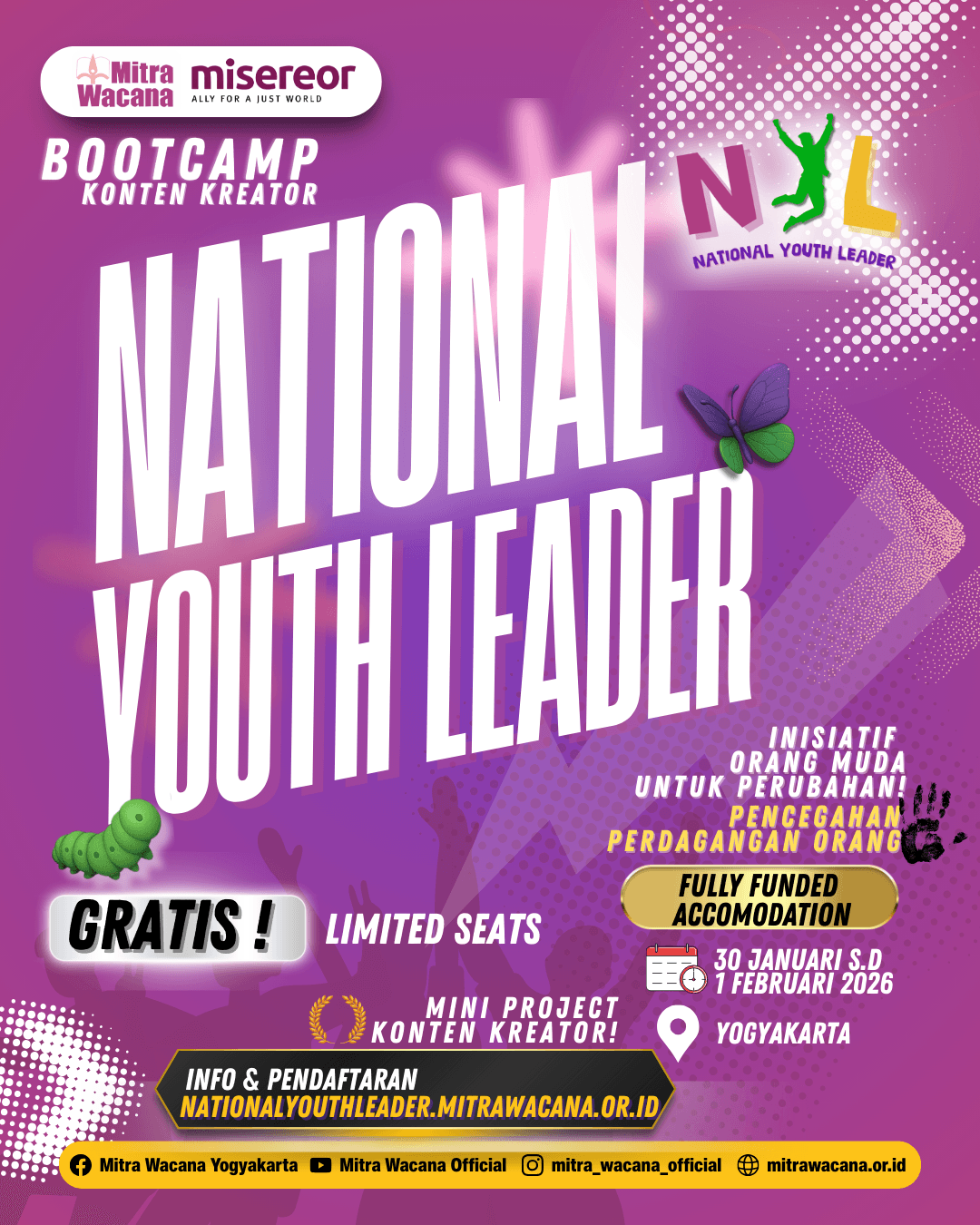Opini
RUU PKS dan Upaya Perlindungan Terhadap Penyintas
Published
7 years agoon
By
Mitra Wacana
Oleh Imelda Zuhaida (Direktur Mitra Wacana WRC)
Upaya penyelesaian kasus pelecehan seksual yang dialami salah seorang mahasiswi ketika tengah melakukan KKN, menuai banyak pendapat dari berbagai kalangan karena dinilai tidak adil bagi penyintas. Selain menyayangkan respon universitas ketika pertama kali mengetahui persoalan tersebut juga dianggap miris karena mengabaikan tuntutan penyintas, yaitu agar HS dikeluarkan dari universitas. Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan pada Senin, 4 Februari 2019, oleh tiga pihak: Agni, HS, dan Panut, yang disaksikan Dekan Fisipol UGM Erwan Agus Purwanto dan Dekan Teknik UGM Nizam, ayah HS, serta pengacara korban, Sukiratnasari. Akhirnya, pertemuan oleh beberapa pihak ini dianggap sebagai tanda kasus pemerkosaan terhadap Agni dianggap “selesai”.
Sebagai penulis, tidak bisa membayangkan bagaimana kondisi psikis Agni ketika mengetahui adanya pertemuan tersebut. Perasaan marah, kecewa, benci dan kesal, bisa jadi menyelimuti perasaan Agni. Sebagai penyelenggara pendidikan, Universitas semestinya lebih mengedepankan perspektif terhadap penyintas sebagai bentuk perlindungan terhadap anak didiknya atau pertanggungjawaban terhadap intitusi pendidikan. Maka, tidaklah heran jika ada sebagian dari masyarakat dan penggiat sosial menyebut jika upaya dan proses penyelesaian kasus ini boleh dikatakan belum perperspektif keadilan bagi penyintas. Jika hal ini yang terjadi, maka rantai kekerasan ini akan terus berulang karena ketiadaan sangsi bagi pelaku dengan dalih perlindungan penyelamatan nama besar sebuah Universitas.
Apakah kasusnya selesai?
Upaya penyelesaian kasus Agni ini cenderung mengabaikan hak-hak Agni sebagai penyintas dan mengedepankan nama baik universitas. Ketika memperjuangkan hak, dianggap mencemarkan nama baik Universitas. Dari konteks ini jelas ada relasi kuasa antara Universitas dan penyintas, dimana kemungkinan ketika Universitas yang memiliki otoritas melakukan upaya-upaya intimidatif terhadap penyintas. Dalam konteks ini persoalan relasi kuasa patut menjadi faktor yang perlu di analisis dan mendapatkan perhatian ketika mencoba mengkritisi kasus tersebut di atas. Adanya kecenderungan birokrasi yang berbelit-belit namun tidak jelas menjadi salah satu bagi penyintas memilih bungkam karena khawatir “disalahkan”, mengingat masih kentalnya budaya victim blaming di tengah masyarakat, termasuk Universitas yang belum bisa steril seratus persen.
Demikian juga hubungan pelaku dan penyintas. Dalam analisis kekerasan berbasis jender, relasi kuasa dan patriarki biasanya selalu dominan ketika ada kasus kekerasan seksual; apapun bentuknya. Dalam patriarkhi; laki laki menganggap bahwa dirinya memiliki kedudukan lebih tinggi dari perempuan dan merasa lebih kuat serta berkuasa terhadap perempuan. Sebaliknya, perempuan dianggap lemah, dipandang sebagai obyek seksual dan kelompok inferior. Dengan anggapan tersebut, maka laki-laki seolah merasa paling berhak melakukan apa saja yang dikehendaki tanpa memperdulikan hak-hak perempuan.
Entah sadar atau tidak, budaya patriarkhi ini memberikan dampak negatif luar biasa dalam tatanan masyarakat, salah satunya yaitu konstruksi dan pola pikir bahwa peran laki-laki berkaitan erat dengan ego maskulinitas yang menyebutkan jika kekuasaan berada di tangan laki-laki maka perempuan dianggap subordinat, boleh dipandang remeh. Laki-laki merasa lebih kuat dan cenderung memiliki keleluasaan untuk melakukan apapun terhadap perempuan, termasuk melakukan pelecehan seksual. Bukankah hal ini mengerikan?
Upaya perlindungan penyintas
Kasus pelecehan seksual yang dialami oleh Agni, adalah salah satu kasus kekerasan seksual yang sekarang banyak terjadi. Perilaku pelecehan seksual merupakan pemaksaan kehendak yang sifatnya merendahkan, menghina, meremehkan perempuan. Kejahatan pelecehan seksual menimbulkan penderitaan yang sangat berat bagi perempuan sebagai penyintas. Penyintas mengalami penderitaan secara fisik dan psikologis yang sangat mendalam.
Maraknya kasus kekerasan seksual baik di Universitas maupun di luar Universitas menunjukkan angka yang cukup tinggi. Pada tahun 2017, Badan Pusat Statistik (BPS) mempublikasikan, sekitar 28 juta perempuan Indonesia mengalami kekerasan dan sebagian besar adalah kekerasan seksual (Kompas, 31/10/2017). Alasan inilah yang mendorong para aktivis perempuan dan Komisi Nasional Perlindungan Perempuan dan Anak (Komnas Perempuan) telah lama berjuang keras untuk memutus mata rantai kekerasan seksual derngan berbagai cara; meningkatkan kapasitas perempuan melalui pendidikan keadilan gender, worshop, seminar, FGD, sarasehan dan diskusi-diskusi yang berkaitan dengan pencegahan pelecehan seksual.
Salah satu strategi yang diambil adalah mendorong terbitnya regulasi khusus tentang pelecehan seksual. Regulasi yang ada selama ini hanya mencakup tindakan pencabulan. Oleh karenanya, Komnas Perempuan mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang -Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS). RUU PKS ini telah lima tahun digagas dan diperjuangkan. Telah melewati beberapa proses, antara lain : pembacaan naskah akademis, berbagai workshop, forum-forum diskusi, hingga aksi damai namun belum juga disahkan.
Dari berbagai informasi yang bisa kita saksikan, selama ini penyintas kekerasan seksual lebih banyak dialami oleh perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya. Oleh karena itu perlu menjadi prioritas mendapatkan perlindungan dari negara agar tidak terjadi keberulangan dan terbebas dari setiap bentuk kekerasan seksual. Dengan adanya RUU PKS diharapkan menguatkan kesadaran dan keberanian perempuan untuk melawan segala bentuk kekerasan. Karena, jika ada perempuan yang mengalami kekerasan seksual, sejatinya sedang mengalami kekerasan yang berlapis; kekerasan verbal, fisik dan kekerasan psikologis bahkan kekerasan sosial.
Salah satu alasan mengapa RUU PKS diterbitkan karena bentuk dan kuantitas kasus kekerasan seksual semakin meningkat, bahkan berkembang. Namun, hukum Indonesia belum secara sistematis dan menyeluruh mampu mencegah, melindungi, memberdayakan dan memulihkan penyintas kekerasan seksual. Dalam upaya pemenuhan hak penyintas meliputi hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan bertujuan mencegah keberulangan kekerasan seksual dan dampak yang berkelanjutan terhadap penyintas.
Disamping itu, juga menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menghapuskan kekerasan seksual. Ini adalah bentuk perjuangan anti kekerasan sekaligus perlindungan terhadap penyintas. Bagi penulis, berkeyakinan bahwa RUU PKS akan memberikan rujukan hukum yang jelas. Lebih dari itu akan memberikan manfaat bagi penyintas kekerasan seksual, misalnya adanya aturan tentang pemenuhan hak penyintas atas penanganan, perlindungan dan pemulihan fisik dan psikis penyintas setelah kejadian, termasuk juga proses hukumnya.
Saat ini RUU PKS masih dalam pembahasan di DPR. Ada beberapa catatan menurut DPR, khususnya komisi VIII, yang menganggap bahwa RUU PKS mengganggu tatanan dalam hubungan perkawinan, berisiko dimanfaatkan oleh LGBT dan dikhawatirkan menjadi pembenaran untuk melakukan kriminalisasi. Bagimanapun proses di DPR, harapannya ini jika sudah layak maka harus segera disahkan, sehingga perempuan Indonesia mempunyai legalitas untuk melindungi harkat, martabat, hak dan eksistensinya. Dan pada akhirnya, bisa menjadi rujukan yang jelas dalam penegakkan hukum kasus kekerasan seksual yang pada akhirnya kekerasan seksual bisa ditangani. Semoga….
Penyelaras : Ruly
Editor : Wahyu Tanoto
Opini
Merevolusi Cara Kita Melihat Tugas Kuliah
Published
3 weeks agoon
29 December 2025By
Mitra Wacana

Nurisa Cahya Artika Farah,Mahasiswi semester 3 Program Studi Tadris (Pendidikan) Bahasa Indonesia, Fakultas Adab dan Bahasa, Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta.
Di dunia perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menjadi individu yang mandiri, kritis, dan kreatif dalam menghadapi berbagai tantangan akademik. Salah satu tantangan tersebut adalah tugas kuliah yang diberikan oleh dosen sebagai proses pembelajaran. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak mahasiswa justru menganggap tugas kuliah sebagai beban yang membebani pikiran. Mahasiswa lebih fokus pada nilai akhir ketimbang proses belajar yang seharusnya memperkaya pengetahuan dan keterampilan. Fenomena ini menjadi gambaran bahwa sebagian mahasiswa masih memandang tugas secara sempit, tanpa menyadari bahwa melalui tugas inilah kemampuan berpikir kritis serta tanggung jawab perkuliahan dapat terasah.
Banyak kalangan mahasiswa mengeluh akan tugas kuliah yang diberikan, mereka memandangnya sebagai beban yang menumpuk dan hanya sebatas untuk mendapatkan nilai, bukan proses pembelajaran. Hal ini membuat motivasi belajar menurun yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, seperti kurangnya minat, kesulitan konsentrasi, masalah pribadi, maupun kualitas hasil tugas yang tidak mencerminkan pemahaman sebenarnya. Padahal, esensi pendidikan tinggi bukan sebatas mengerjakan tugas, namun membangun cara berpikir kritis dan kreatif mahasiswa. Karena itu, saatnya mahasiswa merevolusi cara pandang terhadap tugas yang dianggap beban menjadi proses pembelajaran yang bermakna.
Perkuliahan mahasiswa sebenarnya tidak hanya belajar dari penjelasan dosen, tetapi juga dari proses mengerjakan tugas. Hal ini sejalan dengan Teori Konstruktivisme yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun dari individu berdasarkan pengalaman dan pemahaman. Seperti halnya dalam pemberian tugas kuliah ini mahasiswa tidak hanya menerima ilmu dari dosen, tetapi juga membentuk pemahaman sendiri melalui pengalaman belajar sebelumnya. Dalam konteks ini, tugas kuliah bukanlah tujuan akhir, tetapi sebagai sarana untuk membangun pemahaman terhadap suatu konsep. Misalnya, ketika mahasiswa diminta menulis esai, mereka tidak hanya terpaku dengan teori yang sudah ada, tetapi juga menyusun gagasan atau ide pribadi berdasarkan pemahaman konseptual dan berpikir kritis. Dengan demikian, tugas menjadi penghubung antara pengetahuan dan penerapan.
Namun, faktanya di lapangan masih banyak mahasiswa yang memandang tugas sebagai sesuatu yang dipaksakan untuk semata-mata demi nilai. Hal ini sejalan dengan rendahnya motivasi dalam diri berdasarkan teori Self-Determination. Mahasiswa akan termotivasi jika memiliki kebebasan pilihan dalam menyelesaikan tugas (autonomi), merasa mampu mengerjakan (kompetensi), dan merasa bahwa tugas memiliki hubungan dengan kehidupan mereka (keterhubungan). Dengan demikian, ketika diberi tugas yang memberikan kebebasan, kemampuan, serta keterhubungan, mahasiswa akan melihat tugas bukan sebagai beban, melainkan sebagai bentuk pengembangan diri.
Selain itu, konsep belajar bermakna dari David Ausubel juga relevan dalam konteks ini. Dalam perkuliahan, hal ini berarti tugas yang diberikan seharusnya berasal dari struktur pemikiran yang telah dimiliki mahasiswa. Misalnya, tugas proyek yang menuntut mahasiswa mengaitkan teori dengan pengalaman pribadi. Ketika mahasiswa menemukan keterkaitan tersebut, proses belajar menjadi bermakna. Mereka tidak sedang mengerjakan tugas dosen melainkan sedang menemukan diri dalam proses pembelajaran.
Pandangan teori humanistik juga memperkuat gagasan ini. Dalam pandangan ini, mahasiswa dipandang sebagai individu yang unik dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Tugas kuliah, seharusnya menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengekspresikan diri, mengeksplorasi nilai-nilai pribadi, dan mengembangkan potensi secara utuh. Tugas tidak hanya mengukur hasil akhir berupa angka, tetapi juga menilai proses berpikir, kreativitas, den refleksi diri mahasiswa.
Sebagai mahasiswa, saya kerap melihat beberapa mahasiswa bahwa tugas baru benar-benar dipahami maknanya setelah dikerjakan, bukan saat materi disampaikan oleh dosen. Dari tugaslah mahasiswa belajar berpikir kritis, mampu mengelola waktu, dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa tugas kuliah sejatinya memiliki peran penting dalam membentuk kualitas mahasiswa, asalkan dipahami dan dijalani dengan cara pandang yang tepat.
Masalahnya sistem pendidikan kita masih berorientasi pada hasil bukan proses. Banyak mahasiswa mengerjakan tugas hanya untuk mendapatkan nilai bukan karena ingin memahami makna apa yang mereka pelajari. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan paradigma, baik dari pihak dosen maupun mahasiswa. Merevolusi cara pandang terhadap tugas kuliah berarti menempatkan kembali tugas sebagai bagian dari proses pembelajaran bukan sebagai beban mahasiswa. Ketika mahasiswa mulai melihat tugas sebagai ruang pengembangan diri mereka akan lebih bersemangat, produktif, dan berdaya saing. Tak hanya mahasiswa, dosen pun akan lebih mudah menilai kualitas pemahaman mahasiswa. Dengan demikian, revolusi ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hasil belajar, tetapi juga membentuk generasi mahasiswa yang berpikir kritis, reflektif, dan siap menghadapi tantangan di kehidupan nyata. Hal yang paling berharga dari tugas kuliah bukan hanya tentang nilai yang berupa angka melainkan proses belajar yang akan menambah pemahaman.