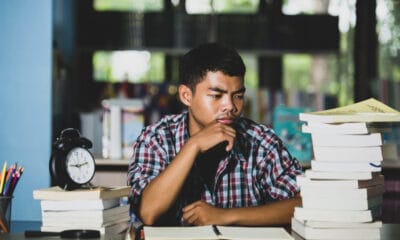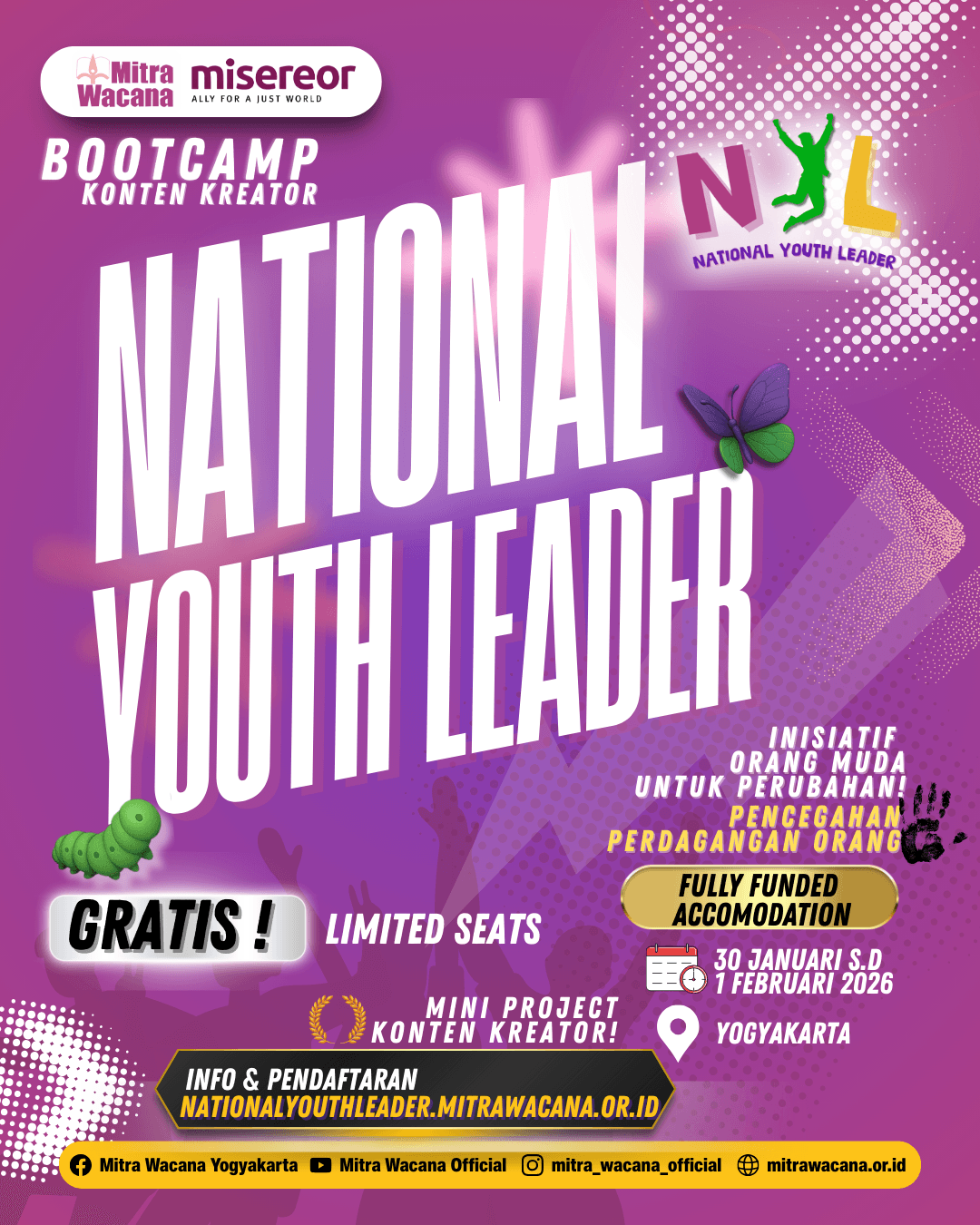Opini
Al- Kindi – Tokoh Aristotelian Neo-Platonis dari Timur dalam Sejarah Filsafat Islam
Published
2 years agoon
By
Mitra Wacana

Penulis : Nuril Islamiyah Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel)
Dalam buku History of Phylosophy in Islam (sejarah filasafat dalam islam) TJ. De Boer (1866-1942) menulis sosok seorang filsuf Al-Kindi, pandangan filsafat menurut Al-Kindi, bahkan De. Boer juga menuliskan teori Al-Kindi tentang pengetahuan. Sebenarnya dalam buku ini tidak hanya membahas tokoh filsuf muslim Al-Kindi saja, banyak tokoh-tokoh filsum muslin yang dijelaskan dalam buku ini. Dalam buku ini De. Boer menulis sejarah filsafat dalam islam, problematika dan perpindahan dari pemikiran satu ke pemikiran yang lain para filsof. Namun, dalam tulisan kali ini hanya membahas tokoh filsuf muslim Al-Kindi.
Nama aslinya yakni Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq Al-Kindi. Beliau berasal dari suku Kindah dan dari keturunan asli Arab, oleh karena itu, beliau disebut sebagai filsuf Arab. Al-Kindi lahir di kota Kufah pada awal abad ke-9. Silsilahnya dapat ditelusuri kembali ke para pangeran Kindah Kuno, meskipun masih belum pasti apakah namanya berasal dari mereka. Suku Kindah di Arab Selatan dalam banyak hal jauh lebih maju daripada suku-suku lain di peradaban luar. Banyak keluarga Kindah yang juga merupakan penduduk lama di Irak (Babylonia).
Al-Kindi merupakan seorang ilmuwan dengan pengetahuan yang luar biasa, seorang ahli sejarah, yang mampu menyerap semua pembelajaran dan budaya pada masanya. Pandangan teologisnya membawa cap dan stempel Mutazilah. Dia menulis secara khusus tentang kekuatan tindakan manusia, dan waktu kemunculannya, apakah sebelum tindakan atau bersamaan dengan tindakan. Al-Kindi sangat menekankan kemahakuasaan dan keilahian Tuhan. Teori Al-Kindi bertentangan dengan teori India dan Brahmanik yang mana teori tersebut menyatakan bahwa nalar adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang memadai. Al-Kindi justru membela kenabian, meskipun ia mencoba menyelaraskannya dengan akal. Perjumpaannya dengan berbagai sistem agama memaksanya untuk membandingkannya, dan ia menemukan elemen yang sama di dalamnya bahwa dunia bekerja karena ada penyebab utama, penyebab tunggal dan abadi, yang tidak dapat kita pahami secara tepat melalui pengetahuan kita.
Buku ini menjelaskan pandangan Al-Kindi bahwa dunia adalah karya Tuhan, namun pengaruh Tuhan terhadap makhluk-Nya disalurkan melalui banyak agen perantara. Semua eksistensi yang lebih tinggi mempengaruhi eksistensi yang lebih rendah, tetapi yang dipengaruhi (akibat) tidak memiliki pengaruh terhadap yang mempengaruhi (sebab), masing-masing berdiri sebagai skala eksistensi yang di atasnya terdapat skala eksistensi yang lain. Dalam semua peristiwa yang terjadi di dunia, ada kausalitas atau hukum sebab dan akibat yang melingkupi segala sesuatu. Realitas luhur dan segala aktivitas merupakan bagian dari roh atau pikiran, dan materi harus sesuai dengan kehendak roh. Di antara roh Tuhan dan dunia material atau inderawi adalah jiwa. Jiwa inilah yang pertama kali menyadari dunia yang memiliki dimensi ruang dan waktu. Dari jiwa inilah kemudian memancar dunia jiwa manusia. Pada hakikatnya, dalam watak dan cara kerjanya, jiwa manusia terikat pada tubuh yang menyatu dengannya, meskipun esensi spiritualnya independen dari tubuh. Al-Kindi selanjutnya mengungkapkan bahwa jiwa kita adalah substansi yang murni dan abadi yang turun dari dunia akal ke dunia indera, tetapi diberi ingatan tentang keadaan sebelumnya.
Buku ini juga menjelaskan teori pengetahuan Al-Kindi dalam kaitannya dengan dualitas etika dan metafisika, pengetahuan indrawi dan pengetahuan spiritual. Menurut teori ini, pengetahuan kita disampaikan melalui indera, atau pengetahuan yang diperoleh oleh akal. Indera memahami bentuk material, tetapi akal memahami bentuk spiritual. Seperti halnya apa yang ditangkap adalah pengetahuan melalui persepsi inderawi, maka apa yang ditangkap oleh akal adalah akal itu sendiri. Di sinilah doktrin tentang akal atau ruh atau pikiran dan nalar (‘aql) pertama kali muncul dalam sebuah bentuk yang, dengan sedikit perubahan, menempati sebagian besar pemikiran para filsuf Muslim di kemudian hari.
Dalam pandangannya Al-Kindi membagi ruh ke dalam empat kategori: Pertama, ruh yang selalu ada, selalu nyata, penyebab dan esensi dari segala sesuatu yang bersifat spiritual di dunia, oleh karena itu, apa yang keluar dari ruh pertama pastilah kebenaran. Kedua, ruh sebagai kemampuan bernalar atau potensi jiwa manusia. Ketiga, ruh sebagai kebiasaan atau kemampuan aktual jiwa, yang dapat digunakan setiap saat. Keempat, ruh sebagai aktivitas, yang dengan demikian realitas dalam jiwa dapat diwujudkan dalam kenyataan, yang terkadang tidak memiliki jiwa. Aktivitas yang terakhir ini, menurut Al-Kindi, merupakan tindakan manusia itu sendiri, sementara penyebab pertama ruh yang selalu hadir digambarkan oleh Al-Kindi sebagai ruh yang memanifestasikan potensi menjadi kebiasaan, atau realisasi yang mungkin.
Membaca buku History of Phylosophy in Islam para pembaca diajak untuk menyelami kearifan filsafat di dalam islam serta dialektika pemikiran satu filsof ke filsof lain. Namun, menurut saya pribadi ketika membaca buku ini, akan sulit memahami bagi orang awam karena buku yang aslinya menggunakan bahasa inggris dan diterjemahkan sehingga bahasanya sulit dipahami, dan bagi orang yang belum mengetahui sejarah filsafat akan sulit juga untuk bisa memahami isi dari buku ini.
Disarikan dari buku: History of Phylosophy in Islam | Penulis: TJ. De Boer | Penerbit: Forum 2019 | Tebal: +312 halaman | ISBN: 978-602-0753-07-2
You may like
Opini
Merevolusi Cara Kita Melihat Tugas Kuliah
Published
3 weeks agoon
29 December 2025By
Mitra Wacana

Nurisa Cahya Artika Farah,Mahasiswi semester 3 Program Studi Tadris (Pendidikan) Bahasa Indonesia, Fakultas Adab dan Bahasa, Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta.
Di dunia perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menjadi individu yang mandiri, kritis, dan kreatif dalam menghadapi berbagai tantangan akademik. Salah satu tantangan tersebut adalah tugas kuliah yang diberikan oleh dosen sebagai proses pembelajaran. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak mahasiswa justru menganggap tugas kuliah sebagai beban yang membebani pikiran. Mahasiswa lebih fokus pada nilai akhir ketimbang proses belajar yang seharusnya memperkaya pengetahuan dan keterampilan. Fenomena ini menjadi gambaran bahwa sebagian mahasiswa masih memandang tugas secara sempit, tanpa menyadari bahwa melalui tugas inilah kemampuan berpikir kritis serta tanggung jawab perkuliahan dapat terasah.
Banyak kalangan mahasiswa mengeluh akan tugas kuliah yang diberikan, mereka memandangnya sebagai beban yang menumpuk dan hanya sebatas untuk mendapatkan nilai, bukan proses pembelajaran. Hal ini membuat motivasi belajar menurun yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, seperti kurangnya minat, kesulitan konsentrasi, masalah pribadi, maupun kualitas hasil tugas yang tidak mencerminkan pemahaman sebenarnya. Padahal, esensi pendidikan tinggi bukan sebatas mengerjakan tugas, namun membangun cara berpikir kritis dan kreatif mahasiswa. Karena itu, saatnya mahasiswa merevolusi cara pandang terhadap tugas yang dianggap beban menjadi proses pembelajaran yang bermakna.
Perkuliahan mahasiswa sebenarnya tidak hanya belajar dari penjelasan dosen, tetapi juga dari proses mengerjakan tugas. Hal ini sejalan dengan Teori Konstruktivisme yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun dari individu berdasarkan pengalaman dan pemahaman. Seperti halnya dalam pemberian tugas kuliah ini mahasiswa tidak hanya menerima ilmu dari dosen, tetapi juga membentuk pemahaman sendiri melalui pengalaman belajar sebelumnya. Dalam konteks ini, tugas kuliah bukanlah tujuan akhir, tetapi sebagai sarana untuk membangun pemahaman terhadap suatu konsep. Misalnya, ketika mahasiswa diminta menulis esai, mereka tidak hanya terpaku dengan teori yang sudah ada, tetapi juga menyusun gagasan atau ide pribadi berdasarkan pemahaman konseptual dan berpikir kritis. Dengan demikian, tugas menjadi penghubung antara pengetahuan dan penerapan.
Namun, faktanya di lapangan masih banyak mahasiswa yang memandang tugas sebagai sesuatu yang dipaksakan untuk semata-mata demi nilai. Hal ini sejalan dengan rendahnya motivasi dalam diri berdasarkan teori Self-Determination. Mahasiswa akan termotivasi jika memiliki kebebasan pilihan dalam menyelesaikan tugas (autonomi), merasa mampu mengerjakan (kompetensi), dan merasa bahwa tugas memiliki hubungan dengan kehidupan mereka (keterhubungan). Dengan demikian, ketika diberi tugas yang memberikan kebebasan, kemampuan, serta keterhubungan, mahasiswa akan melihat tugas bukan sebagai beban, melainkan sebagai bentuk pengembangan diri.
Selain itu, konsep belajar bermakna dari David Ausubel juga relevan dalam konteks ini. Dalam perkuliahan, hal ini berarti tugas yang diberikan seharusnya berasal dari struktur pemikiran yang telah dimiliki mahasiswa. Misalnya, tugas proyek yang menuntut mahasiswa mengaitkan teori dengan pengalaman pribadi. Ketika mahasiswa menemukan keterkaitan tersebut, proses belajar menjadi bermakna. Mereka tidak sedang mengerjakan tugas dosen melainkan sedang menemukan diri dalam proses pembelajaran.
Pandangan teori humanistik juga memperkuat gagasan ini. Dalam pandangan ini, mahasiswa dipandang sebagai individu yang unik dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Tugas kuliah, seharusnya menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengekspresikan diri, mengeksplorasi nilai-nilai pribadi, dan mengembangkan potensi secara utuh. Tugas tidak hanya mengukur hasil akhir berupa angka, tetapi juga menilai proses berpikir, kreativitas, den refleksi diri mahasiswa.
Sebagai mahasiswa, saya kerap melihat beberapa mahasiswa bahwa tugas baru benar-benar dipahami maknanya setelah dikerjakan, bukan saat materi disampaikan oleh dosen. Dari tugaslah mahasiswa belajar berpikir kritis, mampu mengelola waktu, dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa tugas kuliah sejatinya memiliki peran penting dalam membentuk kualitas mahasiswa, asalkan dipahami dan dijalani dengan cara pandang yang tepat.
Masalahnya sistem pendidikan kita masih berorientasi pada hasil bukan proses. Banyak mahasiswa mengerjakan tugas hanya untuk mendapatkan nilai bukan karena ingin memahami makna apa yang mereka pelajari. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan paradigma, baik dari pihak dosen maupun mahasiswa. Merevolusi cara pandang terhadap tugas kuliah berarti menempatkan kembali tugas sebagai bagian dari proses pembelajaran bukan sebagai beban mahasiswa. Ketika mahasiswa mulai melihat tugas sebagai ruang pengembangan diri mereka akan lebih bersemangat, produktif, dan berdaya saing. Tak hanya mahasiswa, dosen pun akan lebih mudah menilai kualitas pemahaman mahasiswa. Dengan demikian, revolusi ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hasil belajar, tetapi juga membentuk generasi mahasiswa yang berpikir kritis, reflektif, dan siap menghadapi tantangan di kehidupan nyata. Hal yang paling berharga dari tugas kuliah bukan hanya tentang nilai yang berupa angka melainkan proses belajar yang akan menambah pemahaman.