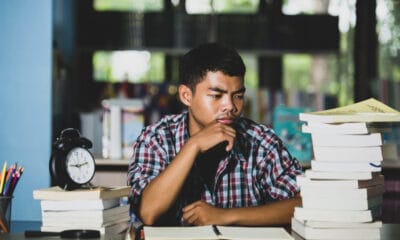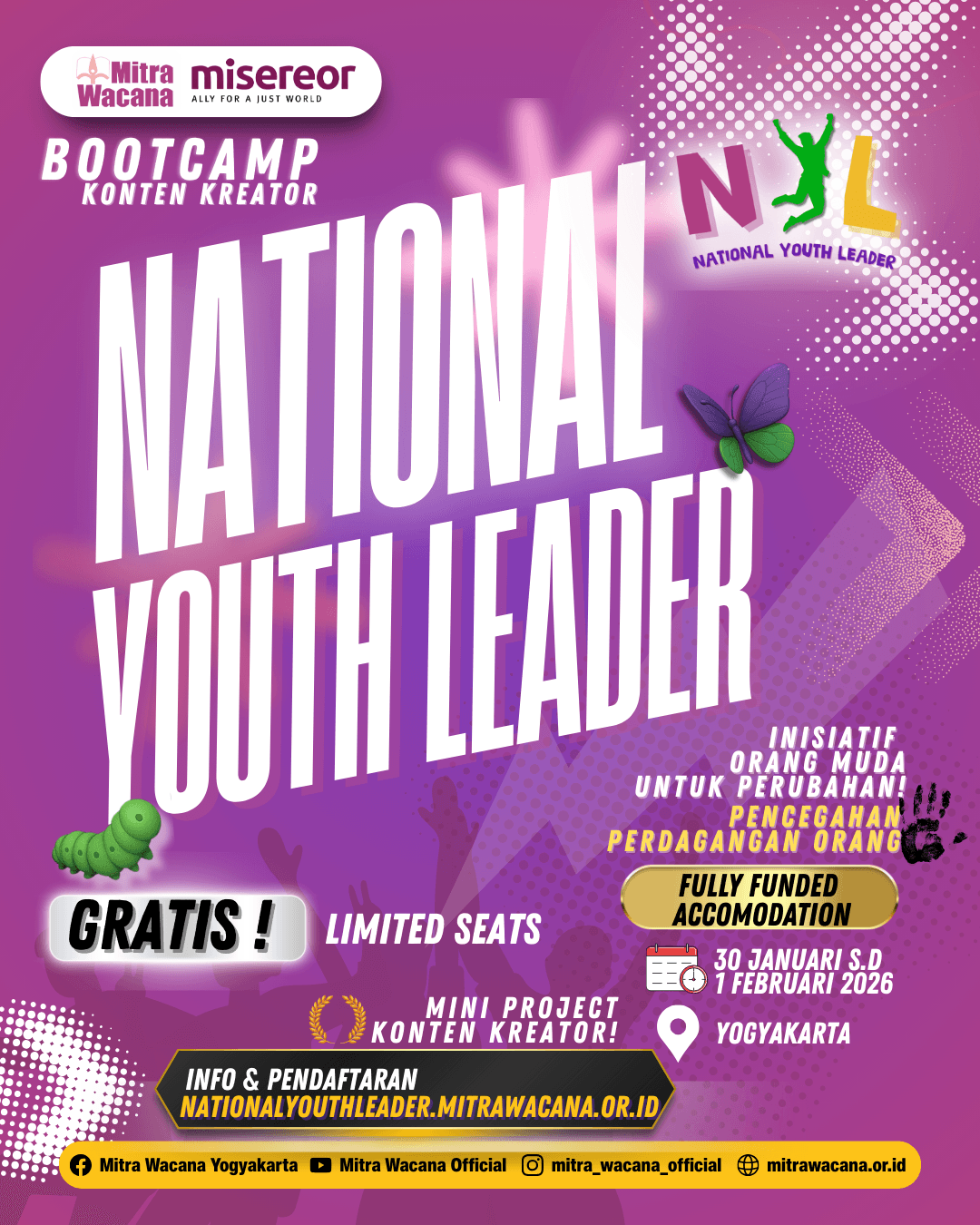Opini
Mahasiswa? Peran dan Permasalahannya
Published
2 years agoon
By
Mitra Wacana

La Ode Muhmeliadi, Mahasantri RTM Darul Falah Cawan Klaten
Mahasiswa itu identik dengan perubahan sosial. Entah itu perubahan sistem politik-ekonomi dan sosial-budaya, ataupun dalam perubahan sikap (tingkah laku) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kalau secara bahasa, adalah penggabungan anatar kata “maha” dan “siswa”. Dalam KBBI, kata “maha” berarti amat atau teramat. Atau dalam arti lain, kata “maha” yaitu sangat, atau sesuatu yang melampaui. Sedangkan “siswa” adalah murid atau peserta didik atau pelajar (dalam jenjang sekolah dasar ataupun menengah).
Dapatlah kita gabungkang makna dari “Mahasiswa” yaitu seseorang yang belajar (murid) dengan kapasitas keilmuan yang cukup melampaui atau teramat tinggi. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 12 Tahun 2012, mahasiswa adalah peserta didik dalam jenjang Pendidikan Tinggi. Sehingga tempat belajarnya bukan lagi sekolah, tetapi perguruan tinggi (Universitas atau Institut).
Mahasiswa adalah pelopor dalam perubahan (agen of change), pengontrol permasalahan sosial (agen social control), dan sebagai generasi penerus kemerdekaan yang kokoh dan kuat (iron stock). Dengan itu setiap mahasiswa harus mampu menjadi teladan perubahan dan moral yang baik (moral force), serta selalu taat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kebudayaan, dan kebangsaan (guardian of value).
Semua mahasiswa adalah aktivis dari setiap bidangnya masing-masing. Lantas bagaimana dengan mahasiswa hedonis (sikap yang selalu foya-foya, bergemerlapan, atau senang-senang), pragmatis (mencari keuntungan dengan sebab-akibat atau nilai guna untuk dirinya), apatis (sikap tidak peduli dengan yang lain, acuh tak acuh) dan oportunis (mementingkan untuk keuntungan diri sendiri), masih pantaskah disebut mahasiswa?
Dalam buku Gerakan Mahasiswa dalam Perspektif Perubahan Politik Nasional, Dody Rudianto (2010) menuliskan ada tiga tipe mahasiswa aktivis. Pertama, Mahasiswa Aktivis Aktif. Kedua, Mahasiswa Aktivis Intelektual. Dan ketiga, Mahasiswa Aktivis Puritan.
Mahasiswa Aktivis Aktif yaitu mahasiswa yang aktif di kampus (kuliah, riset, pengembangan minat, dan pelatihan-pelatihan tertentu), aktif menulis di media cetak atau media online, dan aktif meluruskan problematika sosail (menyuarakan aspirasi masyarakat).
Mahasiswa Aktivis Intelektual yaitu mahasiswa yang aktif di kampus (kuliah, riset, pengembangan minat, dan pelatihan-pelatihan tertentu), aktif menulis di media cetak atau media online, tetapi tidak aktif dalam menyuarakan aspirasi rakyat.
Sementara Mahasiswa Aktivis Puritan yaitu mahasiswa yang hanya aktif mengikuti perkuliahan, pengembangan minat dan bakat dari study club atau komunitas tertentu, melaksanakan penelitian berbasis keilmuannya, dan pengembangan diri dengan mengikuti pelatihan atau seminar-seminar tertentu.
Jelaslah sudah tentang hal ini, ‘siapa itu mahasiswa’. Adakah perubahan siklus perkembangan dan pola pergerakan masaiswa dari tahun ke tahun? Ada 5 periode gerakan mahasiswa di Indonesia, baik perubahan tingkah laku maupun dalam perubahan sistem bernegara
Periode Pertama. Mahasiswa terlibat dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Fase ini, mahasiswa dari pelbagai kalangan atau organisasi sosial kemasyarakatan ikut andil dengan mengangkat senjata melawan Belanda. Hal itu dilakukan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Periode ini disebut dengan periode kemerdekaan, yang bermula dari tahun 1945 hingga 1949.
Periode Kedua. Mahasiswa dengan gerakan demonstrasi akibat permasalahan pada sistem pemerintahan indonesia. Hal ini bermula dari dekrit presiden 1959 dan keputusan presiden tentang Trikora (Tiga Komando Rakyat) di masa Orde Lama. Maka pada waktu itu mahasiswa menuntut tiga hal, yaitu pembubaran PKI, perombakan Kabinet Dwikora, dan penurunan harga. Gerakan ini pada tahun 1966. Selanjutnya, aksi masa (Periode Demonstrasi) terus dipakai sebagai jalan perubahan sosial, berlangsung pada tahun 1974, lebih dikenal dengan gerakan Malari (Malapetaka 15 Januari) 1974. Setelah peristiwa Malari, maka pemerintahan Orde Baru mempertegas terkait kebebasan dan ideologi dengan pemanfaatan Angkatan Bersentaja Republik Indonesia, hingga banyak mahasiswa yang sulit menyampaikan aspirasi.
Periode Ketiga. Periode ini, Mahasiswa berjuang dengan tuliisan dan seni. Seperti musik yang bergendre HAM (Hak Asasi Manusia), keadilan dan kesejahteraan. Grup-grup lawak yang bertujuan sebagai wadah kritik pemerintah, teaterikal jalanan, puisi-puisi dan artikel sosial, baik yang dimuat di media cetak, majalah, dan selembaran-selembaran. Hingga dibuatlah buku-buku membangkitkan proses berpikir dan buku-buku pergakan untuk perubahan sosial. Masa ini adalah salah satu masa sulit para mahasiswa; banyak yang diculik, disiksa, dihilangkan identitasnya, dan hal-hal buruk lainnya. periode ini bermula setelah Malari 1974 hingga 1998. Penyebutan untuk periode ini adalah Periode Intelektual (masa kebangkitan seni dan ilmu pengetahuan).
Periode Kempat. Periode ini adalah puncak keberhasilan dari propaganda yang dibangun para mahasiswa di periode ketiga. Mahasiswa difase ini, mereka berkalaborasi dengan berbagai tokoh politik, organisasi buruh-tani, tokoh-tokoh pemuda, cendikiawan dan akdemisi, dan pers. Gerakan ini ditandai dengan krisis ekonomi dan buruknya kekuasaan (sistem pemerintahan) Orde Baru, hingga puncaknya adalah menggulingkan rezim Orde Baru pada tahun 1998. Periode ini disebut Masa Reformasi dan berlangsung hingga tahun 2004.
Periode Kelima. Periode ini, mahasiswa sudah lebih banyak eksis di dunia digitalisasi. Proses informasi semakin cepat dengan kemajuan teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi berkembang semakin luas. Media sosial adalah sarana utama mahasiswa di periode ini. Penyebutan pada fase ini yaitu Periode Digitalisasi (Information Technology), yang bermula dari tahun 2004 hingga sekarang.
Dengan pemanfaatan teknologi modern, mahasiswa saat ini seperti termanjakan dengan keadaan. Berpikir sudah lebih praktis, banyak copy-paste, sulit bersosialisasi, malas bertindak, sedikitnya keaktifan dalam organisasi, ikut-ikutan, kuliah hanya untuk cari kerja, dan masih banyak lagi. Dengan masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa, maka peran agen of change and control social tidak lagi bermanfaat, tidak berhasil menyuarakan aspirasi rakyat. Dikarenakan nilai-nilai sejarah bangsa banyak terlupakan dan nilai-nilai agama dan budaya banyak yang ditinggalkan.
Dari problematika yang ada, terkumpullah 10 permasalahan inti (pokok) mahasiswa yang dianggap sepele atau yang dianggap biasa. Masalah tersebut yaitu, Tidak menjalankan kewajiban agama; Malas membaca; Tertipu dengan penampilan; Hanya pandai retorika; Tidak peduli (acuh tak acuh) dengan problematika sosial; Sangat aktif bermasyarakat, tetapi kuliah terlupakan; Kebanyakan main game online, scroli media sosial (TikTok, IG dan sejenisnya), dan Rebahan; Ketidakstabilan dalam manajemen waktu; Pacaran, hal yang melampaui batas; dan, Tidak mau belajar ilmu agama.
Pada hakikatnya, mahasiswa harus aktif dalam segala hal. Harus aktif di ruang kelas, aktif berorganisasi, aktif membaca dan menulis, aktif berdiskusi, aktif meneliti permasalahan sosial, aktif dalam membela kebenaran, dan seterusnya. Sehingga label aktivis sangat tepat digaungkan kepadanya. Karena sebaik-baik mahasiswa adalah mahasiswa yang selalu aktif dan berani menyuarakan kebenaran dimanapun berada.
You may like
Opini
Merevolusi Cara Kita Melihat Tugas Kuliah
Published
3 weeks agoon
29 December 2025By
Mitra Wacana

Nurisa Cahya Artika Farah,Mahasiswi semester 3 Program Studi Tadris (Pendidikan) Bahasa Indonesia, Fakultas Adab dan Bahasa, Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta.
Di dunia perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menjadi individu yang mandiri, kritis, dan kreatif dalam menghadapi berbagai tantangan akademik. Salah satu tantangan tersebut adalah tugas kuliah yang diberikan oleh dosen sebagai proses pembelajaran. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak mahasiswa justru menganggap tugas kuliah sebagai beban yang membebani pikiran. Mahasiswa lebih fokus pada nilai akhir ketimbang proses belajar yang seharusnya memperkaya pengetahuan dan keterampilan. Fenomena ini menjadi gambaran bahwa sebagian mahasiswa masih memandang tugas secara sempit, tanpa menyadari bahwa melalui tugas inilah kemampuan berpikir kritis serta tanggung jawab perkuliahan dapat terasah.
Banyak kalangan mahasiswa mengeluh akan tugas kuliah yang diberikan, mereka memandangnya sebagai beban yang menumpuk dan hanya sebatas untuk mendapatkan nilai, bukan proses pembelajaran. Hal ini membuat motivasi belajar menurun yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, seperti kurangnya minat, kesulitan konsentrasi, masalah pribadi, maupun kualitas hasil tugas yang tidak mencerminkan pemahaman sebenarnya. Padahal, esensi pendidikan tinggi bukan sebatas mengerjakan tugas, namun membangun cara berpikir kritis dan kreatif mahasiswa. Karena itu, saatnya mahasiswa merevolusi cara pandang terhadap tugas yang dianggap beban menjadi proses pembelajaran yang bermakna.
Perkuliahan mahasiswa sebenarnya tidak hanya belajar dari penjelasan dosen, tetapi juga dari proses mengerjakan tugas. Hal ini sejalan dengan Teori Konstruktivisme yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun dari individu berdasarkan pengalaman dan pemahaman. Seperti halnya dalam pemberian tugas kuliah ini mahasiswa tidak hanya menerima ilmu dari dosen, tetapi juga membentuk pemahaman sendiri melalui pengalaman belajar sebelumnya. Dalam konteks ini, tugas kuliah bukanlah tujuan akhir, tetapi sebagai sarana untuk membangun pemahaman terhadap suatu konsep. Misalnya, ketika mahasiswa diminta menulis esai, mereka tidak hanya terpaku dengan teori yang sudah ada, tetapi juga menyusun gagasan atau ide pribadi berdasarkan pemahaman konseptual dan berpikir kritis. Dengan demikian, tugas menjadi penghubung antara pengetahuan dan penerapan.
Namun, faktanya di lapangan masih banyak mahasiswa yang memandang tugas sebagai sesuatu yang dipaksakan untuk semata-mata demi nilai. Hal ini sejalan dengan rendahnya motivasi dalam diri berdasarkan teori Self-Determination. Mahasiswa akan termotivasi jika memiliki kebebasan pilihan dalam menyelesaikan tugas (autonomi), merasa mampu mengerjakan (kompetensi), dan merasa bahwa tugas memiliki hubungan dengan kehidupan mereka (keterhubungan). Dengan demikian, ketika diberi tugas yang memberikan kebebasan, kemampuan, serta keterhubungan, mahasiswa akan melihat tugas bukan sebagai beban, melainkan sebagai bentuk pengembangan diri.
Selain itu, konsep belajar bermakna dari David Ausubel juga relevan dalam konteks ini. Dalam perkuliahan, hal ini berarti tugas yang diberikan seharusnya berasal dari struktur pemikiran yang telah dimiliki mahasiswa. Misalnya, tugas proyek yang menuntut mahasiswa mengaitkan teori dengan pengalaman pribadi. Ketika mahasiswa menemukan keterkaitan tersebut, proses belajar menjadi bermakna. Mereka tidak sedang mengerjakan tugas dosen melainkan sedang menemukan diri dalam proses pembelajaran.
Pandangan teori humanistik juga memperkuat gagasan ini. Dalam pandangan ini, mahasiswa dipandang sebagai individu yang unik dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Tugas kuliah, seharusnya menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengekspresikan diri, mengeksplorasi nilai-nilai pribadi, dan mengembangkan potensi secara utuh. Tugas tidak hanya mengukur hasil akhir berupa angka, tetapi juga menilai proses berpikir, kreativitas, den refleksi diri mahasiswa.
Sebagai mahasiswa, saya kerap melihat beberapa mahasiswa bahwa tugas baru benar-benar dipahami maknanya setelah dikerjakan, bukan saat materi disampaikan oleh dosen. Dari tugaslah mahasiswa belajar berpikir kritis, mampu mengelola waktu, dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa tugas kuliah sejatinya memiliki peran penting dalam membentuk kualitas mahasiswa, asalkan dipahami dan dijalani dengan cara pandang yang tepat.
Masalahnya sistem pendidikan kita masih berorientasi pada hasil bukan proses. Banyak mahasiswa mengerjakan tugas hanya untuk mendapatkan nilai bukan karena ingin memahami makna apa yang mereka pelajari. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan paradigma, baik dari pihak dosen maupun mahasiswa. Merevolusi cara pandang terhadap tugas kuliah berarti menempatkan kembali tugas sebagai bagian dari proses pembelajaran bukan sebagai beban mahasiswa. Ketika mahasiswa mulai melihat tugas sebagai ruang pengembangan diri mereka akan lebih bersemangat, produktif, dan berdaya saing. Tak hanya mahasiswa, dosen pun akan lebih mudah menilai kualitas pemahaman mahasiswa. Dengan demikian, revolusi ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hasil belajar, tetapi juga membentuk generasi mahasiswa yang berpikir kritis, reflektif, dan siap menghadapi tantangan di kehidupan nyata. Hal yang paling berharga dari tugas kuliah bukan hanya tentang nilai yang berupa angka melainkan proses belajar yang akan menambah pemahaman.