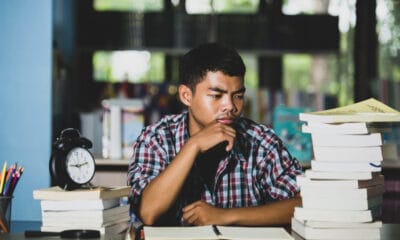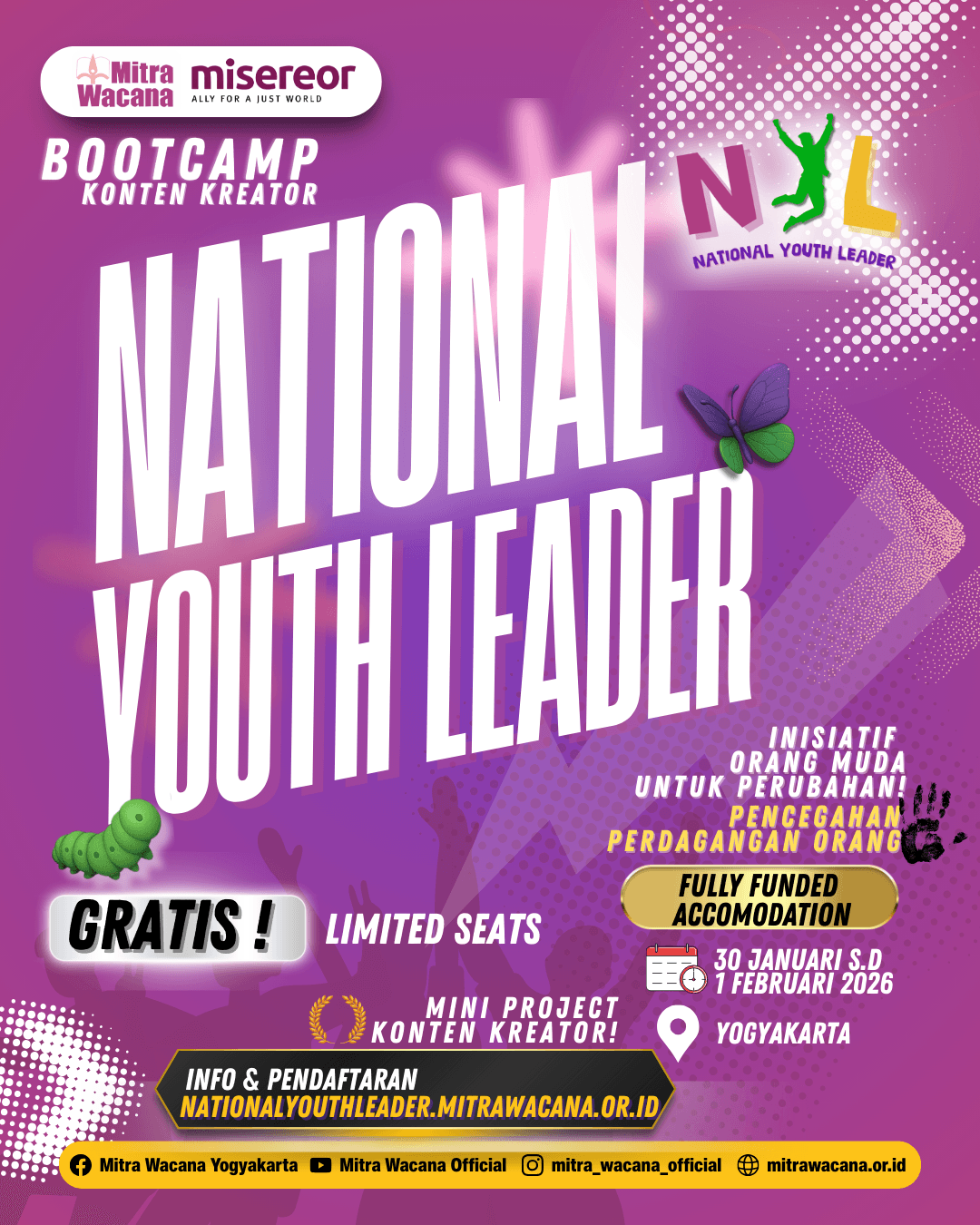Opini
Pengetahuan Perempuan dan Spirit Berpikir Kritis dalam Islam
Published
1 year agoon
By
Mitra Wacana

Satrio Dwi Haryono
Komunitas Dianoia, Sukoharjo
Dalam fakta sejarah, perempuan sering kali dipinggirkan dan dianggap sebagai gender kelas dua. Sehingga akses terhadap berbagai hal perempuan seringkali mengalami keterbatasan. Hal tersebut bekerja secara sistemik melalui berbagai kerja pengetahuan seperti kebudayaan dan pendidikan serta didorong dengan stereotipe dan subordinasi.
Sebut saja fenomena perempuan sebagai properti pada zaman pra-Islam dan aturan di Inggris tahun 1805 yang masih melegalkan penjualan perempuan merupakan segelintir fakta di panggung sejarah bahwa perempuan dipinggirkan (Nur Rofiah, 2020). Hal ini tentunya menyebabkan perempuan termaginalkan dan terbelakang. Ketidakberdayaan perempuan sangat kentara disini. Dimana perempuan mengalami berbagai dampak negatif seperti ketidaksetaraan ekonomi, tingkat kesehatan yang rendah bahkan partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik yang (di)minim(kan).
Secara ideal, kemunduran dan kemajuan perempuan tentu akan sangat dipengaruhi dengan pengetahuan perempuan dan cara perempuan mengetahui. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan sehingga dalam konteks ini dianalogikan sebagai sepasang sepatu yang sempurna. Mary Belenky, Blythe, Nancy Goldberger Jill Tarule dari Ferris State University merancang suatu teori unik yakni Women`s Ways of Knowledge yang menyoal tentang lima tingkatan cara perempuan mengetahui .
Pertama, diam, pada tingkatan ini, perempuan tidak menggunakan daya akalnya sama sekali. Perempuan bergantung pada subyek lain yang memberikan pengetahuan kepadanya. Pengetahuan yang diterima tidak hanya bersifat afirmatif namun juga negatif bahkan koersif. Pengetahuan yang diterima perempuan memiliki beragam wujud yang tak hanya verbal namun juga non verbal bahkan dengan bentuk seperti bentakan, tendangan atau kekerasan. Tidak hanya sebagai a silent knower, melainkan perempuan juga sebagai silenced knower, atau orang yang dibungkam.
Kedua, pengetahuan terterima (received knowledge), berbeda dengan tingkatan yang pertama, di tingkatan ini perempuan menyakini bahwa pengetahuan sebagai kebenaran semata. Berbagai upaya dilakukan perempuan walaupun tanpa mencari pembanding dengan sumber pengetahuan lainnya, perempuan secara total memercaya otoritas seperti media sosial, sekolah, kuliah, artikel, podcast, bahkan majelis taklim. Pengetahuan yang diterimanya pun diresapi dan disebarkan dengan cepat. Padahal dalam kandungan pengetahuan memuat unsur politis dan ideologis pemegang otoritas. Dengan itu, maka tak heran jika kini masih berkeliaran informasi palsu dan tak sedikit yang malah mendiskreditkan perempuan yang disebarkan oleh perempuan itu sendiri.
Ketiga, pengetahuan subyektif (subjective knowledge), pada tingkatan yang lebih tinggi ini, perempuan menggunakan subjektivitas dirinya sebagai bahan pertimbangan atas informasi yang ia terima. Bahan pertimbangan tersebut umumnya bersumber dari pengalaman personal dan ’emosi’ perempuan. Sebut saja ketika perempuan mendapatkan informasi mengenai kerja-kerja domestik yang menjadi kewajibannya ia akan menimbang dengan pengetahuan yang ia terima dari pengalamannya bertemu dengan seseorang, melihat atau membaca dalam sosial media tentang kiprah perempuan dalam ranah publik.
Keempat, pengetahuan prosedural (procedural knowledge), perempuan mulai menyadari pengetahuan pada ranah objektif. Ketika ia menerima suatu informasi ia akan menimbang dengan sumber yang berbeda dan akan mengolahnya sehingga memunculkan kesimpulan yang bulat. Sehingga perempuan tidak lagi bersandar pada pengalaman personal namun juga menimbangnya dengan sumber-sumber lain dan merangkainya.
Kelima, pengetahuan kukuh (constructed knowledge), pada tingkatan yang paling tinggi ini perempuan tidak sekadar merangkai berbagai sumber pengetahuan dan merangkainya melainkan bersandar pada kerangka objektif dan melakukan verifikasi mendalam serta meletakkan pengetahuan secara kontekstual. Dimana pengetahuan yang ia terima secara sadar maupun tidak sadar dihubungkan dengan subjektivitas perempuan dan ditimbang secara objektif lalu diletakkan pada ranah kontekstual. Pengetahuan yang ia peroleh pun tidak hanya bersandar pada otoritasnya namun pada kuat tidaknya argumentasi yang berada pada inti pengetahuan tersebut.
Tak dapat dinafikan bahwa ‘tingkatan cara perempuan mengetahui’ ini tidak terjadi pada perempuan secara menyeluruh namun terdapat bagian-bagian atau bidang-bidang tertentu yang dikuasai oleh perempuan itu sendiri. Namun, tak dapat dinafikan pula latar belakang historis perempuan itu sendiri juga memengaruhi ‘ yang turut memengaruhi tingkatan mana yang sedang dilalui perempuan tersebut.
Antara ‘cara perempuan mengetahui’ dan pengetahuan perempuan pun harus berjalan secara bersamaan. Aneh rasanya, jika ‘cara perempuan mengetahui’ pada tahap lima namun pengetahuan perempuan tersebut sangat minim, begitu pula sebaliknya.
Dalam Islam pun pengguanaan akal untuk secara aktif diperintahkan Allah SWT dalam berbagai firmannya. Bahkan kata ‘akal’ dalam al-Qur`an berbentuk kata kerja bukan kata benda. Maka, akal disini seyogyanya digunakan secara maksimal dan juga tidak secara serampangan tanpa melibatkan pengalaman, mengingat pengelaman juga tak lepas dari kerja-kerja akal. Serta prosedur pengetahuan yang objektif dan kontekstualisasi pengetahuan juga mustahil tanpa melibatkan peran akal.
Prinsip berpikir kritis pun diperintahkan Allah SWT dengan tegas pada Surat al-`Alaq (1-5), Allah SWT menekankan kata ‘Iqra’ secara berulang-ulang. Tentunya, kata ‘Iqra’ tidak sesederhana translasi ‘bacalah’, namun mencakup seluruh kemampuan berpikir untuk mengeksplorasi dan memahami suatu hal.
Perintah Iqra pada surat tersebut juga tidak diikuti oleh objek tertentu yang bermakna bahwa apa saja yang ada di dunia ini harus kita pahami dan dieksplorasi secara kritis.
Sehingga dengan ‘cara perempuan mengetahui’, pengetahuan perempuan dan berpikir kritis dapat menciptakan peradaban yang adil dan tidak diskriminatif. Pada akhirnya, dengan bekal tersebut mengembang pada berbagai bidang seperti meningkatnya akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan serta partisipasi sosial dan publik.
You may like
Opini
Merevolusi Cara Kita Melihat Tugas Kuliah
Published
3 weeks agoon
29 December 2025By
Mitra Wacana

Nurisa Cahya Artika Farah,Mahasiswi semester 3 Program Studi Tadris (Pendidikan) Bahasa Indonesia, Fakultas Adab dan Bahasa, Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta.
Di dunia perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menjadi individu yang mandiri, kritis, dan kreatif dalam menghadapi berbagai tantangan akademik. Salah satu tantangan tersebut adalah tugas kuliah yang diberikan oleh dosen sebagai proses pembelajaran. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak mahasiswa justru menganggap tugas kuliah sebagai beban yang membebani pikiran. Mahasiswa lebih fokus pada nilai akhir ketimbang proses belajar yang seharusnya memperkaya pengetahuan dan keterampilan. Fenomena ini menjadi gambaran bahwa sebagian mahasiswa masih memandang tugas secara sempit, tanpa menyadari bahwa melalui tugas inilah kemampuan berpikir kritis serta tanggung jawab perkuliahan dapat terasah.
Banyak kalangan mahasiswa mengeluh akan tugas kuliah yang diberikan, mereka memandangnya sebagai beban yang menumpuk dan hanya sebatas untuk mendapatkan nilai, bukan proses pembelajaran. Hal ini membuat motivasi belajar menurun yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, seperti kurangnya minat, kesulitan konsentrasi, masalah pribadi, maupun kualitas hasil tugas yang tidak mencerminkan pemahaman sebenarnya. Padahal, esensi pendidikan tinggi bukan sebatas mengerjakan tugas, namun membangun cara berpikir kritis dan kreatif mahasiswa. Karena itu, saatnya mahasiswa merevolusi cara pandang terhadap tugas yang dianggap beban menjadi proses pembelajaran yang bermakna.
Perkuliahan mahasiswa sebenarnya tidak hanya belajar dari penjelasan dosen, tetapi juga dari proses mengerjakan tugas. Hal ini sejalan dengan Teori Konstruktivisme yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun dari individu berdasarkan pengalaman dan pemahaman. Seperti halnya dalam pemberian tugas kuliah ini mahasiswa tidak hanya menerima ilmu dari dosen, tetapi juga membentuk pemahaman sendiri melalui pengalaman belajar sebelumnya. Dalam konteks ini, tugas kuliah bukanlah tujuan akhir, tetapi sebagai sarana untuk membangun pemahaman terhadap suatu konsep. Misalnya, ketika mahasiswa diminta menulis esai, mereka tidak hanya terpaku dengan teori yang sudah ada, tetapi juga menyusun gagasan atau ide pribadi berdasarkan pemahaman konseptual dan berpikir kritis. Dengan demikian, tugas menjadi penghubung antara pengetahuan dan penerapan.
Namun, faktanya di lapangan masih banyak mahasiswa yang memandang tugas sebagai sesuatu yang dipaksakan untuk semata-mata demi nilai. Hal ini sejalan dengan rendahnya motivasi dalam diri berdasarkan teori Self-Determination. Mahasiswa akan termotivasi jika memiliki kebebasan pilihan dalam menyelesaikan tugas (autonomi), merasa mampu mengerjakan (kompetensi), dan merasa bahwa tugas memiliki hubungan dengan kehidupan mereka (keterhubungan). Dengan demikian, ketika diberi tugas yang memberikan kebebasan, kemampuan, serta keterhubungan, mahasiswa akan melihat tugas bukan sebagai beban, melainkan sebagai bentuk pengembangan diri.
Selain itu, konsep belajar bermakna dari David Ausubel juga relevan dalam konteks ini. Dalam perkuliahan, hal ini berarti tugas yang diberikan seharusnya berasal dari struktur pemikiran yang telah dimiliki mahasiswa. Misalnya, tugas proyek yang menuntut mahasiswa mengaitkan teori dengan pengalaman pribadi. Ketika mahasiswa menemukan keterkaitan tersebut, proses belajar menjadi bermakna. Mereka tidak sedang mengerjakan tugas dosen melainkan sedang menemukan diri dalam proses pembelajaran.
Pandangan teori humanistik juga memperkuat gagasan ini. Dalam pandangan ini, mahasiswa dipandang sebagai individu yang unik dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Tugas kuliah, seharusnya menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengekspresikan diri, mengeksplorasi nilai-nilai pribadi, dan mengembangkan potensi secara utuh. Tugas tidak hanya mengukur hasil akhir berupa angka, tetapi juga menilai proses berpikir, kreativitas, den refleksi diri mahasiswa.
Sebagai mahasiswa, saya kerap melihat beberapa mahasiswa bahwa tugas baru benar-benar dipahami maknanya setelah dikerjakan, bukan saat materi disampaikan oleh dosen. Dari tugaslah mahasiswa belajar berpikir kritis, mampu mengelola waktu, dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa tugas kuliah sejatinya memiliki peran penting dalam membentuk kualitas mahasiswa, asalkan dipahami dan dijalani dengan cara pandang yang tepat.
Masalahnya sistem pendidikan kita masih berorientasi pada hasil bukan proses. Banyak mahasiswa mengerjakan tugas hanya untuk mendapatkan nilai bukan karena ingin memahami makna apa yang mereka pelajari. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan paradigma, baik dari pihak dosen maupun mahasiswa. Merevolusi cara pandang terhadap tugas kuliah berarti menempatkan kembali tugas sebagai bagian dari proses pembelajaran bukan sebagai beban mahasiswa. Ketika mahasiswa mulai melihat tugas sebagai ruang pengembangan diri mereka akan lebih bersemangat, produktif, dan berdaya saing. Tak hanya mahasiswa, dosen pun akan lebih mudah menilai kualitas pemahaman mahasiswa. Dengan demikian, revolusi ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hasil belajar, tetapi juga membentuk generasi mahasiswa yang berpikir kritis, reflektif, dan siap menghadapi tantangan di kehidupan nyata. Hal yang paling berharga dari tugas kuliah bukan hanya tentang nilai yang berupa angka melainkan proses belajar yang akan menambah pemahaman.