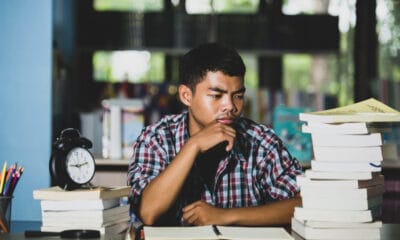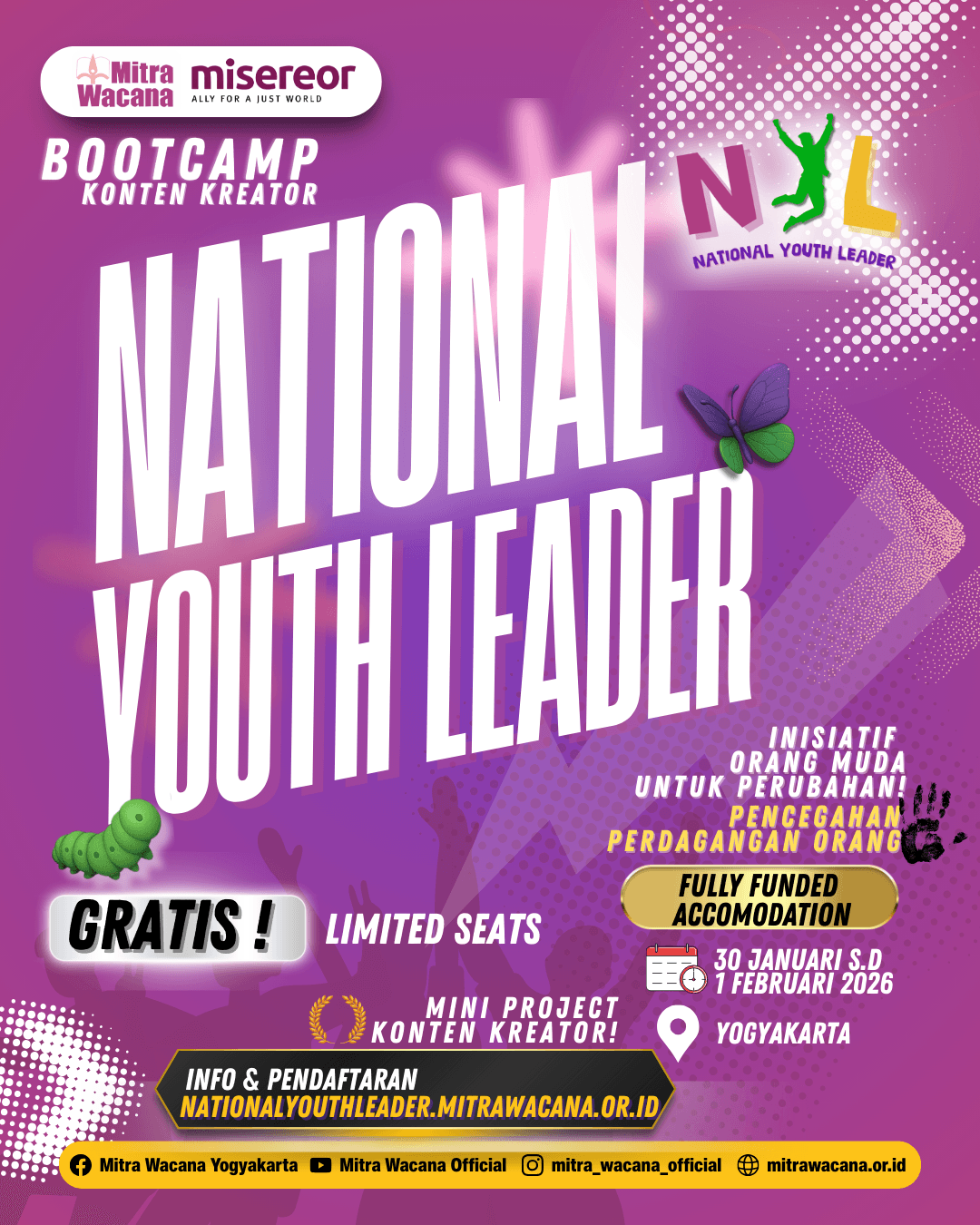Opini
Asa Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Tengah Gempuran Polarisasi
Published
10 months agoon
By
Mitra Wacana
Indonesia, dengan segala keragamannya, terus berupaya menjaga kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB). Meskipun konstitusi telah menjamin hak tersebut, kenyataan di lapangan sering kali menunjukkan sebaliknya. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang dikenal sebagai “Kota Pendidikan”, “Kota Toleransi”, dan “Kota Budaya”, seyogianya menjadi cerminan harmoni. Namun, dengan gelar tersebut, Yogyakarta juga menghadapi tantangan dalam merawat keberagaman. Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar memelihara kebebasan itu, atau justru membiarkan batas-batas perbedaan makin menggejala?
Laporan dari SETARA Institute mengungkapkan adanya 217 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) sepanjang tahun 2023, yang mencatat total 329 tindakan pelanggaran. Ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2022, yang tercatat 175 kasus dengan 333 tindakan pelanggaran. Dari total 329 tindakan, sebanyak 114 dilakukan oleh aktor negara, sementara 215 berasal dari aktor non-negara. Pelanggaran yang dilakukan oleh aktor negara paling banyak berasal dari pemerintah daerah (40 tindakan), diikuti oleh kepolisian (24 tindakan), Satpol PP (10 tindakan), TNI (8 tindakan), Forkopimda (6 tindakan), dan institusi pendidikan (4 tindakan).
Di sisi lain, dari aktor non-negara, warga menjadi pelaku dengan 78 tindakan, diikuti oleh individu (19 tindakan), Majelis Ulama Indonesia (17 tindakan), organisasi kemasyarakatan keagamaan (8 tindakan), dan warga negara asing (5 tindakan). Lonjakan ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap kebebasan beragama masih merupakan isu penting di Indonesia. Pelanggaran KBB dapat berbentuk penolakan pendirian tempat ibadah, diskriminasi terhadap kelompok keagamaan, hingga persekusi terhadap penganut kepercayaan tertentu.
Meskipun DIY sering dipandang sebagai daerah yang mengedepankan nilai-nilai toleransi, beberapa insiden intoleransi tetap terjadi. Data dari SETARA Institute menunjukkan bahwa DIY termasuk dalam sepuluh provinsi dengan jumlah kasus pelanggaran KBB yang cukup serius. Salah satu contoh yang mencuat adalah kasus pemotongan salib pada nisan Albertus Slamet Sugihardi di Kotagede pada tahun 2023. Salib tersebut dipotong agar menyerupai huruf “T”, dianggap sebagai syarat agar jenazah dapat dimakamkan di kompleks TPU setempat. Di tahun yang sama, Kabupaten Kulon Progo sempat ramai diperbincangkan akibat insiden penutupan patung Bunda Maria di Dusun Degolan, Bumirejo, Lendah, yang ditutupi terpal atas desakan sekelompok orang yang mengatasnamakan organisasi Islam. Meski patung tersebut berada di area rumah doa, penutupan tetap dilakukan.
Contoh lainnya antara lain penolakan terhadap panewu non-muslim oleh sebagian warga di Kapanewon Pajangan, Bantul, pada tahun 2017, dengan alasan mayoritas penduduk wilayah tersebut beragama Islam. Bahkan, pada Mei 2022, sekelompok orang membubarkan sebuah kebaktian yang berlangsung di rumah seorang warga di Sleman, dengan alasan acara tersebut tidak memiliki izin resmi dan berpotensi mengganggu ketertiban.
Sebuah penelitian oleh Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sebagian besar pelajar di Yogyakarta memiliki pemahaman agama yang cenderung eksklusif, yang dapat berpotensi meningkatkan intoleransi. Studi lain dari Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) pada 2010/2011 menyebutkan bahwa 48,9% siswa Sekolah Menengah Atas di Indonesia setuju dengan penerapan syariat agama (Islam) dalam hukum negara, yang dapat mengarah pada pengabaian hak-hak kelompok minoritas.
Dinamika Intoleransi dan Polarisasi di Era Digital
Dalam konteks ini, tidaklah berlebihan jika kita menyebutkan bahwa meningkatnya politisasi agama di Indonesia berhubungan erat dengan perilaku intoleransi di kalangan para pemuda. Banyak pelajar dan mahasiswa yang terpapar pengaruh doktrin “eksklusif” yang mendorong sikap tidak toleran terhadap kelompok lain yang memiliki kepercayaan yang berbeda. Dengan kata lain, perilaku ini rentan dalam “menyuburkan” benih intoleransi dan radikalisme. Dalam situasi ini, pendekatan beragama yang moderat dan tidak berlebihan dapat menjadi solusi untuk meredakan ketegangan dengan menekankan pentingnya sikap toleran dan penghargaan terhadap keberagaman.
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri telah melakukan berbagai langkah untuk menjaga harmoni dan kerukunan antarumat beragama. Salah satu peran pemerintah adalah sebagai fasilitator, memberdayakan dan mendukung Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah untuk dialog antara berbagai agama dalam rangka mencegah dan menyelesaikan potensi konflik. Selain itu, pemerintah juga melaksanakan program pemantapan cinta tanah air dan nasionalisme yang melibatkan pelajar, mahasiswa, organisasi masyarakat, serta tokoh agama. Program ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan kebersamaan di kalangan generasi muda. Meskipun demikian, penulis mengamati bahwa implementasi regulasi yang terkait dengan toleransi masih belum sepenuhnya menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan yang jujur dan penuh. Oleh karena itu, peran masyarakat sipil dan organisasi keagamaan sangat diperlukan guna memastikan bahwa kebijakan yang ada berfokus pada perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.
Di tengah meningkatnya polarisasi dan intoleransi, pendidikan tetap menjadi instrumen kunci untuk menjaga kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pendidikan tentang toleransi beragama tidak hanya perlu diterapkan di lingkungan sekolah, tetapi juga dalam konteks sosial yang lebih luas, termasuk keluarga dan komunitas. Penelitian dari SETARA Institute menunjukkan bahwa siswa yang mendapatkan pendidikan tentang keberagaman cenderung lebih toleran terhadap perbedaan agama dan keyakinan.
Selain melalui pendidikan, media sosial juga memiliki peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat mengenai isu-isu keberagaman. Kampanye digital yang menekankan toleransi dan keberagaman dapat menjadi strategi efektif untuk melawan narasi intoleran yang berkembang di dunia maya. Penulis menyadari bahwa memelihara kebebasan beragama dan berkeyakinan di tengah tantangan polarisasi bukanlah perkara mudah, tetapi juga bukan hal yang mustahil. Dibutuhkan komitmen dari berbagai elemen, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, tokoh agama, dan dunia pendidikan, untuk terus mengedepankan dialog partisipatif, dan penghormatan terhadap perbedaan.
Di akhir tulisan ini, penulis teringat akan kekayaan budaya Jawa yang dapat memperkuat hubungan antar warga negara, terutama antarumat beragama. Konsep “memayu hayuning bawana,” yang berarti memperindah dunia dengan menjaga keseimbangan dan harmoni, layak kita jadikan sebagai acuan dalam merawat kebebasan beragama sebagaimana adanya, bukan sebagaimana semestinya. Selain itu, ada juga konsep “manunggaling kawula Gusti,” yang menekankan pada hubungan personal antara seseorang dan Tuhan tanpa perlu mendiskreditkan kepercayaan orang lain. Prinsip ini mengajarkan bahwa spiritualitas seharusnya bukanlah alat pemecah belah, melainkan sarana untuk saling memahami dan menghormati tanpa syarat. ***
Wahyu Tanoto
You may like
Opini
Merevolusi Cara Kita Melihat Tugas Kuliah
Published
3 weeks agoon
29 December 2025By
Mitra Wacana

Nurisa Cahya Artika Farah,Mahasiswi semester 3 Program Studi Tadris (Pendidikan) Bahasa Indonesia, Fakultas Adab dan Bahasa, Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta.
Di dunia perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menjadi individu yang mandiri, kritis, dan kreatif dalam menghadapi berbagai tantangan akademik. Salah satu tantangan tersebut adalah tugas kuliah yang diberikan oleh dosen sebagai proses pembelajaran. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak mahasiswa justru menganggap tugas kuliah sebagai beban yang membebani pikiran. Mahasiswa lebih fokus pada nilai akhir ketimbang proses belajar yang seharusnya memperkaya pengetahuan dan keterampilan. Fenomena ini menjadi gambaran bahwa sebagian mahasiswa masih memandang tugas secara sempit, tanpa menyadari bahwa melalui tugas inilah kemampuan berpikir kritis serta tanggung jawab perkuliahan dapat terasah.
Banyak kalangan mahasiswa mengeluh akan tugas kuliah yang diberikan, mereka memandangnya sebagai beban yang menumpuk dan hanya sebatas untuk mendapatkan nilai, bukan proses pembelajaran. Hal ini membuat motivasi belajar menurun yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, seperti kurangnya minat, kesulitan konsentrasi, masalah pribadi, maupun kualitas hasil tugas yang tidak mencerminkan pemahaman sebenarnya. Padahal, esensi pendidikan tinggi bukan sebatas mengerjakan tugas, namun membangun cara berpikir kritis dan kreatif mahasiswa. Karena itu, saatnya mahasiswa merevolusi cara pandang terhadap tugas yang dianggap beban menjadi proses pembelajaran yang bermakna.
Perkuliahan mahasiswa sebenarnya tidak hanya belajar dari penjelasan dosen, tetapi juga dari proses mengerjakan tugas. Hal ini sejalan dengan Teori Konstruktivisme yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun dari individu berdasarkan pengalaman dan pemahaman. Seperti halnya dalam pemberian tugas kuliah ini mahasiswa tidak hanya menerima ilmu dari dosen, tetapi juga membentuk pemahaman sendiri melalui pengalaman belajar sebelumnya. Dalam konteks ini, tugas kuliah bukanlah tujuan akhir, tetapi sebagai sarana untuk membangun pemahaman terhadap suatu konsep. Misalnya, ketika mahasiswa diminta menulis esai, mereka tidak hanya terpaku dengan teori yang sudah ada, tetapi juga menyusun gagasan atau ide pribadi berdasarkan pemahaman konseptual dan berpikir kritis. Dengan demikian, tugas menjadi penghubung antara pengetahuan dan penerapan.
Namun, faktanya di lapangan masih banyak mahasiswa yang memandang tugas sebagai sesuatu yang dipaksakan untuk semata-mata demi nilai. Hal ini sejalan dengan rendahnya motivasi dalam diri berdasarkan teori Self-Determination. Mahasiswa akan termotivasi jika memiliki kebebasan pilihan dalam menyelesaikan tugas (autonomi), merasa mampu mengerjakan (kompetensi), dan merasa bahwa tugas memiliki hubungan dengan kehidupan mereka (keterhubungan). Dengan demikian, ketika diberi tugas yang memberikan kebebasan, kemampuan, serta keterhubungan, mahasiswa akan melihat tugas bukan sebagai beban, melainkan sebagai bentuk pengembangan diri.
Selain itu, konsep belajar bermakna dari David Ausubel juga relevan dalam konteks ini. Dalam perkuliahan, hal ini berarti tugas yang diberikan seharusnya berasal dari struktur pemikiran yang telah dimiliki mahasiswa. Misalnya, tugas proyek yang menuntut mahasiswa mengaitkan teori dengan pengalaman pribadi. Ketika mahasiswa menemukan keterkaitan tersebut, proses belajar menjadi bermakna. Mereka tidak sedang mengerjakan tugas dosen melainkan sedang menemukan diri dalam proses pembelajaran.
Pandangan teori humanistik juga memperkuat gagasan ini. Dalam pandangan ini, mahasiswa dipandang sebagai individu yang unik dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Tugas kuliah, seharusnya menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengekspresikan diri, mengeksplorasi nilai-nilai pribadi, dan mengembangkan potensi secara utuh. Tugas tidak hanya mengukur hasil akhir berupa angka, tetapi juga menilai proses berpikir, kreativitas, den refleksi diri mahasiswa.
Sebagai mahasiswa, saya kerap melihat beberapa mahasiswa bahwa tugas baru benar-benar dipahami maknanya setelah dikerjakan, bukan saat materi disampaikan oleh dosen. Dari tugaslah mahasiswa belajar berpikir kritis, mampu mengelola waktu, dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa tugas kuliah sejatinya memiliki peran penting dalam membentuk kualitas mahasiswa, asalkan dipahami dan dijalani dengan cara pandang yang tepat.
Masalahnya sistem pendidikan kita masih berorientasi pada hasil bukan proses. Banyak mahasiswa mengerjakan tugas hanya untuk mendapatkan nilai bukan karena ingin memahami makna apa yang mereka pelajari. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan paradigma, baik dari pihak dosen maupun mahasiswa. Merevolusi cara pandang terhadap tugas kuliah berarti menempatkan kembali tugas sebagai bagian dari proses pembelajaran bukan sebagai beban mahasiswa. Ketika mahasiswa mulai melihat tugas sebagai ruang pengembangan diri mereka akan lebih bersemangat, produktif, dan berdaya saing. Tak hanya mahasiswa, dosen pun akan lebih mudah menilai kualitas pemahaman mahasiswa. Dengan demikian, revolusi ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hasil belajar, tetapi juga membentuk generasi mahasiswa yang berpikir kritis, reflektif, dan siap menghadapi tantangan di kehidupan nyata. Hal yang paling berharga dari tugas kuliah bukan hanya tentang nilai yang berupa angka melainkan proses belajar yang akan menambah pemahaman.