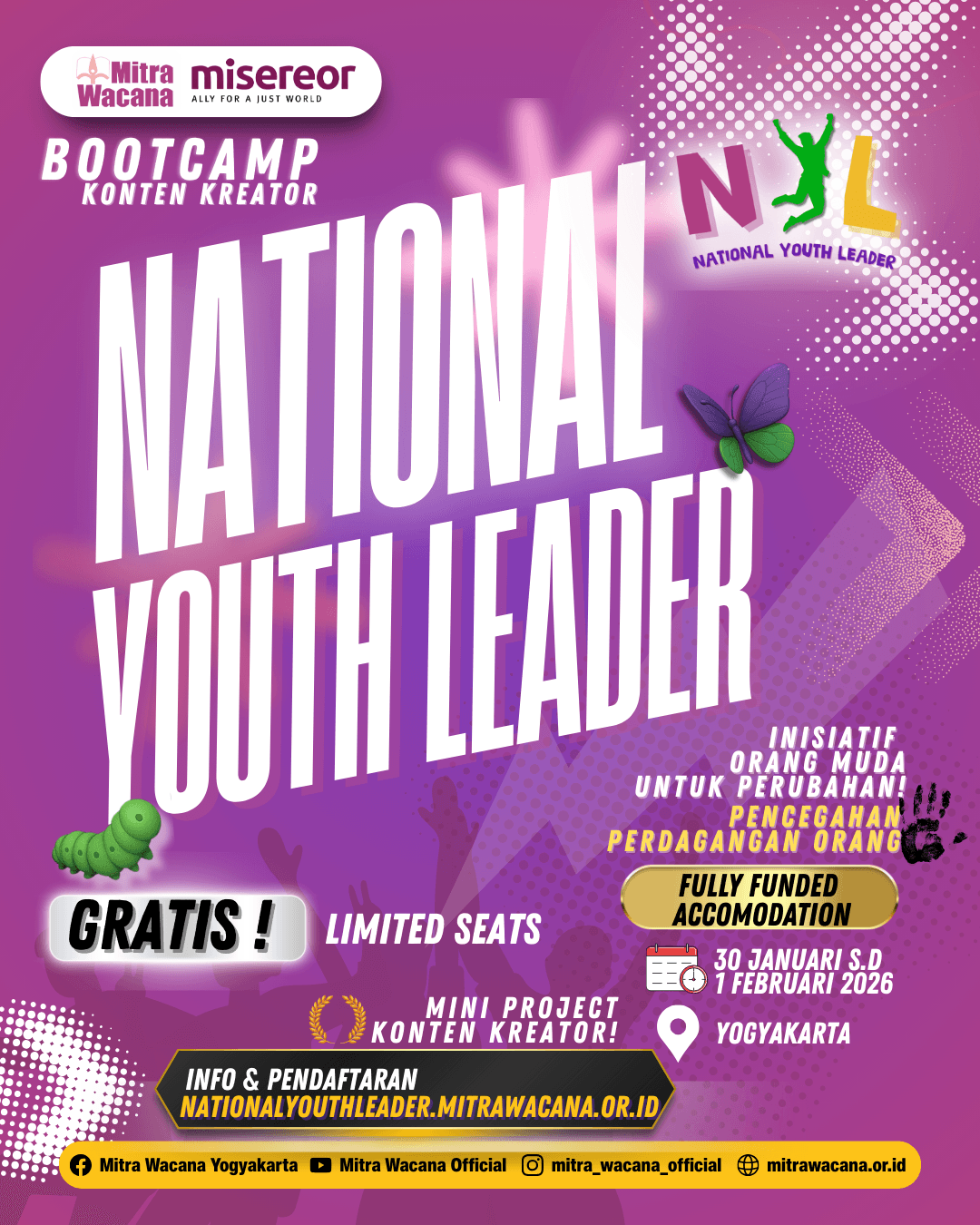Opini
Toleransi di Belanda: Antara Progresivitas dan Ambiguitas Moral
Published
1 year agoon
By
Mitra Wacana
Penulis : Sabrina Yasmine Azzahra
Dilihat secara geografis, Belanda merupakan salah satu negara terkecil di Eropa Barat yang besarnya hanya sekitar satu perdelapan Pulau Kalimantan di Indonesia. Meskipun begitu, negara kecil padat penduduk tersebut berpengaruh signifikan terhadap perkembangan isu-isu sosial seperti soft-drugs, aborsi, prostitusi, serta perkawinan sejenis. Mengapa hal itu bisa terjadi? Roney (2009) mengungkapkan bahwa Belanda memiliki sejarah yang panjang terkait keragaman etnis, agama, dan daerah. Misalnya, kebijakan verzuiling atau pilarisasi yang mengatur agar kelompok-kelompok dengan latar belakang berbeda dapat hidup berdampingan tanpa adanya bentrok konflik. Keragaman tersebut membuat fondasi masyarakat Belanda didasarkan pada prinsip toleransi. Pada dasarnya, prinsip ini bukan lagi menjadi hal khusus, tetapi toleransi di Belanda sering dipandang sebagai salah satu nilai utama yang membentuk identitas nasional negara tanah rendah ini. Buruma (2007) menerangkan bahwa toleransi di Belanda bukan hanya terkait permasalahan moral, tetapi juga mengenai kemampuan masyarakat untuk hidup berdampingan dengan masyarakat yang memiliki beragam latar belakang. Masyarakat Belanda digambarkan memiliki kecenderungan untuk melihat konflik secara rasional dengan mengutamakan pendekatan pragmatis untuk menjaga keharmonian sosial dari prasangka-prasangka maupun emosi yang akan memengaruhi interaksi sehari-hari. Praktik toleransi ini melahirkan legalisasi isu-isu di area kontroversial seperti nederwiet, aborsi, prostitusi, dan perkawinan sejenis serta regulasi yang mengatur batasan ‘’legal’’ praktik tersebut.
Meskipun begitu, dalam pandangan sebagian orang toleransi dalam masyarakat Belanda dianggap sebagai ambiguitas moral. Ketegangan mulai muncul ketika batas-batas toleransi tersebut dilangkahi yang mengakibatkan meningkatnya kekhawatiran publik hingga menyangkut pautkan penegakkan hukum. Kasus-kasus seperti ekstremisme, kekerasan seksual, penyalahgunaan obat-obatan, serta diskriminasi kelompok marjinal membuat batasan tersebut kian terkikis. Belanda mungkin memang menerapkan gedogen sebagai asas kemasyarakatan mereka, tetapi dengan berkembangnya popularitas politisi kontroversial seperti Pim Fortuyn dan Geert Wilders, tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi pendekatan yang berbeda terhadap toleransi ini. Tokoh-tokoh politik populis seperti PVV yang dipimpin oleh WIlders telah mendorong batas toleransi dengan menekankan perlunya mempertahankan budaya Belanda “asli”. Hal ini menciptakan pecahnya dinamika toleransi terhadap keberagaman yang didukung lebih lanjut dengan radikalisme serta protes yang berkelanjutan. Theo van Gogh menjadi salah satu contoh melangkahi batas toleransi dengan film-nya Submission yang mengantarkan van Gogh ke pintu maut. Film yang ditujukan sebagai kritik terhadap budaya Islam dalam memperlakukan perempuan tidak diterima dengan baik oleh masyarakat muslim di Belanda. Van Gogh dan Hirsi Ali yang merupakan penulis skrip film tersebut sekaligus anggota dari parlemen Belanda pada saat itu mendapat kecaman tajam atas representasi muslim di film Submission dengan tuduhan penistaan agama di mana ayat kitab suci al-Quran tertulis di badan mayat-mayat perempuan. Kasus tersebut sering dibahas sebagai peristiwa yang menunjukkan bahwa toleransi masyarakat Belanda dalam posisi terancam. Selain itu, hal tersebut juga menunjukkan perubahan kepekaan masyarakat post-modern dalam menghadapi batas-batas multikulturalisme.
Namun jika dilihat dari penelitian Barendregt (2011), hingga saat ini praktik gedogen masih menjadi hal yang diturunkan dari generasi ke generasi di Belanda dan dilakukan dimanapun dan kapanpun oleh masyarakat Belanda, walaupun beberapa beralasan dengan syarat tidak merugikan orang lain. Belanda secara keseluruhan merupakan negara progresif yang mengedepankan inklusivitas masyarakat dan kebebasan individual. Dengan catatan bahwa toleransi bukan berarti kebebasan tanpa batas, melainkan ada batasan di mana hak-hak tersebut diatur sedemikian rupa agar mencapai kesejahteraan bersama.
REFERENSI
Barendregt, W. (2011). Gedogen: the psychological aspects of Dutch tolerance. Twente University. https://essay.utwente.nl/61190/1/Barendregt%2C_W._-_s0184667_%28verslag%29.pdf
Buruma, Y. (2007). Dutch Tolerance: On Drugs, Prostitution, and Euthanasia. Crime and Justice in the Netherlands, 35(1), 73-113. https://www.jstor.org/stable/10.1086/650185
Roney, J. B. (2009). Culture and Customs of the Netherlands. Bloomsbury Academic.
Opini
Merevolusi Cara Kita Melihat Tugas Kuliah
Published
3 weeks agoon
29 December 2025By
Mitra Wacana

Nurisa Cahya Artika Farah,Mahasiswi semester 3 Program Studi Tadris (Pendidikan) Bahasa Indonesia, Fakultas Adab dan Bahasa, Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta.
Di dunia perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menjadi individu yang mandiri, kritis, dan kreatif dalam menghadapi berbagai tantangan akademik. Salah satu tantangan tersebut adalah tugas kuliah yang diberikan oleh dosen sebagai proses pembelajaran. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak mahasiswa justru menganggap tugas kuliah sebagai beban yang membebani pikiran. Mahasiswa lebih fokus pada nilai akhir ketimbang proses belajar yang seharusnya memperkaya pengetahuan dan keterampilan. Fenomena ini menjadi gambaran bahwa sebagian mahasiswa masih memandang tugas secara sempit, tanpa menyadari bahwa melalui tugas inilah kemampuan berpikir kritis serta tanggung jawab perkuliahan dapat terasah.
Banyak kalangan mahasiswa mengeluh akan tugas kuliah yang diberikan, mereka memandangnya sebagai beban yang menumpuk dan hanya sebatas untuk mendapatkan nilai, bukan proses pembelajaran. Hal ini membuat motivasi belajar menurun yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, seperti kurangnya minat, kesulitan konsentrasi, masalah pribadi, maupun kualitas hasil tugas yang tidak mencerminkan pemahaman sebenarnya. Padahal, esensi pendidikan tinggi bukan sebatas mengerjakan tugas, namun membangun cara berpikir kritis dan kreatif mahasiswa. Karena itu, saatnya mahasiswa merevolusi cara pandang terhadap tugas yang dianggap beban menjadi proses pembelajaran yang bermakna.
Perkuliahan mahasiswa sebenarnya tidak hanya belajar dari penjelasan dosen, tetapi juga dari proses mengerjakan tugas. Hal ini sejalan dengan Teori Konstruktivisme yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun dari individu berdasarkan pengalaman dan pemahaman. Seperti halnya dalam pemberian tugas kuliah ini mahasiswa tidak hanya menerima ilmu dari dosen, tetapi juga membentuk pemahaman sendiri melalui pengalaman belajar sebelumnya. Dalam konteks ini, tugas kuliah bukanlah tujuan akhir, tetapi sebagai sarana untuk membangun pemahaman terhadap suatu konsep. Misalnya, ketika mahasiswa diminta menulis esai, mereka tidak hanya terpaku dengan teori yang sudah ada, tetapi juga menyusun gagasan atau ide pribadi berdasarkan pemahaman konseptual dan berpikir kritis. Dengan demikian, tugas menjadi penghubung antara pengetahuan dan penerapan.
Namun, faktanya di lapangan masih banyak mahasiswa yang memandang tugas sebagai sesuatu yang dipaksakan untuk semata-mata demi nilai. Hal ini sejalan dengan rendahnya motivasi dalam diri berdasarkan teori Self-Determination. Mahasiswa akan termotivasi jika memiliki kebebasan pilihan dalam menyelesaikan tugas (autonomi), merasa mampu mengerjakan (kompetensi), dan merasa bahwa tugas memiliki hubungan dengan kehidupan mereka (keterhubungan). Dengan demikian, ketika diberi tugas yang memberikan kebebasan, kemampuan, serta keterhubungan, mahasiswa akan melihat tugas bukan sebagai beban, melainkan sebagai bentuk pengembangan diri.
Selain itu, konsep belajar bermakna dari David Ausubel juga relevan dalam konteks ini. Dalam perkuliahan, hal ini berarti tugas yang diberikan seharusnya berasal dari struktur pemikiran yang telah dimiliki mahasiswa. Misalnya, tugas proyek yang menuntut mahasiswa mengaitkan teori dengan pengalaman pribadi. Ketika mahasiswa menemukan keterkaitan tersebut, proses belajar menjadi bermakna. Mereka tidak sedang mengerjakan tugas dosen melainkan sedang menemukan diri dalam proses pembelajaran.
Pandangan teori humanistik juga memperkuat gagasan ini. Dalam pandangan ini, mahasiswa dipandang sebagai individu yang unik dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Tugas kuliah, seharusnya menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengekspresikan diri, mengeksplorasi nilai-nilai pribadi, dan mengembangkan potensi secara utuh. Tugas tidak hanya mengukur hasil akhir berupa angka, tetapi juga menilai proses berpikir, kreativitas, den refleksi diri mahasiswa.
Sebagai mahasiswa, saya kerap melihat beberapa mahasiswa bahwa tugas baru benar-benar dipahami maknanya setelah dikerjakan, bukan saat materi disampaikan oleh dosen. Dari tugaslah mahasiswa belajar berpikir kritis, mampu mengelola waktu, dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa tugas kuliah sejatinya memiliki peran penting dalam membentuk kualitas mahasiswa, asalkan dipahami dan dijalani dengan cara pandang yang tepat.
Masalahnya sistem pendidikan kita masih berorientasi pada hasil bukan proses. Banyak mahasiswa mengerjakan tugas hanya untuk mendapatkan nilai bukan karena ingin memahami makna apa yang mereka pelajari. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan paradigma, baik dari pihak dosen maupun mahasiswa. Merevolusi cara pandang terhadap tugas kuliah berarti menempatkan kembali tugas sebagai bagian dari proses pembelajaran bukan sebagai beban mahasiswa. Ketika mahasiswa mulai melihat tugas sebagai ruang pengembangan diri mereka akan lebih bersemangat, produktif, dan berdaya saing. Tak hanya mahasiswa, dosen pun akan lebih mudah menilai kualitas pemahaman mahasiswa. Dengan demikian, revolusi ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hasil belajar, tetapi juga membentuk generasi mahasiswa yang berpikir kritis, reflektif, dan siap menghadapi tantangan di kehidupan nyata. Hal yang paling berharga dari tugas kuliah bukan hanya tentang nilai yang berupa angka melainkan proses belajar yang akan menambah pemahaman.