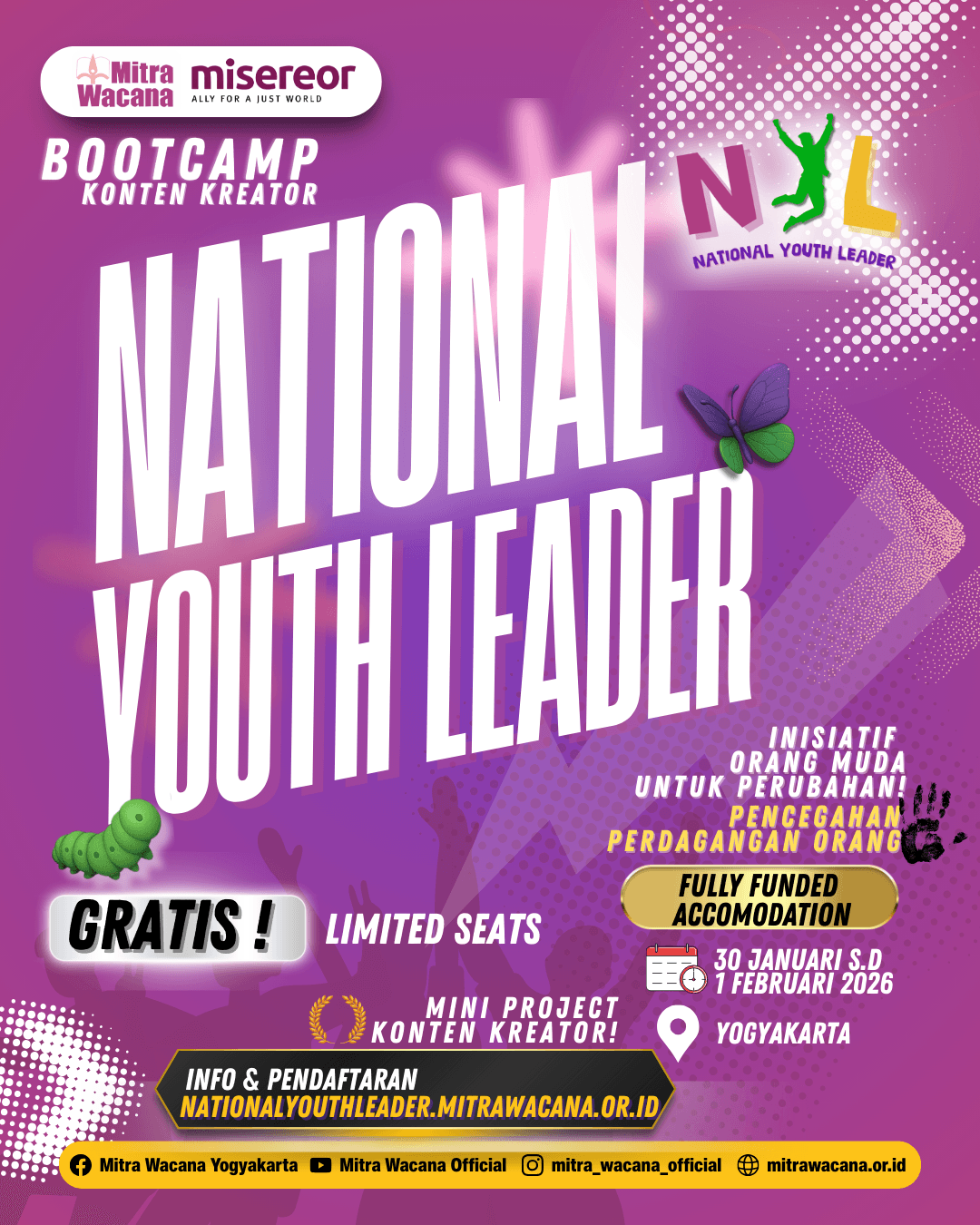Publikasi
SALUANG DENDANG DALAM PERSPEKTIF KATO NAN AMPEK BUDAYA MINANGKABAU
Published
1 year agoon
By
Mitra Wacana

Penulis : Maryatul Kuptiah (Universitas Andalas, Sumatera Barat)
PENDAHULUAN
(Edriyetri Amir, 2013) secara harfiah, sastra lisan berarti sastra yang disampaikan secara lisan. Sastra lisan dibawakan/ ditampilkan oleh seniman sastra lisan. Sastra lisan sebagai ungkapan ungkapan gabungan sastra dan lisan, karenanya dapat diberikan batasan sastra yang disampaikan dan dinikmati secara lisan. Sastra lisan adalah seni bahasa yang diwujudkan dalam pertunjukan oleh seniman dan dinikmati secara lisan oleh khalayak, menggunakan bahasa ragam puitika dan estetika masyarakat bahasanya. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa, sastra lisan adalah:
1. Ia ada atau wujud dalam pertunjukan, dalam banyak kasus, diiringi dengan instrument bunyi-bunyian, bahkan tarian.
2. Unsur hiburan dan pendidikan dominan di dalamnya.
3. Menggunakan bahasa setempat, bahasa setempat, bahasa daerah,paling tidak dialek daerah.
4. Menggunakan puitika masyarakat bahasa itu.
Minangkabau sebagai salah satu derah dengan keberagaman budaya, adat istiadat, dan tradisi yang tumbuh dan berkembang sebagai sistem yang telah dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat. Berakar dari sistem kekerabatan matrilinial Minangkabau. Tradisi tersebut merupakan wujud yang mencerminkan identitas, dinamika dan perkembangan yang terjadu dakam masyarakat Minangkabau, sesuai dengan falsafah adatnya Alam Takambang Jadi Guru. Minangkabau memiliki salah satu sastra lisan yang masih hidup dan keberadaannya yaitu saluang dendang yang bergerak sesuai dengan perkembangan zaman. Dinamika perkembangan tradisi budaya Minangkabau sendiri dari akhir tahun 60-an begitu cepat dan bergemuruh.
METODE PENELITIAN
Penelitian yang dilakukan dalam sastra lisan saluang dendang ini adalah menggunakan metode penelitian kuantitatif., dengan pendekatan observasi-partisipasi dengan cara menghadirkan penampil saluang dendang. Karena penelitian sastra lisan saluang dendang ini bersifat kuantitatif, maka melaksanakan pendekatannya dengan menekankan hubungan-hubungan yang bermakna sesuai dengan keadaan tempat penelitian, dengan cara menghubungkan bagian-bagian dari suatu substansi ke dalam keseluruhan. Berkaitan dengan hal itu, teknik pengumpulan data yang dapat digunakan salah satunya, yaitu observasi-partisipasi, wawacara mengenai penyusunan teks, perkembangan, bagaimana bentuk penyajian sastra lisan saluang dendang kepada penampil. Teknik pengumpulan data bersifat obervasi-partisipasi ini adalah dengan mengamati secara langsung pertunjukan saluang dendang yang di hadirkan di kampus. Pengamatan lapangan pada saat pertunjukan ini difokuskan untuk memuat informasi mengenai pertunjukan saluang dendang, dan hubungan komunikasi antara penonton dan penampil saat berlangsungnya pertunjukan saluang dendang.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Istilah saluang dendang muncul dari tradisi budaya masyarakat Minangkabau, yakni tradisi budaya lisan yang merupakan salah satu ciri khas budaya Minangkabau. Saluang berasal dari kata ‘saruang’ yang berarti satu ruang. Filosofi lobang saluang dibuat dengan empat lobang tetapi dapat memainkan lima nada, di antaranya yaitu do, re, mi, fa, dan sol yang berasal dari masyarakat Minangkabau sendiri. Menurut penulusuran dahulunya, di Minangkabau dikenal dengan nama kato nan ampek, cara tertutur kata antar sesama dalam istilah Minangkabau yang disimbolkan dengan tangga empat. Kato nan ampek ini mengatur bagaimana setiap orang Minangkabau bisa memposisikan diri sesuai dengan lawan bicaranya ketika berkomunikasi dengan empat cara, yaitu sebagai berikut:
1. Kato Mandaki
Secara harfiah, kato mandaki diartikan sebagai kata mendaki. Cara ini digunakan untuk bertutur kata kepada orang yang lebih tua/ dituakan.
2. Kato Manurun
Cara ini digunakan untuk bertutur kata kepada orang yang lebih muda.
3. Kato Mandata
Kato Mandata adalah arti dari kata mendatar/ setara. Artinya kato mandata ketika bertutur kepada teman sebaya yang sepantaran/ seumuran.
4. Kato Melereang
Kato melereang adalah cara berkomunikasi khusus digunakan terhadap sosok yang cukup dihormati, dan biasanya ditujukan kepada seseorang yang tidak memiliki hubungan darah secara langsung.
Fungsi saluang adalah untuk mengiringi dendang-dendang yang dilantunkan. Awalnya dendang disesuaikan dengan situasi, misalnya ketika seseorang ingin kesawah teks dendangnya yang di lafalkan tentang bagaimana sawah/ ladangnya, atau jika seorang perantau menceritakan bagaimana perjuangan hidupnya di tanah rantau. Namun, seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman semakin pesat, dendang dalam pertunjukan saluang dendang mulai beradaptasi dan menyesuaikan diri, misalnya tentang jatuh cinta, patah hati,mati karena cinta dan lain-lain. Tentunya dengan tetap mempertahankan eksistensi/ warna tradisi kebudayaan Minangkabau. Mengapa hal tersebut di lakukan oleh penampil saluang dendang? Supaya pertunjukan saluang dendang tidak tergilas masa dan tertinggal zaman, teknologi, musik, tetapi tetap meninggalkan jejak terutama bagi kalangan pemudi-pemuda. Pertunjukan saluang dendang, lagu-lagu yang dilantunkan, hanya lagu pertama dan terakhir yang ditentukan, lengkap dengan lagu Singggalang. Setelah lagu ini dinayanyikan, biasanya khalyak bisa mengajukan permintaan untuk lagu-lagu yang disukai. Tetapi jika belum ada permintaan, biasanya penmapil memilih sendiri lagu yang akan di nyanyikannya. Dari penelitian yang telah dilakukan, pertunjukan saluang dendang beranggotakan tiga orang, satu orang peniup saluang, satu orang pendendang, dan satu orang pemain kerenceng. Penampil bermain dengan posisi duduk setengah lingkaran. Waktu pertunjukan saluang dendang ini adalah ba’da isya, sampai menjelang subuh.
Perkembangan Pertunjukan Saluang Dendang
Dari pengamatan dilapangan, pertunjukan saluang dendang saat ini sudah menggunakan tiga bahasa, yaitu bahasa Minangkabau, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris melihat khalayak dari berbagai kalangan dan penampil bisa didatangkan di berbagai daerah di Indonesia untuk berbagai festival. Pertunjukan saluang dendang juga akan berkolaborasi dengan orkestra modern. Hal tersebut, dikarenakan agar tradisi saluang dendang tetap eksis di zaman sekarang, tetapi tidak menyingkirkan ciri khas dari budaya Minangkabau. Dari hasil pengamatan, didapatkan perbedaan antara pertunjukan sastra lisan rabab biola dan saluang dendang. Selain dari perbedaan alat musik yaitu biola dan saluang. Nada dari biola bisa di transformasikan ke nada saluang, karena nada-nada dibiola bisa mencapai 2 oktaf, sementara nada-nada di saluang hanya sampai nada sol. Artinya, dapat disimpulkan bahwa semua lagu saluang dendang bisa dinyanyikan di biola. Tapi tidak semua lagi rabab pasisia bisa dinyanyikan di saluang dendang. Pertunjukan sastra lisan saluang dendang ini berfungsi sebagai penghibur bagi masyarakat.
SIMPULAN
Pertunjukan saluang dendang sebagai bagian yang integral dari kehidupan kebudayaan Minangkabau, yang secara tidak langsung menunjukkan hubungannya dengan masyarakat Minangkabau.
DAFTAR PUSTAKA
Amir, Edriyetti. 2013.SASTRA LISAN INDONESIA.Yogyakarta: Andi
Sukmawati, Noni. 2008. “Bagurau Saluang dan Dendang Dalam Perspektif Perubahan Budaya Minangkabau”, Vol.35 No.2
Biodata Singkat :
Maryatul Kuptiah, mahasiswa aktif jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas. Hobi menulis puisi dan artikel. Saat ini sedang bergiat di Labor Kepenulisan Kreatif FIB Unand. Telah menerbitkan sebuah novel yang berjudul “serapuh ranting patah”.
Opini
Merevolusi Cara Kita Melihat Tugas Kuliah
Published
3 weeks agoon
29 December 2025By
Mitra Wacana

Nurisa Cahya Artika Farah,Mahasiswi semester 3 Program Studi Tadris (Pendidikan) Bahasa Indonesia, Fakultas Adab dan Bahasa, Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta.
Di dunia perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menjadi individu yang mandiri, kritis, dan kreatif dalam menghadapi berbagai tantangan akademik. Salah satu tantangan tersebut adalah tugas kuliah yang diberikan oleh dosen sebagai proses pembelajaran. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak mahasiswa justru menganggap tugas kuliah sebagai beban yang membebani pikiran. Mahasiswa lebih fokus pada nilai akhir ketimbang proses belajar yang seharusnya memperkaya pengetahuan dan keterampilan. Fenomena ini menjadi gambaran bahwa sebagian mahasiswa masih memandang tugas secara sempit, tanpa menyadari bahwa melalui tugas inilah kemampuan berpikir kritis serta tanggung jawab perkuliahan dapat terasah.
Banyak kalangan mahasiswa mengeluh akan tugas kuliah yang diberikan, mereka memandangnya sebagai beban yang menumpuk dan hanya sebatas untuk mendapatkan nilai, bukan proses pembelajaran. Hal ini membuat motivasi belajar menurun yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, seperti kurangnya minat, kesulitan konsentrasi, masalah pribadi, maupun kualitas hasil tugas yang tidak mencerminkan pemahaman sebenarnya. Padahal, esensi pendidikan tinggi bukan sebatas mengerjakan tugas, namun membangun cara berpikir kritis dan kreatif mahasiswa. Karena itu, saatnya mahasiswa merevolusi cara pandang terhadap tugas yang dianggap beban menjadi proses pembelajaran yang bermakna.
Perkuliahan mahasiswa sebenarnya tidak hanya belajar dari penjelasan dosen, tetapi juga dari proses mengerjakan tugas. Hal ini sejalan dengan Teori Konstruktivisme yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun dari individu berdasarkan pengalaman dan pemahaman. Seperti halnya dalam pemberian tugas kuliah ini mahasiswa tidak hanya menerima ilmu dari dosen, tetapi juga membentuk pemahaman sendiri melalui pengalaman belajar sebelumnya. Dalam konteks ini, tugas kuliah bukanlah tujuan akhir, tetapi sebagai sarana untuk membangun pemahaman terhadap suatu konsep. Misalnya, ketika mahasiswa diminta menulis esai, mereka tidak hanya terpaku dengan teori yang sudah ada, tetapi juga menyusun gagasan atau ide pribadi berdasarkan pemahaman konseptual dan berpikir kritis. Dengan demikian, tugas menjadi penghubung antara pengetahuan dan penerapan.
Namun, faktanya di lapangan masih banyak mahasiswa yang memandang tugas sebagai sesuatu yang dipaksakan untuk semata-mata demi nilai. Hal ini sejalan dengan rendahnya motivasi dalam diri berdasarkan teori Self-Determination. Mahasiswa akan termotivasi jika memiliki kebebasan pilihan dalam menyelesaikan tugas (autonomi), merasa mampu mengerjakan (kompetensi), dan merasa bahwa tugas memiliki hubungan dengan kehidupan mereka (keterhubungan). Dengan demikian, ketika diberi tugas yang memberikan kebebasan, kemampuan, serta keterhubungan, mahasiswa akan melihat tugas bukan sebagai beban, melainkan sebagai bentuk pengembangan diri.
Selain itu, konsep belajar bermakna dari David Ausubel juga relevan dalam konteks ini. Dalam perkuliahan, hal ini berarti tugas yang diberikan seharusnya berasal dari struktur pemikiran yang telah dimiliki mahasiswa. Misalnya, tugas proyek yang menuntut mahasiswa mengaitkan teori dengan pengalaman pribadi. Ketika mahasiswa menemukan keterkaitan tersebut, proses belajar menjadi bermakna. Mereka tidak sedang mengerjakan tugas dosen melainkan sedang menemukan diri dalam proses pembelajaran.
Pandangan teori humanistik juga memperkuat gagasan ini. Dalam pandangan ini, mahasiswa dipandang sebagai individu yang unik dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Tugas kuliah, seharusnya menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengekspresikan diri, mengeksplorasi nilai-nilai pribadi, dan mengembangkan potensi secara utuh. Tugas tidak hanya mengukur hasil akhir berupa angka, tetapi juga menilai proses berpikir, kreativitas, den refleksi diri mahasiswa.
Sebagai mahasiswa, saya kerap melihat beberapa mahasiswa bahwa tugas baru benar-benar dipahami maknanya setelah dikerjakan, bukan saat materi disampaikan oleh dosen. Dari tugaslah mahasiswa belajar berpikir kritis, mampu mengelola waktu, dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa tugas kuliah sejatinya memiliki peran penting dalam membentuk kualitas mahasiswa, asalkan dipahami dan dijalani dengan cara pandang yang tepat.
Masalahnya sistem pendidikan kita masih berorientasi pada hasil bukan proses. Banyak mahasiswa mengerjakan tugas hanya untuk mendapatkan nilai bukan karena ingin memahami makna apa yang mereka pelajari. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan paradigma, baik dari pihak dosen maupun mahasiswa. Merevolusi cara pandang terhadap tugas kuliah berarti menempatkan kembali tugas sebagai bagian dari proses pembelajaran bukan sebagai beban mahasiswa. Ketika mahasiswa mulai melihat tugas sebagai ruang pengembangan diri mereka akan lebih bersemangat, produktif, dan berdaya saing. Tak hanya mahasiswa, dosen pun akan lebih mudah menilai kualitas pemahaman mahasiswa. Dengan demikian, revolusi ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hasil belajar, tetapi juga membentuk generasi mahasiswa yang berpikir kritis, reflektif, dan siap menghadapi tantangan di kehidupan nyata. Hal yang paling berharga dari tugas kuliah bukan hanya tentang nilai yang berupa angka melainkan proses belajar yang akan menambah pemahaman.