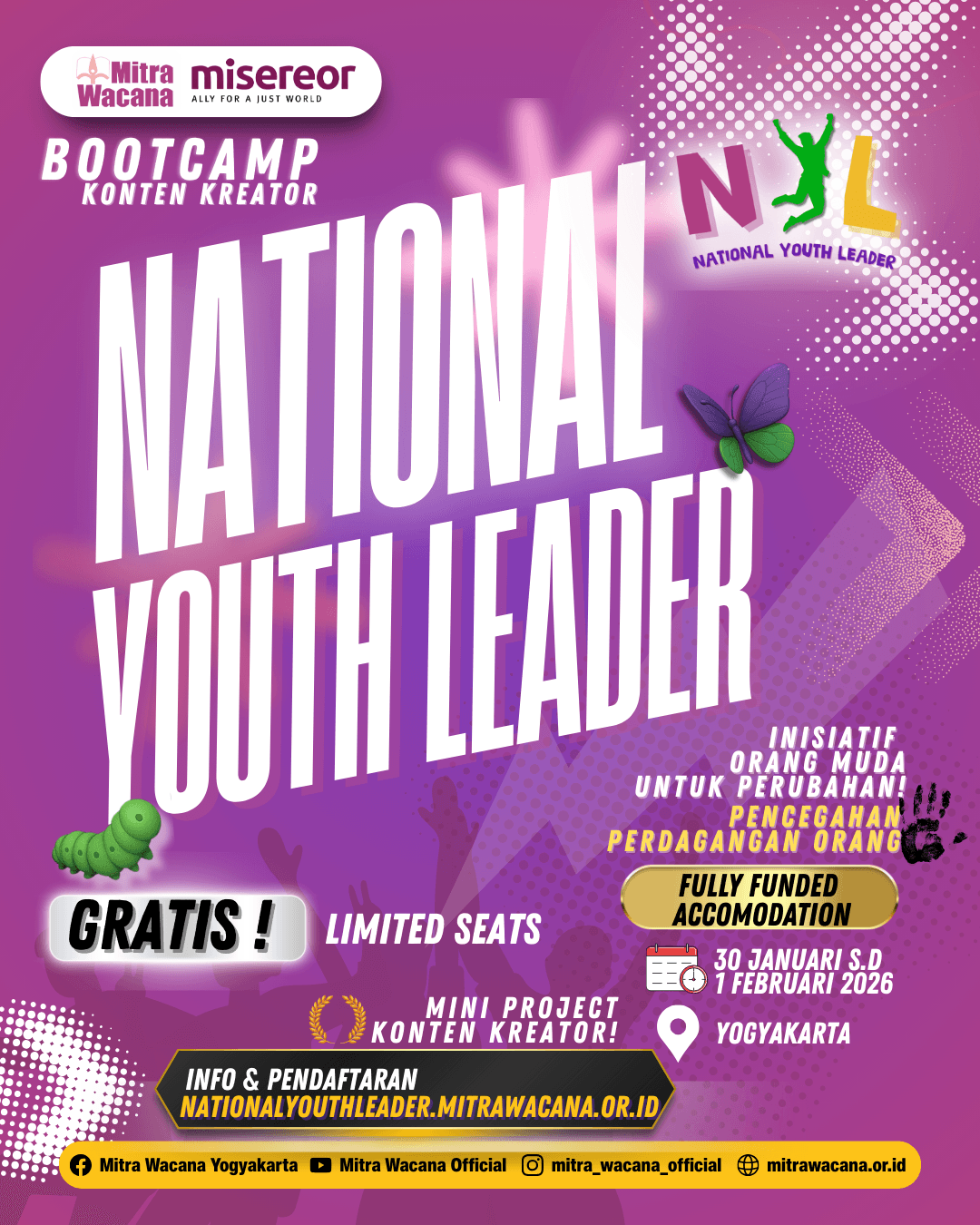Opini
Bahasa Bias Jender dalam Relasi Kuasa Budaya Patriarkhi
Published
11 years agoon
By
Mitra Wacana
Oleh Arif Sugeng Widodo
Manusia dalam berinteraksi memakai bahasa, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua. Dalam berinteraksi bahasa tidak sekedar sebagai alat komunikasi tapi juga menggambarkan apa yang ada dalam pikiran masing-masing orang. Dalam kehidupan sehari hari kadang ada bahasa yang dianggap tidak pantas diucapkan oleh seseorang atau pantas diucapkan seseorang tapi tidak untuk orang-orang tertentu. Dalam hal ini akan dikaji bahasa yang bias jender yang ada dalam kehidupan sehari-hari . Bahasa yang bias jender adalah bahasa yang dipakai atau digunakan dengan mendiskriditkan jenis kelamin tertentu dalam pemakaian suatu bahasa di masyarakat. Bahasa yang bias jender ini masih sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, tidak saja didalam keluarga tapi juga di pasar-pasar, pengajian, bahkan lembaga pendidikan. Bahasa yang bias jender ini sangat berhubungan dengan budaya patriarki yang tertanam kuat di masyarakat.
Dalam budaya Jawa atau bahkan mungkin di beberapa budaya yang lain ditemui bahasa-bahasa yang mendiskriditkan perempuan atau anak perempuan. Beberapa pernyataan yang muncul misalnya; anak perempuan jangan pake celana panjang tidak pantas, anak perempuan jangan bermain pistol-pistolan, anak perempuan jangan main bola gak pantas, anak laki-laki jangan main boneka gak pantas, perempuan itu pantasnya mengurus masalah dapur, sumur dan dapur saja, perempuan pakai rok mini sih pantas diperkosa, perempuan itu tidak usah sekolah tinggi-tinggi toh nantinya ikut suami juga, perempuan itu kalau bicara yang halus jangan bicara yang kasar gak pantas, perempuan itu jangan makan banyak-banyak gak pantas. Laki-laki itu harus tegas biar perempuan tunduk, laki-laki itu harus kasar pada perempuan baru keliatan macho, laki-laki kok nangis kayak perempuan saja, berkelahi itu baru jantan jangan kayak anak perempuan adu mulut aja, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya yang sebenarnya ada dalam kehidupan sehari-hari.
Bahasa yang bias jender tersebut terasa tidak salah karena sering sekali di dengar dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dianggap wajar dan benar adanya. Tapi kalau dilihat lebih dalam betapa bahasa yang bias jender tersebut merendahkan kedudukan perempuan dalam relasinya dengan laki-laki. Bahasa yang bias jender tersebut menunjukkan betapa pandangan terhadap perempuan yang subordinat tersebut masih ada. Bahasa tersebut terus direproduksi dari generasi ke generasi sehingga pengaruh budaya patriarki itu diturunkan juga melalui bahasa selain dalam tindakan-tindakan sosial. Dalam beberapa kasus bahasa yang bias jender kadang dijadikan bahan candaan atau bahkan iklan produk tertentu. Sudut pandang bahwa laki-laki adalah makhluk yang serba baik, benar, kuat dll masih mucul dalam bahasa. Menarik apa yang diungkapkan oleh Brooks; “Grosz menunjukkan bagaimana usaha lacan mengenai seksualitas menyoroti peran krusial permainan bahasa di dalam konstruksi identitas personal. “identitas maskulin dan feminine tidaklah ‘alamiah’, namun hasil retakan retakan di dalam tatanan alamiah, jurang dimana bahasa menyindir dirinya sendiri. Sebagai penanda utama dari yang simbolik, alat kelamin menandai tubuh dan seksualitas laki-laki dan perempuan dalam berbagai cara”(ibid). implikasinya bagi teori feminis adalah penting karena, sebagaimana Grosz mencatat, hal tersebut menyoroti ‘berakhirnya universalis,atau humanis, model seksual netral tentang subjektivitas. Model yang demikian dapat dipandang sebagai alat kelamin sentries, penggunaan kuasa pada representasi dan otoritas bagi model laki-laki’(ibid.). ( Brooks, 2009: 110).
Penggunaan bahasa akan menunjukkan apa yang dipikirkan seseorang dan sejauh mana pengetahuan seseorang. Pikiran manusia juga tidak lepas dari pengetahuan yang didapatnya, pengetahuan itu itupun bisa dikomunikasikan lewat bahasa. Ada cuplikan menarik dari Pinker; “Having a language, of course, is part of what it means to be human, so it is natural to be curious. But having hands that are not occupied in locomotion is even more important to being human, and chances are you would never have made it to the last chapter of a book about the human hand. People are more than curious about language; they are passionate. The reason is obvious . language is the most accessible part of the mind. People want to know about language because they hope this knowledge will lead to insight about human nature”. (Pinker,2011: 419).
Menarik apa yang diungkapkan oleh Kaelan, selain sebagai alat komunikasi bahasa juga berperan dalam menyertai proses berpikir manusia dalam usaha memahami dunia luar, baik secara objektif maupun secara imajinatif. Bahasa juga punya fungsi kognitif dan emotif selain fungsi komunikatif. Bahasa dapat mengantarkan informasi dengan menunjuk sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas mental selain menunjuk pada struktur kebahasaan itu sendiri. Hubungan antara bahasa dan pikiran sudah menjadi bahan kajian para filsuf bahkan sejak Aristoteles. (Kaelan, 2002: 290) Senanda dengan Kaelan, Djojosuroto juga mengungkapkan bahwa bahasa adalah alat atau instrument dari proses berpikir. Bahasa juga bukan alat mati dari pikiran, bahasa mempunyai peran lain dalam kehidupan manusia selain logika. (Djojosuroto, 2006:122)
Kalau dilihat pemakaian bahasa yang bias jender menunjukkan cerminan dari orang yang menggunakannya. Dengan menggunakan bahasa-bahasa yang bias jender maka akan terlihat bagaimana pemikiran dan pengetahuan seseorang tentang relasi kuasa. Apa yang dikatakan itulah apa yang dipikirkan dan apa yang dipikirkan itulah merupakan pengetahuan yang selama ini diperoleh. orang-orang masih banyak yang menggunakan bahasa bias jender karena selama ini bahasa tersebut beredar di masyarakat dan dianggap wajar. Karena dianggap wajar bahasa yang bias jender tersebut dianggap sesuatu yang benar, karena dianggap sesuatu yang benar bahasa tersebut direproduksi sedemikan rupa dan dipakai di dalam berinteraksi dengan orang lain. Adanya pernyataan “perempuan jangan main bola tidak pantas” misalnya menunjukkan bahwa yang pantas dan memang layak main bola adalah laki-laki. Jika ada perempuan main bola berarti hal tersebut sudah mengusik suatu nilai-nilai kepantasan dalam masyarakat. Pada saat sebuah tindakan itu mengusik suatu “tatanan” maka akan ada penilaian lewat pemakaian bahasa, hal tersebutlah yang menyebabkan bahasa yang bias jender itu selalu saja muncul secara berulang. Pemakaian bahasa yang bias jender juga berkaitan dengan tabu, perempuan dianggap tabu melakukan sesuatu jika dianggap di luar nilai-nilai tertentu.
“Karena tabu tidak hanya menyangkut ketakutan terhadap roh gaib, melainkan juga berkaitan dengan sopan santun dan tata karma pergaulan sosial, orang yang tidak ingin dianggap “tidak sopan” akan menghindarkan penggunaan kata-kata tertentu. Dalam masyarakat Indonesia, terutama dalam bahasa daerah, sering dikatakan wanita lebih banyak menghindari penggunaan kata-kata yang berhubungan dengan alat kelamin atau kata-kata “kotor” yang lain. Kata-kata ini seolah-olah ditabukan oleh wanita, atau seolah-olah menjadi monopoli pria.” (Sumarsono dan partana, 2002: 106-107).
Penggunaan kata-kata yang bias jender tidak lepas dari makna apa yang muncul. Sehingga menggunakan suatu kata-kata haruslah hati-hati apakah mengandung unsur-unsur yang merendahkan, melecehkan atau mendiskriminasikan terhadap sesuatu hal. Di kelompok tertentu bisa jadi pemakaian suatu bahasa yang bias jender bisa dimaklumi tapi di kelompok yang lain pemakaian bahasa bias jender bisa dianggap sebagai penghinaan yang serius terhadapa suatu kelompok. Sehingga penting untuk memperhatikan dimana suatu kata itu dipergunakan dan untuk apa digunakan, apakah berdampak secara sosial apa tidak? Karena pemakaian bahasa yang tidak tepat bisa mengacaukan situasi sosial di suatu masyarakat yang pada akhirnya bisa menimbulkan konflik berkepanjangan gara-gara sebuah pernyataan.
Pemakaian bahasa yang bias gender tidak lepas dari relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut juga mempengaruhi pola bahasa yang dipakai saat terjadi relasi antara laki-laki dan perempuan. Sehingga menarik untuk sedikit menyinggung mengenai dominasi maskulin dalam kehidupan sehari-hari. Karena hal tersebut berkaitan erat dengan pemakaian bahasa yang bias jender. Pemakaian bahasa yang bias jender tidak saja terjadi di satu atau dua wilayah tapi terhadi hampir di semua wilayah yang sistem patriarkinya cukup kental. Adanya analisis antropologis yang dilakukan oleh Pierre Bourdieu mengenai dominasi maskulin sedikit banyak akan membantu memberikan gambaran bagaimana bahasa yang bias jender itu terbentuk di dalam masyarakat.
Referensi
Brooks, Ann, 2009, Posfeminisme and Cultural Studies (Sebuah Pengantar Paling Komprehensif), Jalasutra, Yogyakarta.
Djojosuroto, kinayati, 2006, Filsafat Bahasa, Penerbit pustaka, Yogyakarta.
Kaelan, 2002, Filsafat bahasa (masalah dan perkembangannya), paradigma, Yogyakarta.
Pinker, Steven, 2011, The Language Instinct, HerperCollins Publishers, New York.
Sumarsono dan Partana, 2002, Sosiolinguistik, Sabda, Yogyakarta.
You may like
Opini
Merevolusi Cara Kita Melihat Tugas Kuliah
Published
3 weeks agoon
29 December 2025By
Mitra Wacana

Nurisa Cahya Artika Farah,Mahasiswi semester 3 Program Studi Tadris (Pendidikan) Bahasa Indonesia, Fakultas Adab dan Bahasa, Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta.
Di dunia perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menjadi individu yang mandiri, kritis, dan kreatif dalam menghadapi berbagai tantangan akademik. Salah satu tantangan tersebut adalah tugas kuliah yang diberikan oleh dosen sebagai proses pembelajaran. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak mahasiswa justru menganggap tugas kuliah sebagai beban yang membebani pikiran. Mahasiswa lebih fokus pada nilai akhir ketimbang proses belajar yang seharusnya memperkaya pengetahuan dan keterampilan. Fenomena ini menjadi gambaran bahwa sebagian mahasiswa masih memandang tugas secara sempit, tanpa menyadari bahwa melalui tugas inilah kemampuan berpikir kritis serta tanggung jawab perkuliahan dapat terasah.
Banyak kalangan mahasiswa mengeluh akan tugas kuliah yang diberikan, mereka memandangnya sebagai beban yang menumpuk dan hanya sebatas untuk mendapatkan nilai, bukan proses pembelajaran. Hal ini membuat motivasi belajar menurun yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, seperti kurangnya minat, kesulitan konsentrasi, masalah pribadi, maupun kualitas hasil tugas yang tidak mencerminkan pemahaman sebenarnya. Padahal, esensi pendidikan tinggi bukan sebatas mengerjakan tugas, namun membangun cara berpikir kritis dan kreatif mahasiswa. Karena itu, saatnya mahasiswa merevolusi cara pandang terhadap tugas yang dianggap beban menjadi proses pembelajaran yang bermakna.
Perkuliahan mahasiswa sebenarnya tidak hanya belajar dari penjelasan dosen, tetapi juga dari proses mengerjakan tugas. Hal ini sejalan dengan Teori Konstruktivisme yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun dari individu berdasarkan pengalaman dan pemahaman. Seperti halnya dalam pemberian tugas kuliah ini mahasiswa tidak hanya menerima ilmu dari dosen, tetapi juga membentuk pemahaman sendiri melalui pengalaman belajar sebelumnya. Dalam konteks ini, tugas kuliah bukanlah tujuan akhir, tetapi sebagai sarana untuk membangun pemahaman terhadap suatu konsep. Misalnya, ketika mahasiswa diminta menulis esai, mereka tidak hanya terpaku dengan teori yang sudah ada, tetapi juga menyusun gagasan atau ide pribadi berdasarkan pemahaman konseptual dan berpikir kritis. Dengan demikian, tugas menjadi penghubung antara pengetahuan dan penerapan.
Namun, faktanya di lapangan masih banyak mahasiswa yang memandang tugas sebagai sesuatu yang dipaksakan untuk semata-mata demi nilai. Hal ini sejalan dengan rendahnya motivasi dalam diri berdasarkan teori Self-Determination. Mahasiswa akan termotivasi jika memiliki kebebasan pilihan dalam menyelesaikan tugas (autonomi), merasa mampu mengerjakan (kompetensi), dan merasa bahwa tugas memiliki hubungan dengan kehidupan mereka (keterhubungan). Dengan demikian, ketika diberi tugas yang memberikan kebebasan, kemampuan, serta keterhubungan, mahasiswa akan melihat tugas bukan sebagai beban, melainkan sebagai bentuk pengembangan diri.
Selain itu, konsep belajar bermakna dari David Ausubel juga relevan dalam konteks ini. Dalam perkuliahan, hal ini berarti tugas yang diberikan seharusnya berasal dari struktur pemikiran yang telah dimiliki mahasiswa. Misalnya, tugas proyek yang menuntut mahasiswa mengaitkan teori dengan pengalaman pribadi. Ketika mahasiswa menemukan keterkaitan tersebut, proses belajar menjadi bermakna. Mereka tidak sedang mengerjakan tugas dosen melainkan sedang menemukan diri dalam proses pembelajaran.
Pandangan teori humanistik juga memperkuat gagasan ini. Dalam pandangan ini, mahasiswa dipandang sebagai individu yang unik dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Tugas kuliah, seharusnya menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengekspresikan diri, mengeksplorasi nilai-nilai pribadi, dan mengembangkan potensi secara utuh. Tugas tidak hanya mengukur hasil akhir berupa angka, tetapi juga menilai proses berpikir, kreativitas, den refleksi diri mahasiswa.
Sebagai mahasiswa, saya kerap melihat beberapa mahasiswa bahwa tugas baru benar-benar dipahami maknanya setelah dikerjakan, bukan saat materi disampaikan oleh dosen. Dari tugaslah mahasiswa belajar berpikir kritis, mampu mengelola waktu, dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa tugas kuliah sejatinya memiliki peran penting dalam membentuk kualitas mahasiswa, asalkan dipahami dan dijalani dengan cara pandang yang tepat.
Masalahnya sistem pendidikan kita masih berorientasi pada hasil bukan proses. Banyak mahasiswa mengerjakan tugas hanya untuk mendapatkan nilai bukan karena ingin memahami makna apa yang mereka pelajari. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan paradigma, baik dari pihak dosen maupun mahasiswa. Merevolusi cara pandang terhadap tugas kuliah berarti menempatkan kembali tugas sebagai bagian dari proses pembelajaran bukan sebagai beban mahasiswa. Ketika mahasiswa mulai melihat tugas sebagai ruang pengembangan diri mereka akan lebih bersemangat, produktif, dan berdaya saing. Tak hanya mahasiswa, dosen pun akan lebih mudah menilai kualitas pemahaman mahasiswa. Dengan demikian, revolusi ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hasil belajar, tetapi juga membentuk generasi mahasiswa yang berpikir kritis, reflektif, dan siap menghadapi tantangan di kehidupan nyata. Hal yang paling berharga dari tugas kuliah bukan hanya tentang nilai yang berupa angka melainkan proses belajar yang akan menambah pemahaman.