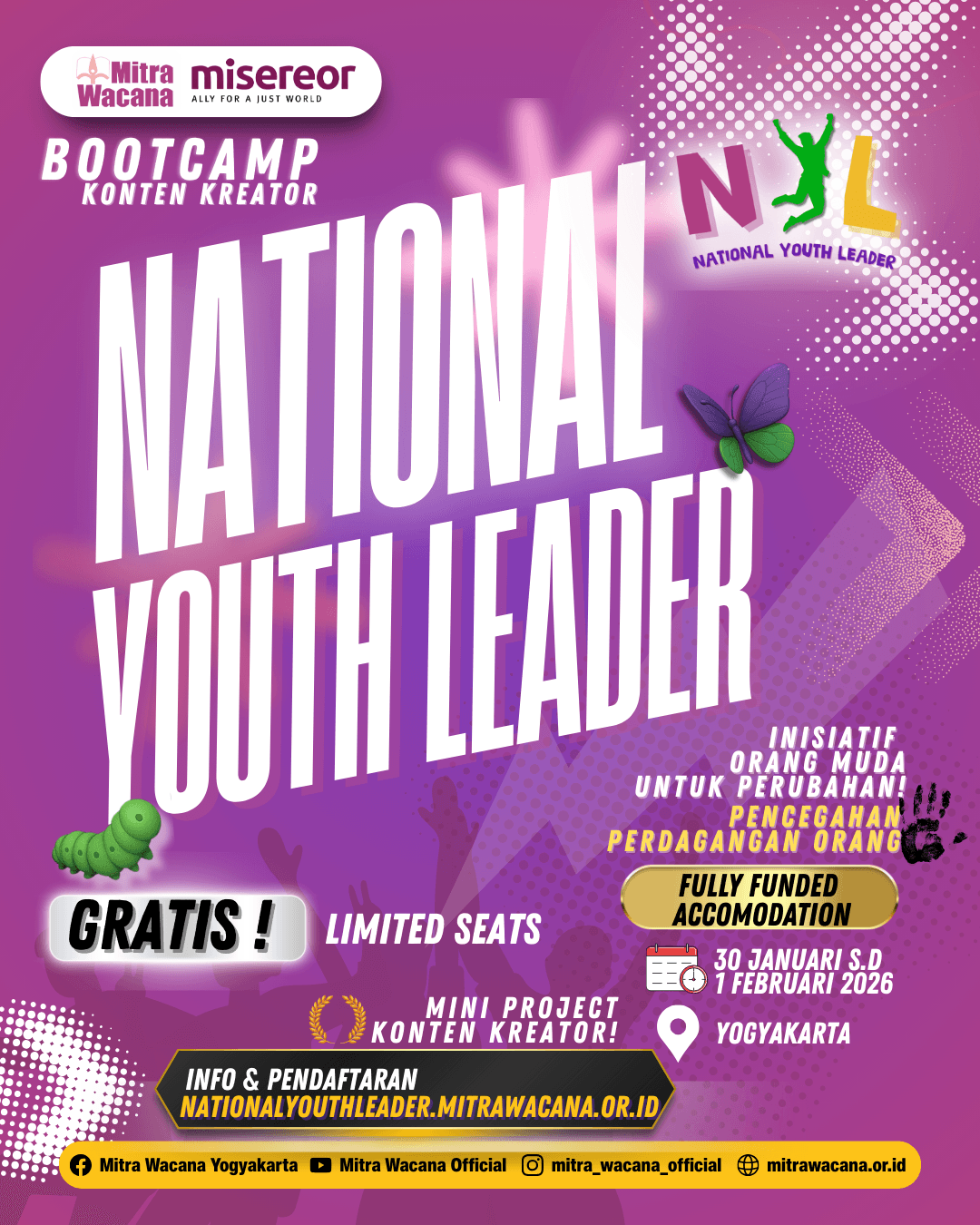Opini
Mengkaji RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri
Published
10 years agoon
By
Mitra Wacana

Nadlroh As Sariroh
Oleh Nadlroh As Sariroh
(Pengurus Nasional Koalisi Perempuan Indonesia Kelompok Kepentingan Buruh Migran)
Pada saat ini diperkirakan jumlah buruh migran Indonesia di luar negeri sudah mencapai angka jutaan orang. Di tahun 2011, berdasarkan data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Ada sekitar 3,8 – 4 juta pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Di 2011 saja ada sekitar 581.081 pekerja migran Indonesia yang berangkat ke luar negeri. Di 2012, 5 negara tujuan terbesar adalah Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Arab Saudi. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga (lihat data BNP2TKI di 2010, 2011). Ada penurunan sedikit di 2012 namun angka pekerja “informal” masih signifikan. Berdasarkan data di tahun yang sama di 2011, Bank Indonesia menginformasikan bahwa pekerja migran mendatangkan US$ 6,7 milyar dalam bentuk remitansi ke Indonesia.
Sebagian besar perempuan buruh migran bekerja di sektor pekerja rumah tangga dan sisanya bekerja di sektor perkebunan, konstruksi, manufaktur, kesehatan dan pelaut. Semuanya dalam kategori buruh rendahan. Berdasarkan basis sosialnya, sebagian besar berasal dari pedesaan dengan tingkat pendidikan yang rendah. Kondisi ini menjauhkan mereka dari akses informasi dan memperbesar kerentanan mereka terhadap eksploitasi. Perempuan buruh migran mengalami diskriminasi dimanapun tempatnya. Di dalam negeri perempuan buruh migran diperlakukan sebagai komoditi dan warga negara kelas dua. Perempuan buruh migran mendapatkan perlakuan yang diskriminatif mulai dari saat perekrutan, di penampungan, pemberangkatan maupun saat kepulangan.
Minimnya instrumen perlindungan juga mejadi pemicu maraknya permasalahan yang menimpa perempuan buruh migran. Tak terhitung berapa perempuan buruh migran telah menjadi korban: trafficking (perdagangan manusia), mati, diperkosa, cacat, dianiaya, disiksa, disekap, gaji tidak dibayar, PHK dan lain sebaginya. Berbagai kasus yang menimpa para perempuan buruh migran mencerminkan betapa buramnya nasib perempuan buruh migran. Tersiksa di luar negeri, teraniaya dalam negeri sendiri. Untuk itu diperlukan organisasi yang kuat bagi perempuan buruh migran, agar bisa menjadi wadah dan tempat saling komunikasi antar buruh migran dalam mengatasi kondisi buruk yang dialami oleh buruh migran, mantan buruh migran, dan anggota keluarganya.
Berdasarkan pengalaman perempuan buruh migran menunjukkan bahwa, Pemerintah Indonesia belum serius melakukan pengawasan pada Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) “nakal” yang : memberikan informasi menyesatkan tentang pekerjaan perempuan buruh migran di negara tujuan; praktek percaloan dalam proses perekrutan dan penempatan; mengambil keuntungan dengan menarik biaya administrasi, pengurusan dokumen, penampungan dan pelatihan di luar pembiayaan resmi negara. Disamping itu, sebagian besar Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) masih kurang proaktif dalam memberikan perlindungan dan bantuan hukum bagi buruh migran Indonesia, yang menjadi korban eksploitasi dan kekerasan di negara tempat bekerja.
Sampai saat ini masih belum terlihat kesungguhan pemerintah dalam mengharmonisasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Konvensi Internasional 1990) ke dalam revisi Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU No 39 Tahun 2004), kecenderungan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memperkuat peran PJTKI serta Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) masih terlihat , dan justru melemahkan peran pemerintah dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan buruh migran sebagai warga negara Indonesia.
Selain itu, pemerintah belum memberikan perlindungan sosial yang komprehensif bagi perempuan buruh migran dan keluarganya, terutama terkait berbagai bantuan sosial dan jaminan sosial bagi anak-anak yang ditinggalkannya di Indonesia, kejelasan status perkawinan buruh migran yang kawin di negara lain, kejelasan status kewarganegaraan dan pemenuhan Hak Anak bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan buruh migran yang dilakukan di Luar Negeri. Hal ini harus menjadikan pertimbangan dalam merumuskan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja ke Luar Negeri yang sedang dibahas oleh DPR. Untuk itu dalam RUU Perlindungan terhadap buruh migran Indonesia hendaknya memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal berikut ini:
• Perlindungan Buruh migran Indonesia ditujukan bagi buruh migran laki-laki dan buruh migran perempuan beserta keluarganya;
• Memperhatikan situasi dan kebutuhan khusus BMI perempuan yang bekerja di sektor domestik dan rentan terhadap kekerasan dan pelanggaran HAM serta tidak dilindungi oleh hukum;
• Memperhatikan situasi dan kebutuhan khusus buruh migran perempuan di berbagai sektor (sebagaimana tercantum di dalam UU terkait);
• Perlindungan BMI perempuan harus ditujukan untuk mencegah dan memberhentikan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender (termasuk dan tidak terbatas pada pelecehan seksual, perkosaan, perdagangan perempuan);
• Untuk kepentingan perlindungan perempuan harus ada pembatasan usia minimal (18 tahun keatas) untuk bekerja di luar negeri dan pencegahan terhadap segala bentuk pemalsuan/informasi yang salah terkait dengan identitas diri calon BMI;
• Kerentanan buruh migran perempuan dan anak perempuan terhadap kekerasan (fisik, psikis, seksual, ekonomi), eksploitasi (jenis pekerjaan, waktu kerja, seksual) dan diskriminasi (pangan yang tidak layak, kesempatan beribadah, hak atas privasi);
• Diskriminasi di bidang kesehatan sebelum keberangkatan, seperti sterilisasi paksa, pemeriksaan HIV/AIDS paksa. Pada saat sedang bekerja di luar negeri, BMI menghadapi minimnya akses terhadap layanan kesehatan;
• Sulitnya akses buruh migran perempuan terhadap pencatatan perkawinan (antar sesama buruh migran Indonesia, dengan buruh migran dari negara lain ataupun dengan warga negara setempat) sehingga mereka tidak memiliki dokumen bukti perkawinan yang sah;
• Anak-anak yang dilahirkan dari pasangan yang tidak memiliki dokumen bukti perkawinan tidak memiliki kejelasan status kewarganegaraan yang mengakibatkan pemenuhan hak dasar anak tidak terpenuhi (Akte kelahiran, pendidikan, kesehatan dan jaminan perlindungan sosial lainnya);
• Banyaknya kasus-kasus pemalsuan identitas diri anak (penambahan usia) sehingga anak-anak perempuan menjadi pekerja migran, terutama pekerja migran di sektor domestik dan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak lainnya;
• Rendahnya perlindungan hukum dan fasilitas bantuan hukum bagi BMI perempuan dan anaknya yang mengalami permasalahan hukum.
• Sulitnya akses informasi tentang hak-hak buruh migran dan keluarganya, proses mekanisme perekrutan, penampungan, pelatihan, penempatan, dan pemulangan BMI, peraturan perundang-undangan terkait perlindungan buruh migran, keberadaan dan situasi BMI;
• Penghasilan buruh migran belum terkelola dengan baik oleh keluarganya sehingga penghasilan buruh migran kurang berkontribusi terhadap kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan;
• Rendahnya akses bantuan hukum bagi keluarga BMI untuk menghadapi kasus hukum yang menimpa buruh migran di luar negeri.
• Keluarga BMI yang berada di negara dimana BMI bekerja
• Ketidakjelasan perlindungan hukum bagi perkawinan antar warga negara
• Adanya stigmatisasi pelabelan negatif sebagai penduduk atau keluarga ilegal
• Masyarakat berhak berpartisipasi untuk memonitor proses mekanisme perekrutan, penampungan, pelatihan, penempatan, dan pemulangan BMI, serta untuk perumusan dan pengambilan keputusan dalam pembuatan dan implementasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan buruh migran.
*Tulisan ini dimuat dalam buletin Mitra Media
You may like
Opini
Merevolusi Cara Kita Melihat Tugas Kuliah
Published
3 weeks agoon
29 December 2025By
Mitra Wacana

Nurisa Cahya Artika Farah,Mahasiswi semester 3 Program Studi Tadris (Pendidikan) Bahasa Indonesia, Fakultas Adab dan Bahasa, Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta.
Di dunia perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menjadi individu yang mandiri, kritis, dan kreatif dalam menghadapi berbagai tantangan akademik. Salah satu tantangan tersebut adalah tugas kuliah yang diberikan oleh dosen sebagai proses pembelajaran. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak mahasiswa justru menganggap tugas kuliah sebagai beban yang membebani pikiran. Mahasiswa lebih fokus pada nilai akhir ketimbang proses belajar yang seharusnya memperkaya pengetahuan dan keterampilan. Fenomena ini menjadi gambaran bahwa sebagian mahasiswa masih memandang tugas secara sempit, tanpa menyadari bahwa melalui tugas inilah kemampuan berpikir kritis serta tanggung jawab perkuliahan dapat terasah.
Banyak kalangan mahasiswa mengeluh akan tugas kuliah yang diberikan, mereka memandangnya sebagai beban yang menumpuk dan hanya sebatas untuk mendapatkan nilai, bukan proses pembelajaran. Hal ini membuat motivasi belajar menurun yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, seperti kurangnya minat, kesulitan konsentrasi, masalah pribadi, maupun kualitas hasil tugas yang tidak mencerminkan pemahaman sebenarnya. Padahal, esensi pendidikan tinggi bukan sebatas mengerjakan tugas, namun membangun cara berpikir kritis dan kreatif mahasiswa. Karena itu, saatnya mahasiswa merevolusi cara pandang terhadap tugas yang dianggap beban menjadi proses pembelajaran yang bermakna.
Perkuliahan mahasiswa sebenarnya tidak hanya belajar dari penjelasan dosen, tetapi juga dari proses mengerjakan tugas. Hal ini sejalan dengan Teori Konstruktivisme yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun dari individu berdasarkan pengalaman dan pemahaman. Seperti halnya dalam pemberian tugas kuliah ini mahasiswa tidak hanya menerima ilmu dari dosen, tetapi juga membentuk pemahaman sendiri melalui pengalaman belajar sebelumnya. Dalam konteks ini, tugas kuliah bukanlah tujuan akhir, tetapi sebagai sarana untuk membangun pemahaman terhadap suatu konsep. Misalnya, ketika mahasiswa diminta menulis esai, mereka tidak hanya terpaku dengan teori yang sudah ada, tetapi juga menyusun gagasan atau ide pribadi berdasarkan pemahaman konseptual dan berpikir kritis. Dengan demikian, tugas menjadi penghubung antara pengetahuan dan penerapan.
Namun, faktanya di lapangan masih banyak mahasiswa yang memandang tugas sebagai sesuatu yang dipaksakan untuk semata-mata demi nilai. Hal ini sejalan dengan rendahnya motivasi dalam diri berdasarkan teori Self-Determination. Mahasiswa akan termotivasi jika memiliki kebebasan pilihan dalam menyelesaikan tugas (autonomi), merasa mampu mengerjakan (kompetensi), dan merasa bahwa tugas memiliki hubungan dengan kehidupan mereka (keterhubungan). Dengan demikian, ketika diberi tugas yang memberikan kebebasan, kemampuan, serta keterhubungan, mahasiswa akan melihat tugas bukan sebagai beban, melainkan sebagai bentuk pengembangan diri.
Selain itu, konsep belajar bermakna dari David Ausubel juga relevan dalam konteks ini. Dalam perkuliahan, hal ini berarti tugas yang diberikan seharusnya berasal dari struktur pemikiran yang telah dimiliki mahasiswa. Misalnya, tugas proyek yang menuntut mahasiswa mengaitkan teori dengan pengalaman pribadi. Ketika mahasiswa menemukan keterkaitan tersebut, proses belajar menjadi bermakna. Mereka tidak sedang mengerjakan tugas dosen melainkan sedang menemukan diri dalam proses pembelajaran.
Pandangan teori humanistik juga memperkuat gagasan ini. Dalam pandangan ini, mahasiswa dipandang sebagai individu yang unik dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Tugas kuliah, seharusnya menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengekspresikan diri, mengeksplorasi nilai-nilai pribadi, dan mengembangkan potensi secara utuh. Tugas tidak hanya mengukur hasil akhir berupa angka, tetapi juga menilai proses berpikir, kreativitas, den refleksi diri mahasiswa.
Sebagai mahasiswa, saya kerap melihat beberapa mahasiswa bahwa tugas baru benar-benar dipahami maknanya setelah dikerjakan, bukan saat materi disampaikan oleh dosen. Dari tugaslah mahasiswa belajar berpikir kritis, mampu mengelola waktu, dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa tugas kuliah sejatinya memiliki peran penting dalam membentuk kualitas mahasiswa, asalkan dipahami dan dijalani dengan cara pandang yang tepat.
Masalahnya sistem pendidikan kita masih berorientasi pada hasil bukan proses. Banyak mahasiswa mengerjakan tugas hanya untuk mendapatkan nilai bukan karena ingin memahami makna apa yang mereka pelajari. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan paradigma, baik dari pihak dosen maupun mahasiswa. Merevolusi cara pandang terhadap tugas kuliah berarti menempatkan kembali tugas sebagai bagian dari proses pembelajaran bukan sebagai beban mahasiswa. Ketika mahasiswa mulai melihat tugas sebagai ruang pengembangan diri mereka akan lebih bersemangat, produktif, dan berdaya saing. Tak hanya mahasiswa, dosen pun akan lebih mudah menilai kualitas pemahaman mahasiswa. Dengan demikian, revolusi ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hasil belajar, tetapi juga membentuk generasi mahasiswa yang berpikir kritis, reflektif, dan siap menghadapi tantangan di kehidupan nyata. Hal yang paling berharga dari tugas kuliah bukan hanya tentang nilai yang berupa angka melainkan proses belajar yang akan menambah pemahaman.